Tindakan Radikal untuk Menyelamatkan Ekosistem Mangrove Indonesia

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Pada tahun 2022, saya mengunjungi Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam rangka pendampingan masyarakat pascabencana. Desa yang berada di wilayah pesisir itu memiliki hutan mangrove yang cukup luas. Namun, suatu ketika, hadirlah investasi ke desa tersebut dalam wujud budidaya udang vaname dengan narasi penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran investasi tambak intensif udang vaname ini mengharuskan adanya lahan yang dipersiapkan yang berada di lokasi mangrove.
Rayuan peningkatan ekonomi membuat masyarakat setempat, meskipun sebenarnya tidak semua sepakat, berbondong-bondong menyerahkan lahannya dan dengan sukarela melakukan penebangan terhadap mangrove yang sudah tumbuh bertahun-tahun. Belakangan, proyek budidaya udang tersebut tidak lagi berlanjut karena persoalan administrasi dan lain sebagainya. Namun, mangrove telah hancur. Apa mau dikata, investasi telah gagal dan mangrove di Desa Lombonga pun telah hilang.
Ini hanyalah salah satu kisah penghancuran mangrove yang pernah saya saksikan. Di berbagai wilayah lain di Indonesia, saya juga mendengar banyak kasus yang sama, dimana atas nama pengembangan ekonomi, jutaan hektare ekosistem mangrove dihancurkan. Saya menyebutnya ekosistem karena mangrove bukan hanya sebatas hutan atau pepohonan, melainkan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Kesehatan ekosistem mangrove sangat menentukan keberlangsungan hidup berbagai spesies yang hidup di dalam dan sekitarnya.
Degradasi Ekosistem Mangrove dan Berbagai Penyebabnya
Ada banyak sekali manfaat yang diberikan oleh hutan mangrove bagi kehidupan manusia, salah satunya sebagai pelindung dari bencana alam. Gempa Mapaga di Sulawesi Tengah merupakan salah satu bukti bagaimana mangrove telah menyelamatkan banyak manusia. Mangrove juga memiliki peran sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang banyak dihasilkan oleh manusia. Namun sayangnya, mangrove yang telah menjadi pelindung itu justru dikhianati dengan ditebang.
Tidak hanya di Lombonga, hutan mangrove di berbagai wilayah di Indonesia menghadapi ancaman setiap tahunnya. Walhi melaporkan bahwa degradasi mangrove terus terjadi setidaknya di Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Menurut Data Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM), ada sekitar 700.000 hektare hutan mangrove yang mengalami deforestasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kerusakan mangrove tercepat di dunia.
“Perusakan” mangrove paling sering terjadi akibat aktivitas manusia (antropogenik), termasuk konversi hutan mangrove menjadi lahan budidaya perikanan atau tambak atau yang sering disebut sebagai ‘revolusi biru’. Hal ini pula yang terjadi di Desa Lombonga. Masyarakat dan pemerintah desa tergiur oleh iming-iming pengembangan ekonomi sehingga melanggengkan penghancuran mangrove demi budidaya tambak.
Selain itu, kerusakan hutan mangrove juga sering diakibatkan oleh penebangan liar seperti yang terjadi di Kalimantan. Masyarakat melakukan penebangan serta pembakaran puluhan juta kilogram pohon bakau untuk dijadikan arang. Tingkat pendapatan yang rendah menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan penebangan mangrove dan beralih ke aktivitas perekonomian lain yang dianggap dapat menghasilkan pemasukan dengan lebih cepat.
Menurut saya, salah satu hal mendasar yang menjadi faktor degradasi mangrove adalah model pendidikan di Indonesia yang tidak berbasis lingkungan. Pendidikan di Indonesia menurut saya tidak membawa kita untuk memperkuat relasi dengan alam. Pendidikan kita seringkali hanya menjadi basis untuk meningkatkan ekonomi; menjadi alat yang dipergunakan untuk mengeksploitasi dan menguasai alam. Pendidikan kita dirancang untuk melayani kebutuhan industri dengan seperangkat keterampilan yang diajarkan untuk menguasai alat-alat taktis untuk keperluan eksplorasi alam dan bukan menjadi alat untuk memahami alam dan lingkungan. Hal inilah yang akhirnya menjauhkan manusia dari alam, dan menjadikan manusia sebagai monster bagi alam, yang salah satu wujudnya berupa penghancuran mangrove.
Perlu Tindakan Radikal
Di tengah masifnya kerusakan ekosistem mangrove, ditambah pemanasan global yang mengakibatkan krisis iklim, perlu ada upaya radikal yang tidak sebatas pada anjuran atau aksi-aksi formalitas belaka. Salah satunya melalui reformasi pendidikan.
Reformasi harus menyentuh aspek mendasar pendidikan. Dalam hal ini, saya mengusulkan agar lingkungan menjadi orientasi utama pendidikan. Tanah dan semua yang meliputinya harus menjadi basis dan pusat pedagogi. Pendidikan harus bertujuan untuk membawa manusia memiliki ikatan dan relasi yang kuat dengan alam. Spiritualitas alam harus menjadi bagian dari sistem pendidikan dasar kita. Hubungan seperti inilah yang dimiliki oleh Masyarakat Adat dengan tanahnya sehingga tak heran jika peran mereka dalam melestarikan alam sangat besar.
Kedua, di tingkat kebijakan dan tata kelola, perlu ada langkah sistematis yang serius dan radikal dalam upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia. Merujuk data WALHI, sejauh ini hanya sekitar 33.000 hektare (5,5 %) mangrove Indonesia yang telah direhabilitasi, jauh dari target pemerintah yaitu 600.000 hektare hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan lemahnya atau tidak efektifnya kebijakan dan program-program terkait perlindungan mangrove yang disediakan pemerintah. Banyak kebijakan yang saling bertabrakan dan tumpang tindih satu sama lain sehingga menyebabkan upaya yang dilakukan kurang berdampak. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara serius memperbaiki dan meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove.
Ketiga, perlu dipikirkan solusi pemanfaatan mangrove jangka menengah dan panjang bagi masyarakat. Pengalaman di Desa Lombonga yang saya sampaikan di awal tulisan terjadi karena lapangan pekerjaan masyarakat pesisir yang minim, sementara hasil dari menangkap ikan semakin susut. Selain perubahan iklim, menyusutnya pendapatan nelayan juga dapat terjadi karena degradasi lingkungan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pemerintah mesti menghadirkan alternatif perekonomian bagi masyarakat pesisir yang dapat mengurangi tekanan pada hutan mangrove.
Keempat, perlu ada upaya pemulihan berbasis komunitas yang terintegrasi. Rehabilitasi dan restorasi mangrove tidak boleh berhenti pada aksi-aksi seremonial belaka. Menurut pengalaman saya, ada banyak kasus dimana penanaman mangrove hanya melibatkan komunitas untuk dokumentasi semata. Tidak ada tindakan yang berkesinambungan, termasuk dalam memantau pertumbuhan mangrove. Selain itu, penanaman yang dilakukan juga seringkali tidak sesuai dengan karakteristik lokasi dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat merusak mangrove. Akibatnya, setelah proses penanaman, hanya sedikit atau bahkan tidak ada satupun mangrove yang hidup atau tumbuh. Untuk itu, masyarakat harus diorganisir, ditransformasi kesadarannya, dan ditingkatkan kapasitasnya dalam menjaga ekosistem mangrove. Dalam semua upaya ini, komunitas lokal harus dilibatkan sebagai aktor utama.
Editor: Abul Muamar
Terbitkan thought leadership dan wawasan berharga Anda bersama Green Network Asia, pelajari Panduan Artikel Opini GNA.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Martin adalah peneliti di SHEEP Indonesia Institute dan mahasiswa pascasarjana di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada.


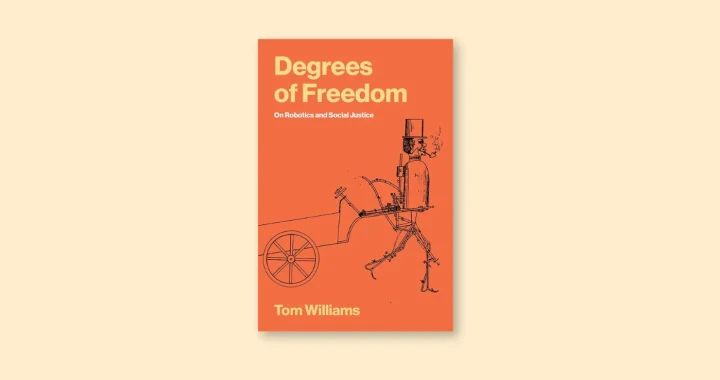 Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams
Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams  Memperkuat Penanggulangan Campak di Indonesia
Memperkuat Penanggulangan Campak di Indonesia  Gambut di Cekungan Kongo Mulai Lepaskan Karbon Purba
Gambut di Cekungan Kongo Mulai Lepaskan Karbon Purba  Pemerintah Tetapkan Larangan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia 16 Tahun
Pemerintah Tetapkan Larangan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia 16 Tahun  Pergeseran Aktivisme Iklim Kaum Muda di Berbagai Negara
Pergeseran Aktivisme Iklim Kaum Muda di Berbagai Negara  Mahkamah Agung India Tetapkan Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar
Mahkamah Agung India Tetapkan Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar