Degradasi Ekosistem Gambut: Bagaimana Mengatasinya?

Rawa gambut di Taman Nasional Sebangau, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. | Foto: Mankdhay Rahman di Wikimedia Commons.
Kehidupan di Bumi turut ditopang oleh keberadaan lahan basah yang sehat, termasuk gambut. Gambut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan rumah dan makanan bagi berbagai satwa liar, dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Namun, ekosistem gambut di Indonesia mengalami degradasi dan penyusutan dalam beberapa dekade terakhir. Lalu, bagaimana mengatasi permasalahan ini?
Ekosistem Gambut dan Fungsinya
Lahan gambut adalah lahan basah dengan lapisan tanah berair yang terbentuk dari akumulasi dan penimbunan bahan-bahan organik berasal dari detritus tumbuhan seperti serasah, ranting pohon, akar pohon, dan kayu yang tidak membusuk secara sempurna. Dibandingkan tanah mineral, lahan gambut memiliki tingkat daya serap air yang jauh lebih tinggi sehingga penting dalam mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. Di banyak tempat, lahan gambut biasanya identik dengan air bersih dengan iklim yang basah.
Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ekosistem gambut terluas di dunia. Lahan gambut tropis di Indonesia bahkan merupakan yang terluas di dunia. Pantau Gambut mencatat, luas lahan gambut tropis Indonesia mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar terutama di tiga pulau besar, yaitu Sumatera (5,8 juta hektare), Kalimantan (4,5 juta hektare), dan Papua (3 juta hektare). Menurut FAO, lahan gambut tropis mencakup 8 persen dari total lahan gambut di dunia.
Ekosistem gambut merupakan habitat vital bagi banyak spesies flora dan fauna dan menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Gambut juga memberikan jasa lingkungan yang sangat penting seperti menjaga kualitas udara dan kesehatan tanah secara keseluruhan. Selain itu, lahan gambut juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Degradasi dan Dampaknya
Degradasi lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia telah merambah ke seluruh bentang alam, tak terkecuali lahan gambut. Sebuah penelitian mengungkap bahwa 6 juta hektare lahan gambut di Indonesia mengalami degradasi.
Pantau Gambut mencatat alih fungsi lahan gambut menjadi area perkebunan dan industri sebagai ancaman terbesar terhadap ekosistem gambut di Indonesia. Kurangnya pemahaman dan tanggung jawab akan kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong maraknya alih fungsi lahan gambut. Proyek lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang mengubah bentang gambut menjadi sawah dan akhirnya menjadi proyek gagal, adalah salah satu contoh alih fungsi lahan gambut terbesar yang pernah terjadi.
Lalu apa dampaknya? Degradasi ekosistem gambut akan menyebabkan terlepasnya emisi karbon di dalam gambut serta berkurangnya biomassa di atas gambut yang akan semakin meningkatkan suhu Bumi. Kerusakan lahan gambut akan mendatangkan bencana bagi semua orang, namun masyarakat lokal menjadi pihak yang paling terdampak, seperti kabut asap dan banjir. Lahan gambut yang rusak juga berarti terancamnya kehidupan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Rencana Aksi Nasional
Pengelolaan ekosistem gambut merupakan bagian integral dalam pembangunan rendah karbon dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan target restorasi lahan gambut seluas 3,44 juta hektare pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah meluncurkan strategi dan rencana aksi nasional untuk mengelola ekosistem gambut, yakni:
- Memperkuat kerangka regulasi, kebijakan dan perencanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan.
- Memperkuat ketersediaan dan manajemen data dan informasi serta pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan.
- Memperkuat kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan.
- Meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat.
- Memperkuat penegakan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan.
- Meningkatkan skema pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan.
Pelibatan Masyarakat Adalah Kunci
Di tengah perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana dan ancaman lainnya, pemulihan lahan gambut dan pengelolaannya yang berkelanjutan menjadi suatu hal yang mendesak. Pemulihan lahan gambut memerlukan pendekatan komprehensif dengan langkah yang tepat, mulai dari pemetaan hingga bentuk restorasi yang diperlukan, yang sekaligus mendukung ekonomi masyarakat lokal.
Untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal, pendekatan paludikultur dapat menjadi salah satu pilihan. Paludikultur merupakan metode budidaya tanaman di lahan gambut dengan cara mempertahankan kondisi aslinya dan membasahi kembali lahan yang telah kering. Metode ini membantu memulihkan gambut yang rusak dengan menanaminya kembali dengan tanaman lokal. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengembangkan ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu dalam perlindungan lahan gambut.
Namun, pada akhirnya, pelibatan masyarakat lokal adalah kunci dalam upaya restorasi dan konservasi lahan gambut. Hal ini terutama karena pengaruh manusia sangat besar dalam mengubah tiga komponen utama lahan gambut—tumbuhan, air, dan tanah gambut. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas, menagih tanggung jawab korporasi, menerapkan pendekatan lokal dalam pengelolaan, dan memperkuat kelembagaan masyarakat adalah beberapa langkah utama yang dibutuhkan.
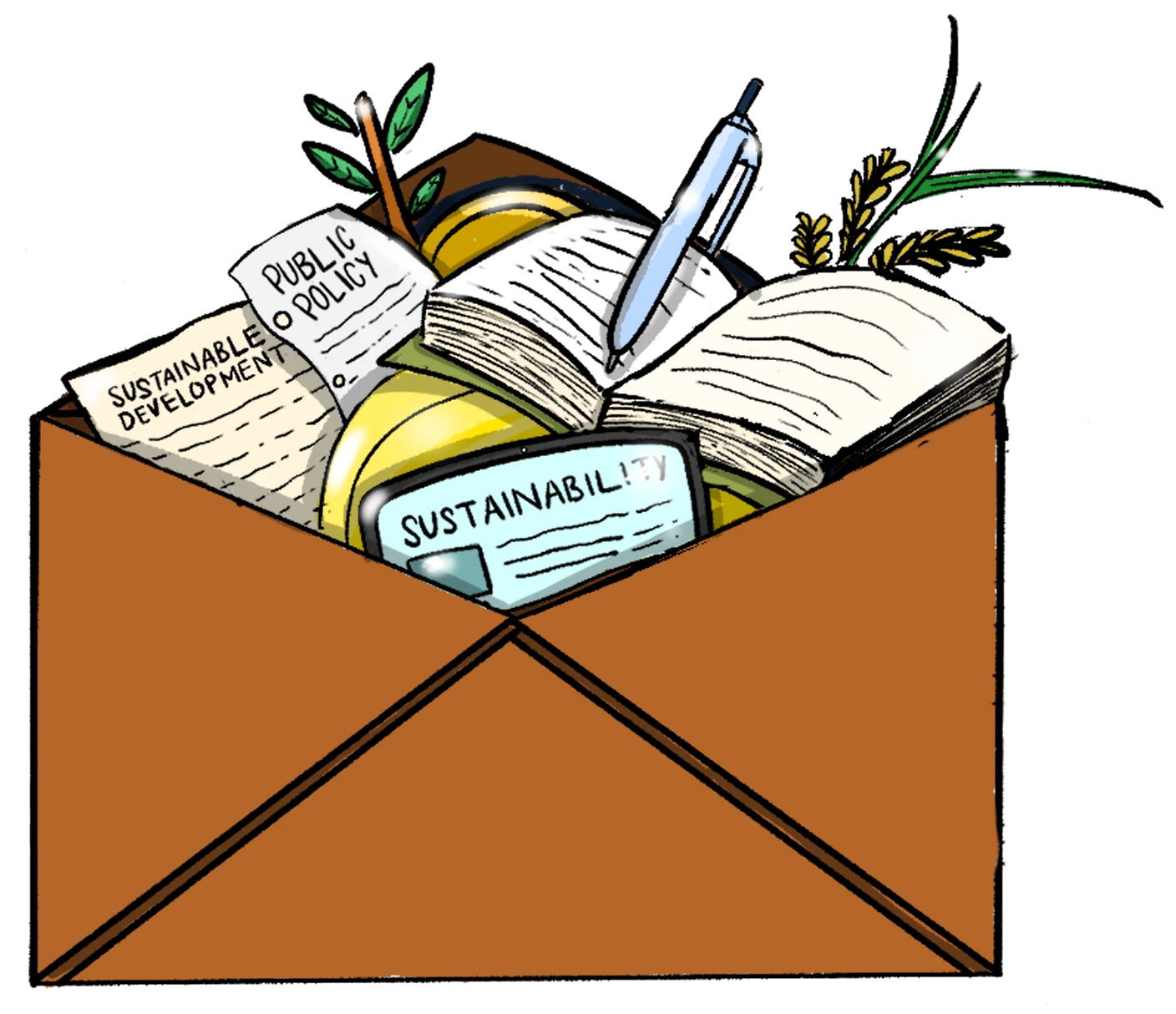
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.


 Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB  Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global  Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan  Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia  Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah  Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja