Fenomena Penumpukan Produk Ramah Lingkungan di Indonesia

Ilustrasi: Frendy Marselino.
Di sebuah resepsi pernikahan, para tamu menerima suvenir “produk ramah lingkungan” berupa tumbler dan tas belanja kain, rapi terbungkus kantong kertas dengan pita rotan. Pemandangan serupa kini juga mudah ditemukan di seminar dan acara-acara korporasi, dengan label “hadiah ramah lingkungan”. Di ritel-ritel dan gerai makanan modern, kantong plastik sekali pakai kini berganti dengan tas belanja guna ulang (reusable) demi mematuhi aturan pemerintah.
Namun, di banyak rumah, deretan tumbler tersimpan tidak terpakai dan tumpukan tas belanja guna ulang memenuhi lemari. Inilah pola yang terjadi ketika barang-barang yang dianggap “hijau” menumpuk jauh lebih cepat daripada penggunaannya. Tanpa pemakaian berulang dan pengelolaan akhir yang tepat, potensi pengurangan sampah dan emisi dari barang-barang ini hampir pasti tidak akan terwujud.
Dampak ‘Produk Ramah Lingkungan’ Ditentukan Frekuensi Pemakaian
Manfaat lingkungan dari produk ramah lingkungan atau produk guna ulang sangat bergantung pada seberapa sering produk tersebut digunakan. Berbagai penelitian Life-Cycle Assessment (LCA) secara konsisten menunjukkan bahwa tas belanja guna ulang harus dipakai berulang kali untuk menutup jejak penggunaan sumber daya dan emisi yang tinggi dari proses pembuatannya.
Sebagai perbandingan, kantong plastik sekali pakai berbahan high-density polyethylene (HDPE) yang biasa dipakai untuk belanja, memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Sebaliknya, tas berbahan katun atau non-woven polypropylene (lebih dikenal sebagai “spunbond” yang sering digunakan sebagai kantong belanja guna ulang) perlu digunakan puluhan kali sebelum jejak karbonnya bisa lebih rendah dibanding kantong plastik HDPE.
Prinsip yang sama berlaku untuk tumbler dan berbagai produk ramah lingkungan lainnya. Dalam keseharian, banyak tumbler hanya dipakai sesekali, bahkan ada yang tidak pernah digunakan sama sekali. Jika konsumen dan produsen tidak berkomitmen pada prinsip kecukupan (sufficiency), ketahanan (durability), dan pemulihan pada skala besar (recovery), produk-produk “hijau” ini justru akan menambah beban lingkungan alih-alih menguranginya.
Bagaimana Budaya dan Komersialisasi Mendorong Konsumsi Berlebihan
Rendahnya frekuensi penggunaan umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan komersialisasi. Di Indonesia, produk ramah lingkungan sering kali menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan. Sayangnya, banyak yang justru berakhir menjadi koleksi dan bukan menggantikan barang serupa yang sudah dimiliki.
Tren media sosial turut memperkuat fenomena ini. Koleksi produk ramah lingkungan kerap kali dipamerkan dalam unggahan, mulai dari deretan tumbler warna-warni hingga tumpukan tas belanja kain dengan beragam desain. Walau mungkin ditujukan untuk menginspirasi perilaku yang lebih berkelanjutan, cara ini berisiko mendorong konsumsi berlebihan dan menggeser fokus dari “menggunakan” menjadi “memiliki”.
Selain itu, ada pula fenomena moral self-licensing. Ketika suatu pembelian dianggap “ramah lingkungan”, konsumen cenderung merasa telah berkontribusi positif sehingga lebih mudah membenarkan pembelian berikutnya atau menggunakannya dengan kurang hati-hati. Pada produk guna ulang, kecenderungan ini dapat mengurangi motivasi untuk memaksimalkan penggunaan, sehingga manfaat lingkungannya tidak tercapai secara optimal.
Kesenjangan Kebijakan dan Infrastruktur
Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap tahun, dengan plastik sebagai salah satu kontributor utama. Menurut data SIPSN, pada tahun 2024, timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 34,27 juta ton, di mana 19,75% di antaranya merupakan sampah plastik. Dari total timbulan sampah, hanya 47,04 % yang berhasil dikelola dengan layak, sedangkan sisanya berpotensi mencemari lingkungan.
Menyadari urgensi tersebut, sejumlah daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Misalnya, DKI Jakarta telah melarang penggunaan kantong belanja plastik sejak tahun 2020, sementara Bali menetapkan larangan untuk memproduksi air minum dalam kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari satu liter sejak 2025. Di tingkat nasional, pemerintah telah meluncurkan Peta Jalan Pengurangan Sampah melalui Pemakaian Kembali oleh Produsen yang mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular.
Namun, tanpa dukungan sistem pemulihan dan infrastruktur yang memadai, kebijakan-kebijakan ini sulit memberikan dampak maksimal. Inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, hingga saat ini fokus pada material bernilai tinggi seperti botol PET (polyethylene terephthalate) dan kardus. Sementara itu, produk seperti tas spunbond sering ditolak karena rendahnya permintaan dan keterbatasan kapasitas pengolahan.
Tanpa sistem pemulihan yang efektif, produk guna ulang yang jarang atau tidak digunakan justru berisiko menjadi timbulan sampah baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa mengganti plastik sekali pakai dengan produk yang lebih ramah lingkungan tidak cukup menjadi solusi yang berkelanjutan. Perubahan perilaku, baik dari konsumen maupun pelaku usaha, menjadi kunci penting dalam membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
Menerapkan Prinsip Kecukupan (Sufficiency)
Mengatasi konsumsi berlebihan membutuhkan pergeseran pola pikir menuju prinsip kecukupan. Bagi konsumen, meskipun barang lama masih berfungsi dengan baik, godaan membeli produk guna ulang yang baru sering muncul karena dikeluarkannya warna baru, edisi terbatas, diskon besar, atau tren media sosial. Padahal, manfaat lingkungan justru datang dari memaksimalkan penggunaan. Satu tumbler dan satu hingga dua tas belanja yang dipakai setiap hari selama bertahun-tahun akan memberikan dampak lingkungan yang jauh lebih besar dibanding memiliki banyak model yang jarang digunakan. Pesan ini dapat diperkuat lewat kampanye publik yang mengajak masyarakat untuk “setia sampai akhir masa pakai”.
Bagi pelaku usaha, prinsip kecukupan berarti menerapkan prinsip desain produk yang menekankan daya tahan, kemudahan perbaikan, serta kesesuaian dengan kapasitas daur ulang dan pemulihan material di tingkat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan Circular Economy Action Plan (CEAP) yang mendorong desain produk berkelanjutan. Mengurangi pembaruan musiman yang tidak perlu, menggunakan komponen standar, dan memilih material yang dapat dipulihkan akan mempermudah perawatan, perbaikan, dan daur ulang. Hal ini dapat memastikan produk dapat digunakan lebih lama dan dapat dipulihkan di akhir masa pakainya.
Bagi pembuat kebijakan, panduan Extended Producer Responsibility (EPR) dari WWF Indonesia dapat menjadi acuan dalam merancang regulasi. Panduan ini memastikan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya. Tanggung jawab ini mencakup target penggunaan ulang, pengumpulan, dan pemulihan material, serta pelaporan yang transparan. Dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari fasilitas perbaikan, mekanisme take-back, hingga dukungan bagi pengumpulan berbasis masyarakat, akan memastikan produk guna ulang tidak hanya berhenti pada kepemilikan.
Mengubah Ukuran Keberhasilan
Produk ramah lingkungan seharusnya menjadi solusi, bukan menjadi timbulan sampah baru. Ukuran keberhasilan bukanlah tentang berapa banyak produk “hijau” yang beredar, melainkan seberapa lama produk tersebut digunakan hingga akhir masa pakainya. Sudah saatnya konsumen memilih dan berperilaku dengan bijak, pelaku usaha merancang produk dengan lebih bertanggung jawab, dan pembuat kebijakan memastikan sistem yang mendukung agar setiap produk guna ulang benar-benar memberi manfaat penuh bagi lingkungan. Pada akhirnya, komitmen semua pihak yang akan menentukan apakah upaya mengurangi sampah benar-benar membawa perubahan atau hanya menjadi tren sesaat.
Editor: Abul Muamar
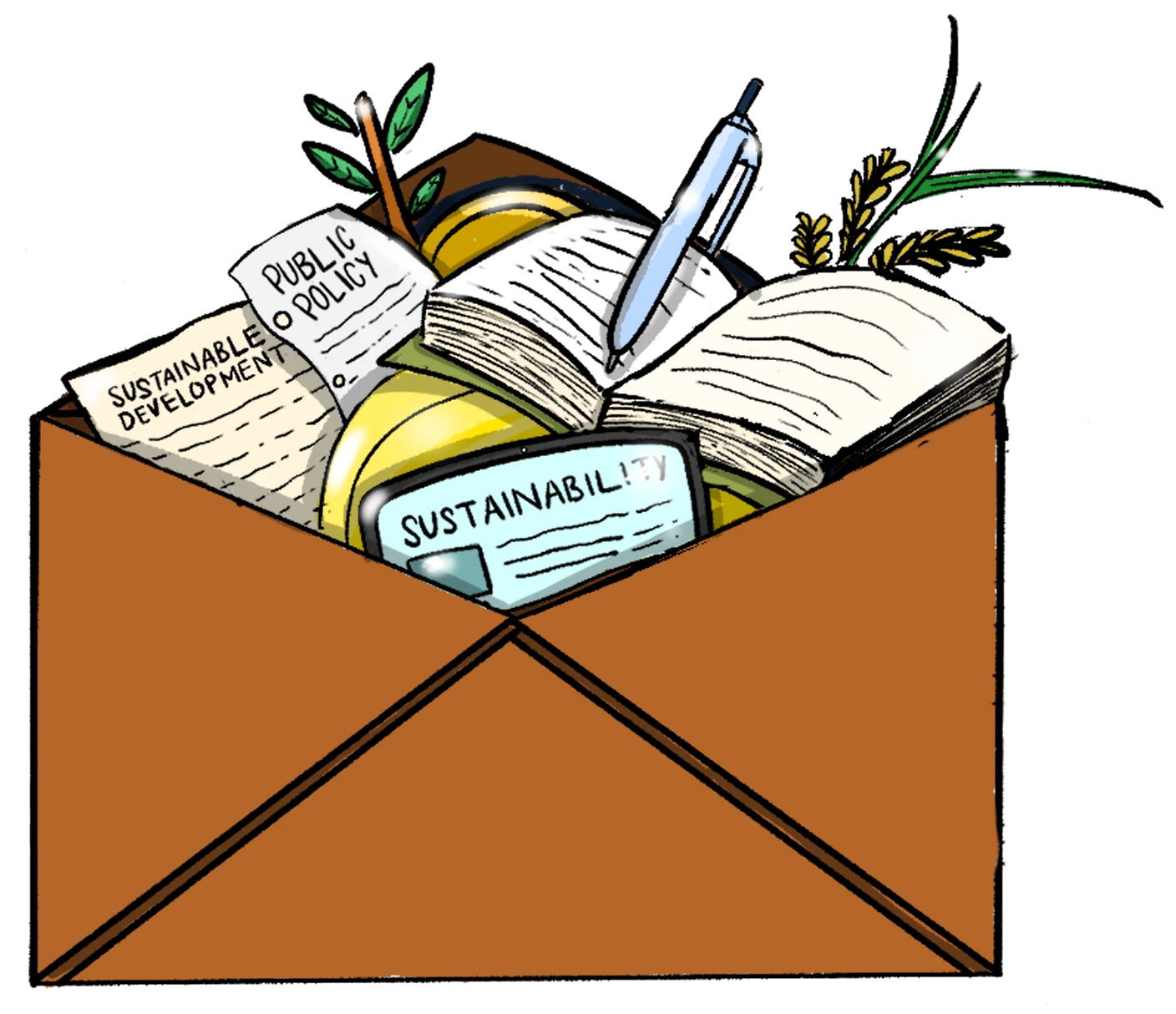
Join Membership Green Network Asia – Indonesia
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Nadia adalah Strategy Director di ImpacThink, sebuah konsultan komunikasi keberlanjutan. Selama lebih dari 15 tahun, ia mengajar mata kuliah Perilaku Konsumen di Universitas Indonesia. Pengalaman mengajar inilah yang menumbuhkan ketertarikannya pada isu konsumsi berkelanjutan. Menggabungkan wawasan akademis dan keahlian komunikasi strategis, Nadia berkomitmen mendorong kesadaran dan aksi nyata dalam mewujudkan keberlanjutan.


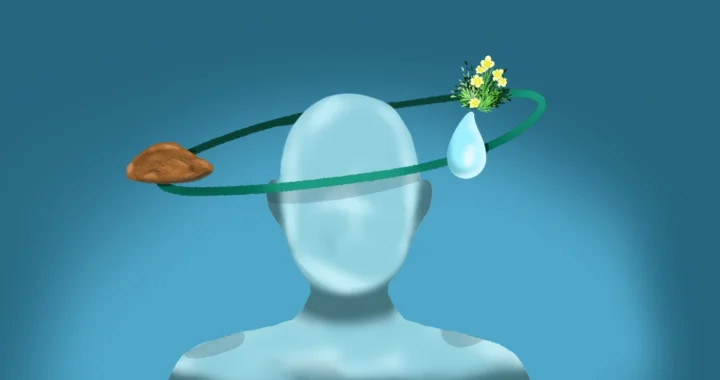 Kosmologi Desa dan Paradigma Transkonstruktif untuk Pemulihan Subjek Ekologi
Kosmologi Desa dan Paradigma Transkonstruktif untuk Pemulihan Subjek Ekologi  Mengatasi Konsumsi Berlebihan untuk Perubahan Transformasional
Mengatasi Konsumsi Berlebihan untuk Perubahan Transformasional  Food Estate: Mimpi Lumbung Pangan, Nyata Lumbung Masalah
Food Estate: Mimpi Lumbung Pangan, Nyata Lumbung Masalah  Reformasi Subsidi Perikanan dan Harapan Baru bagi Keberlanjutan Laut
Reformasi Subsidi Perikanan dan Harapan Baru bagi Keberlanjutan Laut  Memperkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan
Memperkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan  Mengulik Penyebab Utama Perubahan Pola Curah Hujan
Mengulik Penyebab Utama Perubahan Pola Curah Hujan