Kristopel Bili, Jagawana yang Merawat Hutan dan Budaya Sumba Lewat Seni Sastra

Kristopel Bili. | Foto: Dokumen pribadi Kristopel Bili.
Kebudayaan adalah saka guru kehidupan. Lebih dari sekadar tradisi atau warisan, Kebudayaan menjaga sendi-sendi kehidupan agar tetap selaras, termasuk kondisi lingkungan yang kita huni. Ketika Kebudayaan ditinggalkan, yang terjadi adalah ketidakseimbangan, yang pada waktunya dapat mendatangkan berbagai dampak buruk. Hal itulah yang mendorong Kristopel Bili untuk berjuang merawat hutan dan budaya Sumba.
Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), terjadi degradasi dalam penghayatan nilai-nilai budaya. Hutan di Sumba terus terancam oleh tindakan penebangan pohon oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya: keseimbangan ekosistem menjadi terganggu.
Sebagai seorang jagawana (orang yang bekerja menjaga hutan), Kristopel memandang perlunya pendekatan yang lebih efektif dan berdampak untuk mengatasi masalah tersebut. Ia yakin bahwa pendekatan tersebut dapat ditempuh bukan dengan kekerasan atau senjata, tetapi dengan kata-kata yang lembut dan berbudaya–yaitu sastra.
Mendirikan Sakola Wanno untuk Merawat Hutan dan Budaya Sumba

Menurut Kristopel, pengikisan nilai budaya di Sumba terjadi secara berangsur-angsur dalam sepuluh tahun terakhir, terutama di wilayah perkampungan yang terletak di dekat kawasan hutan. Dulu, para orang tua di kampungnya sangat menghormati keberadaan pohon di hutan dan tidak pernah menebang secara liar dan membabi buta.
“Kalau menebang pohon di hutan, leluhur kami akan melakukan ritual dulu. Minta izin dulu ke penghuni hutan atau leluhur. Dan mereka menebang sesuai kebutuhan, secukupnya saja. Tapi makin ke sini, ketika banyak rumah-rumah situs terbakar, banyak hutan, dalam hal ini hutan kawasan, menjadi rusak. Penebangan dilakukan tak terukur. Mereka tak lagi menghormati nilai-nilai budaya dalam ritual adat yang harus ditaati dan sakral. Terjadi degradasi nilai budaya di sini. Terkesan ritual adat hanyalah seremonial biasa dan di sini kita kehilangan makna budaya yang sesungguhnya,” katanya.
Kristopel memberi contoh. Beberapa warga kini mulai mengambil kayu di hutan kawasan untuk membangun ulang rumah kampung situs yang terbakar.
“Padahal mengambil kayu ramuan rumah adat tidak harus dari dalam (hutan). Leluhur sudah mengajarkan semua tatanan kehidupan. Kampung harus ditanami pohon-pohon besar, di bawah pagar ada tumpukan batu (kangali), lalu di bawahnya hutan kecil (kalio’wo). Nah, hutan-hutan kecil atau kalio’wo ini sudah habis dijual, padahal kita harapkan untuk memasok kayu, tali bambu, dan rotan. Artinya apa? Ada degradasi budaya, termasuk dialami oleh para tetua dan pemangku adat,” tutur Kristopel.
Degradasi nilai budaya juga berpengaruh terhadap berbagai tradisi di Sumba, salah satunya Pasola, sebuah tradisi permainan yang menampilkan ketangkasan lempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu antara dua kelompok. Pasola merupakan bagian dari upacara ritual kepercayaan Marapu—kepercayaan masyarakat Sumba—yang diselenggarakan untuk merayakan musim tanam padi, memohon pengampunan dan kemakmuran untuk hasil panen yang melimpah.

Waktu penyelenggaraan Pasola ditentukan berdasarkan penghitungan bulan dan bintang serta tanda-tanda alam lainnya, di mana sebulan sebelum upacara ini digelar, masyarakat harus mematuhi sejumlah pantangan, seperti mengadakan pesta dan membangun rumah.
“Sekarang, kalau ada tamu ‘istimewa’ dan turis asing yang mau datang, waktu penyelenggaraannya tidak lagi tepat sesuai ritual yang telah diajarkan dan diwariskan oleh pendahulu. Malah disesuaikan dengan jadwal kedatangan tamu ‘istimewa’ dan turis asing itu. Aneh. Entah ini campur tangan siapa, kadang jadwalnya dimajukan, kadang dimundurkan. Jadi sudah tidak sesuai tetapan para tetua adat (Rato) melalui rasi bintang atau bulan lagi. Sakralnya berkurang,” katanya. “Kalau di kota-kota besar, degradasi nilai budaya itu terkikis karena pengaruh modernisasi dan perkembangan teknologi. Nah, di Sumba ini sebenarnya faktor-faktor itu tidak terlalu terlihat, tapi budayanya juga terkikis.”
Semua bentuk degradasi budaya itulah yang mendorong Kristopel mendirikan Sakola Wanno pada tahun 2017, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Kebudayaan Sumba melalui pendekatan seni sastra. Tekad Kristopel untuk mendirikan Sakola Wanna semakin bulat ketika ia membaca pesan di peti jenazah almarhum Hendrik Pali, seorang tokoh adat Sumba Timur, yang ia pikul bersama beberapa orang lainnya menuju tempat pemakaman.
“Ada tulisan ‘Jangan biarkan anak-anak tercabut dari akar budayanya’. Saat memikul peti itu rasanya ada beban Kebudayaan yang kian hari kian memberat di pundak saya. Saya ingin tanamkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini untuk anak-anak supaya mereka tidak mudah terpengaruh,” kata Kristopel.
Membentuk Karakter Anak-anak dengan Sastra

Setiap tahunnya, jumlah Ana Wanno—sebutan bagi anak-anak yang belajar di Sakola Wanno—terus bertambah. Mereka terdiri dari anak-anak SD, SMP, hingga SMA. Hingga 2023, jumlah mereka telah mencapai 40 orang, baik yang berasal dari Wanno Kasa maupun dari Puu Mangita, Desa Dede Kadu, dan desa-desa lain di sekitarnya. Mereka antusias belajar membaca dan menulis puisi, berhitung, dan bermain permainan tradisional.
Dibantu dua orang pengajar, Kristopel mengajarkan anak-anak di Sakola Wanno menanam pohon setiap tahun, menggelar ritual pengkeramatan sumber mata air dan melepas ikan sidat sebagai penjaga sumber mata air, dan mengembangkan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanaman yang ditanam antara lain porang, alpukat, pisang, dan durian. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi warga setempat.
“Yang diutamakan adalah mengasah mental dan karakter mereka sebagai anak-anak kampung agar berani tampil dengan segala keyakinan. Jadi ketika suatu hari mereka keluar, entah itu ke Jawa misalnya, mereka percaya diri,” kata pria kelahiran Waikabubak, 1 April 1982 ini.
Sastra sendiri sebenarnya bukanlah bidang yang dikuasai oleh Kristopel. Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Yogyakarta ini baru berkenalan dengan sastra setelah lulus kuliah. Ketika itu, tahun 2009, sebelum pulang ke kampung halaman, ia mendapat pesan yang terus terngiang di kepalanya dari sastrawan asal Sumba, Umbu Landu Paranggi, yang telah berpulang pada 21 April 2021. Pesan tersebut disampaikan melalui putri sang sastawan, yakni Rambu Anarara Wulang Paranggi. “Bunyinya: Kirimkanlah karya anak-anakku padaku, bentuklah komunitas kecil sastra dan puisikanlah Sumba. Jangan mencariku, aku akan mendatangi kalian untuk satu kerinduan yang tak bertepi.
“Saya belum menulis puisi dan bahkan tak pernah bertemu beliau kala itu, hanya dititipkan amanah. Kekuatan kata-kata itu begitu kuat bagi saya. Kami di Sakola Wanno sangat mempercayai kekuatan kata,” jelasnya.
Untuk membiayai kegiatan Sakola Wanno, Kristopel dan istrinya rela menyisihkan gaji setiap bulan. “Dengan sastra kita jadi lebih mengenal diri kita, mengenal budaya kita, dan mengenal Indonesia,” tegasnya.
Memberdayakan Masyarakat dengan Pelatihan Kewirausahaan

Kristopel juga menyasar orang-orang dewasa untuk mencegah perambahan hutan lebih lanjut. Namun, pendekatannya berbeda. Jika anak-anak dengan sastra, orang-orang dewasa ia berikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM, seperti teh dan kopi dengan produk Tea Kandara dan Coffee Wanno.
“Dari segi mental dan karakter, kan, sulit mengubah orang dewasa. Jadi yang saya lakukan untuk orang dewasa adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena saya melihat rusaknya lingkungan dan hancurnya Kebudayaan itu karena ekonomi. Kalau ekonominya baik, saya yakin mereka gak akan lagi menebang pohon,” katanya.
Selain Sakola Wanno, Kristopel juga membentuk kelompok Seni Sastra Budaya Sumba (SSBS) dengan tujuan yang sama, yakni membentuk karakter anak-anak muda di Sumba agar mencintai alam dan budaya.
Atas semua yang ia lakukan, Kristopel tak mengharapkan apapun kecuali keberlangsungan lingkungan dan budaya Sumba itu sendiri. Ia bahkan tak hirau ketika ada orang-orang yang mengatainya ‘gila’ atas apa yang ia lakukan. Ia hanya berharap, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya dapat melakukan langkah-langkah konkret, serius, dan efektif untuk menyelamatkan lingkungan dan Kebudayaan di Sumba.
“Ada banyak mimpi tertunda yang ingin saya wujudkan, terutama untuk keselamatan budaya Sumba. Yang jelas saya tidak mau kaya dengan materi, saya mau kaya dengan perbuatan dan karya-karya nyata saya. Tapi mimpi itu butuh dukungan. Saya harap saya tidak sendiri,” tukasnya.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.


 Mahkamah Agung India Tetapkan Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar
Mahkamah Agung India Tetapkan Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar  Asa Baru Perluasan Perlindungan: Penyakit Kronis Bisa Masuk Kategori Disabilitas
Asa Baru Perluasan Perlindungan: Penyakit Kronis Bisa Masuk Kategori Disabilitas  Dampak Polusi Limbah Elektronik terhadap Kesehatan Hewan dan Manusia
Dampak Polusi Limbah Elektronik terhadap Kesehatan Hewan dan Manusia 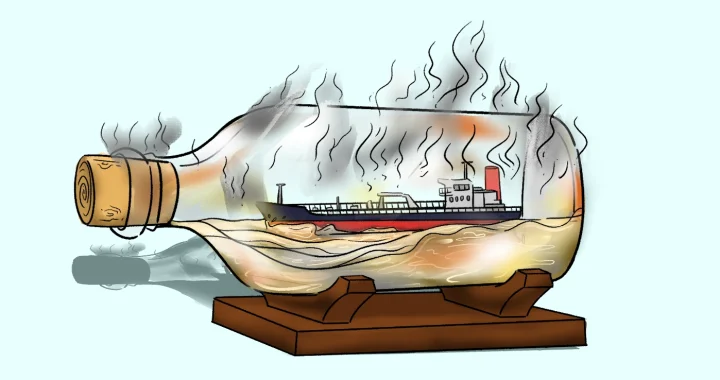 Pelajaran dari Selat Hormuz untuk Indonesia: Kita Tak Bisa Berleha-leha Soal Kedaulatan Energi
Pelajaran dari Selat Hormuz untuk Indonesia: Kita Tak Bisa Berleha-leha Soal Kedaulatan Energi  Meningkatkan Peran Sektor Swasta dalam Atasi Ancaman Krisis Fertilitas
Meningkatkan Peran Sektor Swasta dalam Atasi Ancaman Krisis Fertilitas  Bagaimana Afrika Mencapai Rekor Lonjakan Energi Surya
Bagaimana Afrika Mencapai Rekor Lonjakan Energi Surya