Bagaimana Masyarakat Adat Mollo Hadapi Krisis Iklim dan Dampak Pertambangan

Perempuan adat Mollo sedang belajar menenun didampingi para penenun senior. | Foto: Dokumentasi MAF.
Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di banyak tempat, termasuk Masyarakat Adat Mollo di Nusa Tenggara Timur. Krisis tersebut telah mengakibatkan kelangkaan air dan kerawanan pangan, yang berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ekspansi pertambangan yang tidak bertanggung jawab, praktik reboisasi yang keliru, dan alih fungsi hutan untuk kepentingan industri menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menyebabkan kerusakan alam.
Lantas, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Mollo? Aleta Kornelia Baun, seorang perempuan adat Mollo yang pernah memimpin gerakan penolakan terhadap ekspansi tambang marmer di wilayah Mollo, berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan itu berdasarkan wawasan dan pengalamannya dalam wawancara bersama Green Network Asia (GNA) pada medio Agustus 2025.
Krisis Iklim dan Dampak Tambang di Wilayah Adat Mollo
Perubahan iklim turut berdampak pada kehidupan Masyarakat Adat Mollo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perubahan curah hujan dan peningkatan suhu membuat krisis air dan pangan menjadi ancaman yang semakin nyata. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan dan kebijakan kehutanan yang tidak memperhatikan kelestarian alam.
“Yang terjadi sekarang di NTT adalah dampak perubahan iklim yang tidak bisa kita hitung dan juga banyak kekurangan sumber-sumber mata air. Kenapa kekurangan sumber mata air? Karena (Dinas) Kehutanan telah mengembangkan pohon mahoni, jati, akasia, dan pohon-pohon ini adalah pohon yang rakus akan air. Ketika tambang masuk, wilayah Mollo menjadi daerah yang kering karena hutan menjadi rusak, tutupan tanah hilang, dan cadangan air tanah semakin menipis,” kata Aleta.
Sumber air yang menyusut di Mollo membuat tanah tidak lagi seproduktif dulu sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. “Masyarakat Mollo itu sebenarnya adalah masyarakat yang sejahtera, sejahtera karena sumber daya alam kami ada. Penghasilan kami bersumber dari perkebunan apel, dulu itu buahnya sarat (banyak), jeruk buahnya sarat (banyak). Saking banyaknya apel itu dikasih makan ke ternak, dan nilai ekonominya luar biasa,” katanya.
Selain berdampak pada pertanian dan perkebunan, perubahan iklim dan pertambangan juga membuat banyak keluarga Mollo yang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air bersih, bahkan terkadang berebutan dengan hewan ternak. Kondisi demikian tidak hanya menguras energi tapi juga menyita waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk bekerja, belajar, ataupun beristirahat.
Perlawanan Masyarakat Adat Mollo

Masyarakat Adat Mollo menganggap alam tempat mereka hidup sebagai entitas yang menyatu dengan kehidupan mereka. Batu dianggap sebagai tulang, air sebagai darah, hutan adalah urat nadi dan pori-pori, dan tanah adalah daging. Maka dari itu, mereka menjaga alam layaknya menjaga kehidupan.
Ketika tambang marmer mulai masuk ke wilayah mereka pada tahun 1990-an, masyarakat Mollo dengan tegas menolak dan melakukan perlawanan. Bukan dengan kekerasan, mereka, terutama para perempuan, melawan dengan menduduki tempat-tempat penambangan marmer saat itu dan menenun di lokasi tambang. “Kami menunjukkan tenun-tenun kami, yang menceritakan tentang struktur adat kami, lembaga adat kami, dan masyarakat adat yang ada di Mollo itu sendiri. Hubungan tenun dengan alam itu tidak bisa dipisahkan karena punya makna dan punya cerita yang sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat yang ada di Mollo,” ujar Aleta.
Perjuangan masyarakat Mollo melawan tambang berlangsung selama belasan tahun. Di masa akhir sebelum mendapatkan titik terang, mereka melakukan aksi menenun selama setahun. Saat itu, para perempuan adat Mollo menenun di lokasi tambang sejak pagi hingga sore, dan kemudian pada malam harinya dilanjutkan oleh para lelaki.
“Dari bentuk perlawanan itu kami memahami bahwa negara ini tidak peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Negara mencaplok saja tanah-tanah mereka. Hak-hak masyarakat adat tidak dipedulikan, tidak didengar, tidak dihargai,” tambah perempuan yang akrab disapa Mama Aleta ini.
Membangun Kemandirian

Meskipun penolakan terhadap tambang marmer berhasil, masyarakat adat Mollo masih berhadapan dengan ancaman perubahan iklim, kerusakan hutan, dan krisis air. Semua itu tidak hanya mengancam lingkungan, tapi juga keberlangsungan budaya dan kehidupan mereka.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Mollo adalah memperkuat kemandirian pangan dan pendidikan lokal. Mereka mengembangakan Pangan Terpadu Berkelanjutan (PTB) dengan menanam kopi, jeruk, alpukat, sayur-sayuran, dan pangan lokal seperti ubi dan jagung. “Walaupun kami tidak didukung oleh siapapun, kami harus memulai kegiatan PTB ini. Kami tidak mau kalah dengan perubahan iklim, kami akan tetap melakukannya,” tutur Aleta.
Inisiatif-inisiatif ini juga diperkuat dengan sebuah organisasi yang lahir dari perjuangan masyarakat Mollo melawan tambang. Organisasi ini berperan menjaga kesinambungan gerakan dengan mendukung pendidikan, pemberdayaan perempuan, pelestarian kebudayaan, serta penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan cara ini, masyarakat Mollo tidak hanya bertahan, tapi juga membangun kemandirian yang berkelanjutan di tengah krisis iklim.
Editor: Abul Muamar
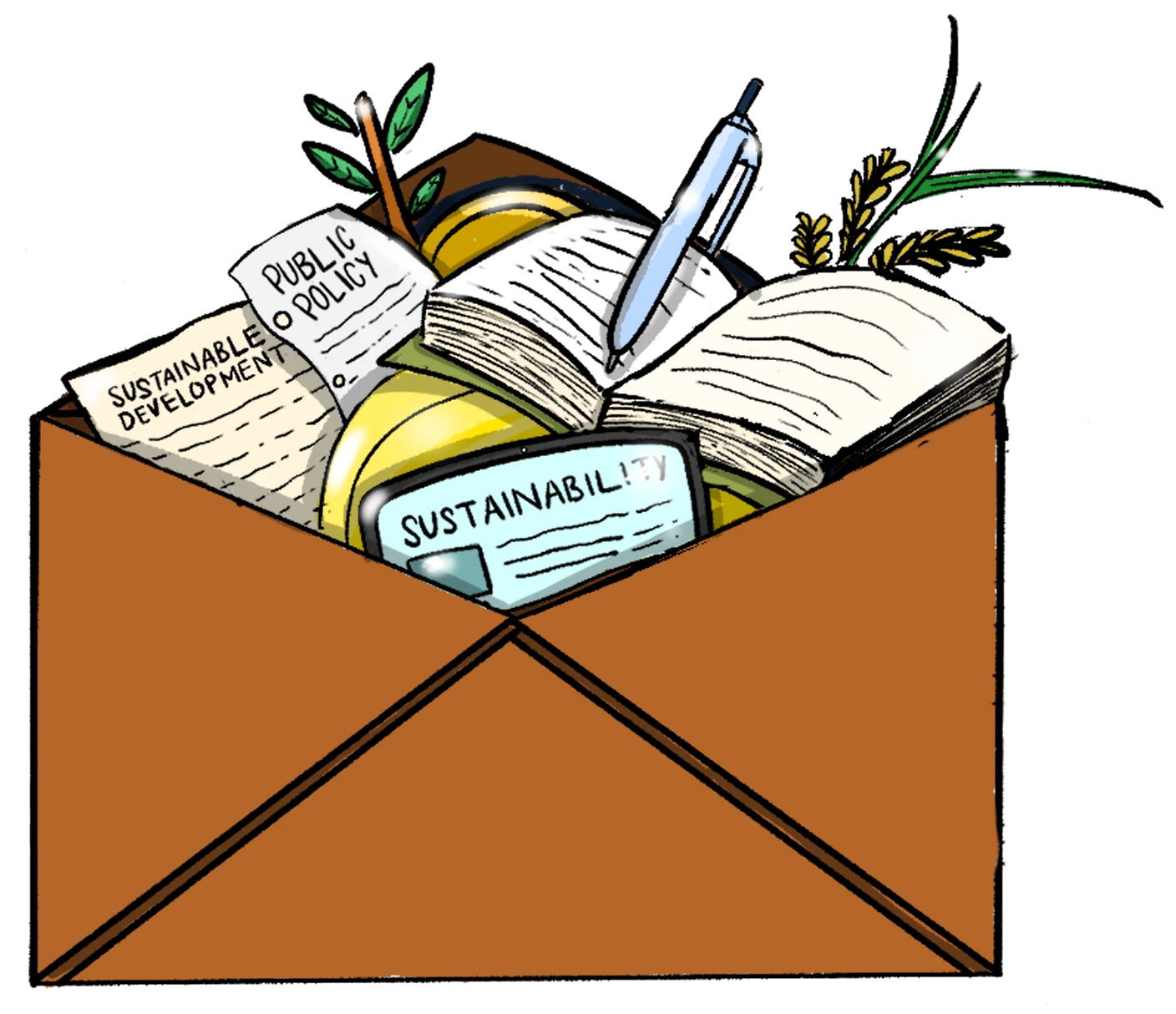
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya  Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air
Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air  PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut  Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa  Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?  Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit