Mendorong Penghitungan Investasi yang Adil dalam Upaya Transisi Energi

Foto: Freepik.
Krisis iklim yang terjadi memaksa pemerintah seluruh dunia untuk mendorong investasi pada transisi menuju energi terbarukan, tanpa terkecuali Pemerintah Indonesia. Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan biaya investasi dalam transisi energi dapat dihitung secara menyeluruh sehingga bisa berjalan dengan adil dan berkelanjutan.
Rencana Transisi Energi Indonesia
Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk menghasilkan 61 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, bahkan menargetkan penggunaan 100 persen pembangkit listrik dari EBT pada tahun 2035. Untuk mencapai target iklim 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan dana sekitar USD 97 miliar sebagaimana yang dituliskan dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP).
Transisi menuju energi terbarukan juga diperkirakan akan membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja antara 2,1 juta hingga 3,7 juta pekerjaan baru pada tahun 2030. Namun, di balik potensi tersebut, penting untuk meninjau dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul selama proses transisi, serta memastikan manfaat dari penerapan teknologi rendah karbon dapat terdistribusi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
Penilaian Dampak Transisi Energi
Selain persoalan teknis dan finansial, peralihan menuju energi terbarukan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, transisi energi yang adil adalah transisi yang dapat mengidentifikasi seluruh potensi kerugian yang akan dihadapi serta memiliki cara untuk mencegah dan memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Ada dua pendekatan yang selama ini dirujuk di Indonesia untuk menganalisis dampak dari transisi energi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, yakni pendekatan komponen biaya yang dikembangkan oleh International Forum for Environment, Sustainability, and Technology (iFOREST) dan pendekatan penilaian dampak dari Asian Development Bank (ADB).
Pendekatan komponen biaya dari iFOREST menghitung kebutuhan investasi transisi energi berdasarkan beberapa komponen utama yang diukur dengan satuan atau pembagi (denominator) tertentu. Terdapat tiga contoh komponen utama dalam pendekatan ini yakni reklamasi dan pemanfaatan kembali tambang batu bara yang biayanya dihitung berdasarkan kapasitas tambang yang akan ditutup selama masa transisi dengan satuan juta ton per tahun (MTPA) atau luas lahannya dengan satuan hektare; penonaktifan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dihitung menurut kapasitas listrik yang akan dihentikan dengan satuan megawatt; dan diversifikasi ekonomi yang diukur berdasarkan kapasitas tambang atau pembangkit yang akan ditutup dengan satuan MTPA atau MW, maupun jumlah penduduk yang terdampak langsung.
Pendekatan ini dapat memperkirakan berapa besar biaya yang dibutuhkan secara keseluruhan agar transisi energi berjalan adil, berdasarkan data yang sudah tersedia. Namun, pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa semua kasus memiliki komponen biaya dan biaya per unit yang serupa sehingga tidak begitu memperhatikan variasi tempat dan waktu. Padahal bisa saja biaya untuk kapasitas pembangkit di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya.
Selanjutnya, pendekatan penilaian dampak dari ADB menilai proses transisi dengan melihat dampaknya di berbagai tingkatan mulai dari level aset yang menilai dampak langsung di lokasi pembangkit misalnya pada pekerja dan komunitas lokal, hingga dampak nasional dan regional. Pendekatan ini menggunakan metode bottom-up berbasis data dengan penilaian pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta mengidentifikasi siapa yang terdampak, jenis risiko, langkah mitigasi yang diperlukan, dan pihak yang bertanggung jawab. Berbeda dengan pendekatan iFOREST yang menekankan estimasi biaya, metode ADB memberikan gambaran kontekstual atas dampak sosial dan ekonomi.
Pendekatan yang Komprehensif
Melihat keterbatasan dari pendekatan yang selama ini digunakan serta berangkat dari metode penilaian dampak yang dikembangkan oleh ADB, Climate Policy Initiative (CPI) menawarkan kerangka kerja yang dinilai lebih layak untuk digunakan dalam menilai kebutuhan investasi untuk transisi energi yang adil dengan lebih menyeluruh. Pendekatan ini mengadopsi metode penilaian dampak dari ADB dan mengembangkannya agar relevan dengan berbagai situasi transisi energi di Indonesia.
CPI merekomendasikan penggunaan format data yang mencakup informasi mengenai setiap pihak yang terdampak langsung, tidak langsung, dan terdampak turunan atau imbas lanjutan. Data tersebut mencakup jenis entitas dan kuantitasnya, deskripsi dan nilai kerugian, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan dan estimasi biayanya, pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pencegahan, aksi transformasi dan estimasi biayanya, serta pihak yang bertanggung jawab atas tindakan transformasi.
Biaya pencegahan merupakan hal yang penting dalam mengurangi potensi pengeluaran untuk transformasi di masa mendatang. Investasi pada langkah pencegahan, ditujukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari transisi energi. Tindakan yang dilakukan bisa beragam, seperti program reskilling dan upskilling bagi para pekerja yang akan terdampak agar bisa segera mendapatkan pekerjaan baru, pembangunan proyek energi terbarukan sebelum PLTU ditutup agar pasokan listrik tetap stabil, serta pembiayaan ulang utang dan penjualan kredit karbon untuk mencegah kerugian finansial yang besar. Sementara itu, pembiayaan untuk transformasi difokuskan untuk menciptakan manfaat sosial-ekonomi baru, misalnya membuka lapangan kerja lokal, menjamin akses energi bagi masyarakat, dan mendorong pembentukan koperasi energi.
Menuju Transisi Energi yang Transparan dan Berkeadilan
Proses pengumpulan dan verifikasi data yang transparan, dengan melibatkan masyarakat, pekerja, perusahaan, serta pemerintah daerah, dapat meningkatkan validitas data, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat legitimasi kebijakan. Dengan kerangka yang fleksibel dan dapat diterapkan dari level aset hingga nasional, pemerintah dan lembaga keuangan dapat merancang strategi investasi yang efisien secara ekonomi, sekaligus berkeadilan secara sosial dan lingkungan. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana prinsip keadilan dalam transisi energi dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan dan praktik yang relevan agar dapat menghadirkan perubahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Abul Muamar
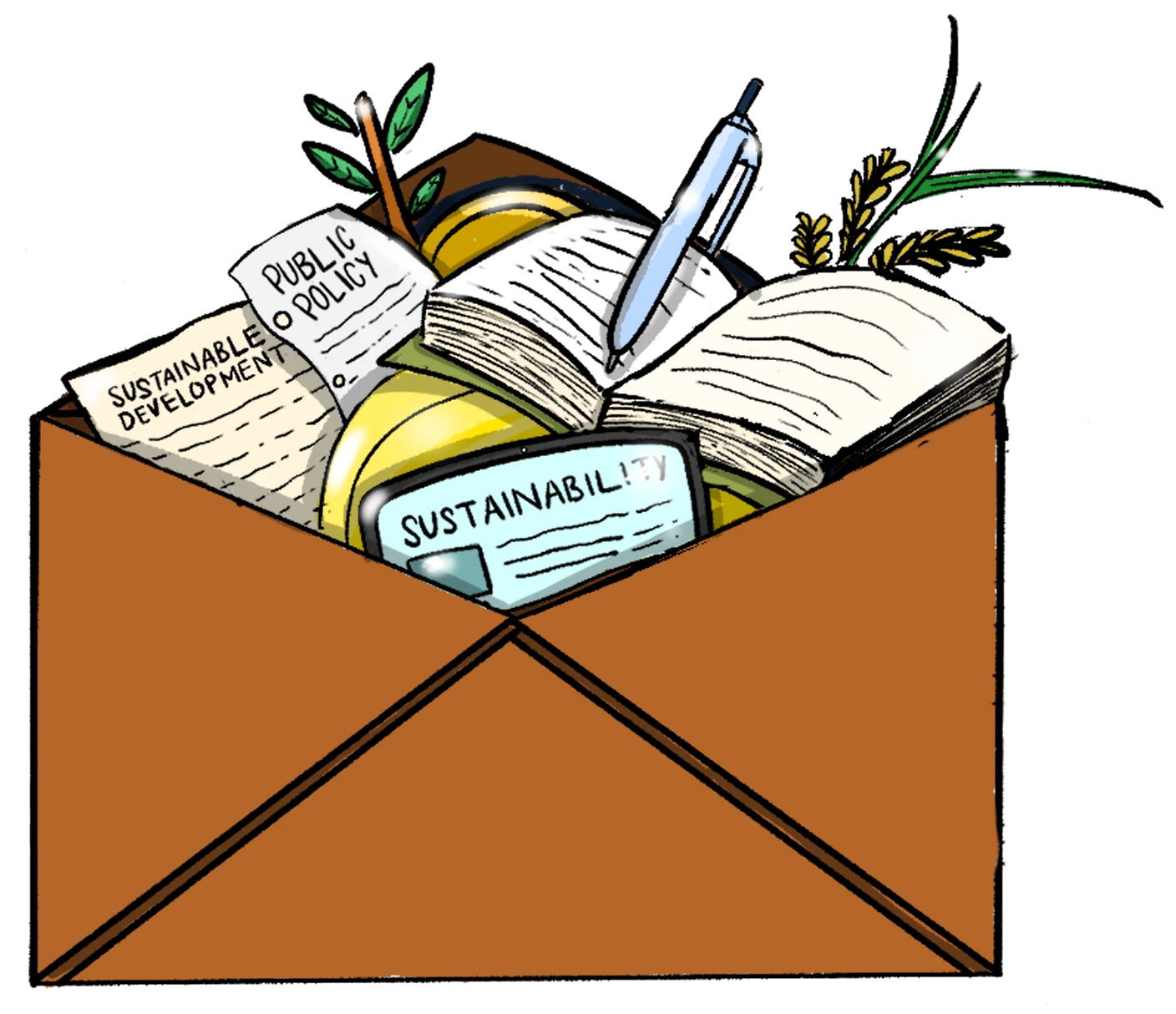
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Finding Harmony: Pencarian Harmoni dengan Alam di Benak Sang Raja
Finding Harmony: Pencarian Harmoni dengan Alam di Benak Sang Raja  Mengatasi Eksploitasi di Balik Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara
Mengatasi Eksploitasi di Balik Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara  Mewujudkan Kondisi Kerja yang Layak bagi Pekerja Platform
Mewujudkan Kondisi Kerja yang Layak bagi Pekerja Platform  Memetakan Kebutuhan Konservasi Hiu dan Pari secara Global
Memetakan Kebutuhan Konservasi Hiu dan Pari secara Global  Ilusi Besar dalam Laporan Kinerja Iklim Perusahaan
Ilusi Besar dalam Laporan Kinerja Iklim Perusahaan  Hamdan bin Zayed Initiative: Upaya Abu Dhabi Mewujudkan Laut Terkaya di Dunia
Hamdan bin Zayed Initiative: Upaya Abu Dhabi Mewujudkan Laut Terkaya di Dunia