Rehabilitasi Mangrove Berbasis Komunitas dengan Silvofishery

Foto: Penjaga Pulau.
Tambak yang terbengkalai seringkali menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan pesisir. Lahan yang semula dibuka untuk budidaya, ketika ditinggalkan, seringkali berubah menjadi ruang terbuka yang rusak dan tidak lagi mampu mendukung fungsi ekologisnya. Pada saat yang sama, pembukaan tambak sendiri menimbulkan kehilangan pada hutan mangrove, padahal ekosistem ini memiliki peran vital sebagai pelindung alami dari abrasi, tempat hidup berbagai biota, serta penopang produktivitas perikanan. Terkait hal ini, sistem silvofishery menawarkan solusi terintegrasi untuk rehabilitasi mangrove sekaligus memulihkan tambak yang rusak.
Degradasi Tambak dan Hilangnya Hutan Mangrove
Pembukaan tambak di wilayah pesisir sering terjadi melalui konversi hutan mangrove menjadi kolam budidaya udang atau ikan. Di Asia Tenggara, area tambak mengalami perkembangan pesat antara tahun 1980 sampai 1990-an dengan laju perkembangan sebesar 20-30% per tahun. Dengan kecepatan ini, tambak memiliki porsi tanggung jawab sebesar 54% terhadap total kehilangan mangrove di Asia Tenggara. Sementara di Indonesia sendiri, diperkirakan kurang lebih 800.000 hektare mangrove telah hilang dalam jangka waktu 30 tahun akibat konversi lahan untuk tambak sejak tahun 1970-an.
Konversi ini tidak hanya menghilangkan vegetasi mangrove, tetapi juga melepaskan banyak karbon yang sebelumnya tersimpan di biomassa dan tanah. Hutan mangrove merupakan ekosistem dengan kapasitas penyimpanan karbon yang tinggi, rata-rata mencapai sekitar 950 ton unsur karbon per hektare atau 2,5–5 kali lipat lebih besar dibandingkan hutan temperate, boreal, maupun hutan tropis daratan.
Sebagian besar karbon ini tersimpan dalam tanah bawah permukaan yang kaya bahan organik dan dapat bertahan selama berabad-abad jika tidak terganggu. Total simpanan karbon mangrove secara global, yakni sekitar 4-20 miliar ton karbon, bahkan setara lebih dari dua kali emisi CO₂ antropogenik tahunan dunia. Namun, konversi mangrove menjadi tambak dapat menghilangkan 70% cadangan karbon ekosistem ini, sekaligus melemahkan peran penting mangrove sebagai penyerap karbon alami.
Selain itu, tambak yang gagal atau terlantar menyimpan masalah jangka panjang. Sebagian besar tambak yang dikonversi dari hutan mangrove cenderung tidak produktif dan akhirnya ditinggalkan karena masalah tanah sulfat masam (acid sulfate soils/ASS). Tanah jenis ini awalnya terbentuk di lingkungan mangrove yang tergenang dan mengandung pirit (FeS₂) yang aman selama kondisi tetap anaerob. Namun, saat mangrove dibuka dan tanah terekspos udara, pirit yang teroksidasi dapat menghasilkan asam sulfat sehingga tanah menjadi sangat asam dan melepaskan ion beracun seperti Fe dan Al ke air. Kondisi ini membuat tambak sulit dikelola, menurunkan kualitas air, serta memicu kerusakan ekosistem pesisir sehingga pemulihannya memerlukan biaya dan waktu yang besar.
Hilangnya hutan mangrove dan semakin luasnya lahan tambak terbengkalai menciptakan kombinasi tekanan yang melemahkan ketahanan ekosistem pesisir, sekaligus mengancam keberlanjutan sumber daya yang bergantung pada keseimbangannya. Kondisi seperti ini menciptakan masalah yang harus dibayar melalui restorasi aktif.
Silvofishery untuk Rehabilitasi Mangrove: Studi Kasus Inisiatif Komunitas Penjaga Pulau
Silvofishery merupakan sebuah metode integratif yang memadukan rehabilitasi mangrove dengan budidaya perikanan tambak. Metode ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1978. Sebagai bentuk restorasi berbasis ekosistem, pendekatan ini mengkombinasikan pemulihan fungsi ekologis mangrove dengan sistem akuakultur berinput rendah.
Saat ini, praktik silvofishery telah diimplementasikan di berbagai wilayah pesisir, termasuk oleh komunitas Penjaga Pulau bersama masyarakat Desa Labuhan Bajo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Model yang digunakan berlandaskan prinsip zonasi 60% area dialokasikan untuk mangrove dan 40% untuk tambak, dengan penanaman mangrove di bagian tengah kolam. Desain ini tidak hanya memulihkan fungsi ekologis mangrove, tetapi juga tetap memberi ruang untuk produksi perikanan secara berkelanjutan.
Dalam implementasinya, Penjaga Pulau bersama kelompok lokal Kabete Bajo dan pemerintah desa memulai dengan rekonstruksi tambak lama, termasuk memperbaiki sistem pengelolaan air. Untuk mendukung rehabilitasi, dilakukan pembibitan mangrove multi-spesies dengan menggunakan tujuh jenis mangrove khas sekitar desa. Dengan metode ini, tingkat keberhasilan hidup bibit di tambak bisa mencapai 90 persen, salah satunya karena masyarakat terlibat langsung dalam pemantauan rutin dan mengganti bibit yang mati.
Keunggulan model silvofishery di Labuan Bajo tidak hanya terletak pada teknis rehabilitasi, tetapi juga pada tata kelola berbasis masyarakat. Penjaga Pulau bersama kelompok lokal menerapkan Adaptive and Integrated Management System (AIMS) yang menggabungkan pengetahuan ilmiah sederhana seperti analisis kualitas air dengan kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, komunitas berfungsi sebagai pelaksana sekaligus pengelola utama, memastikan kegiatan budidaya dan rehabilitasi berlangsung adaptif terhadap kondisi lingkungan. Kerja kolektif ini juga memastikan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi membangun sistem pengelolaan bersama yang berkelanjutan pula.
Langkah untuk Keberlanjutan dan Replikasi
Silvofishery oleh komunitas Penjaga Pulau memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat rehabilitasi mangrove di kawasan tambak yang rusak. Keberhasilan ini membuka peluang lebih luas untuk pengembangan model serupa di wilayah pesisir lain yang menghadapi tekanan yang sama. Namun, potensi replikasi hanya akan berhasil jika ditopang oleh dukungan lintas sektor yang konsisten. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa silvofishery tidak berhenti pada tahap rehabilitasi teknis, tetapi juga terintegrasi dalam tata kelola pesisir yang lebih luas.
Selain itu, keberhasilan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh adanya evaluasi dan riset rutin. Pemantauan berbasis data dapat menjadi dasar ilmiah untuk menilai efektivitas intervensi, memperbaiki kelemahan teknis, serta menyesuaikan strategi dengan dinamika lingkungan setempat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, silvofishery dapat berkembang dari sekadar metode rehabilitasi lokal menjadi model pengelolaan pesisir adaptif yang relevan bagi berbagai kondisi ekosistem di Indonesia.
Editor: Abul Muamar
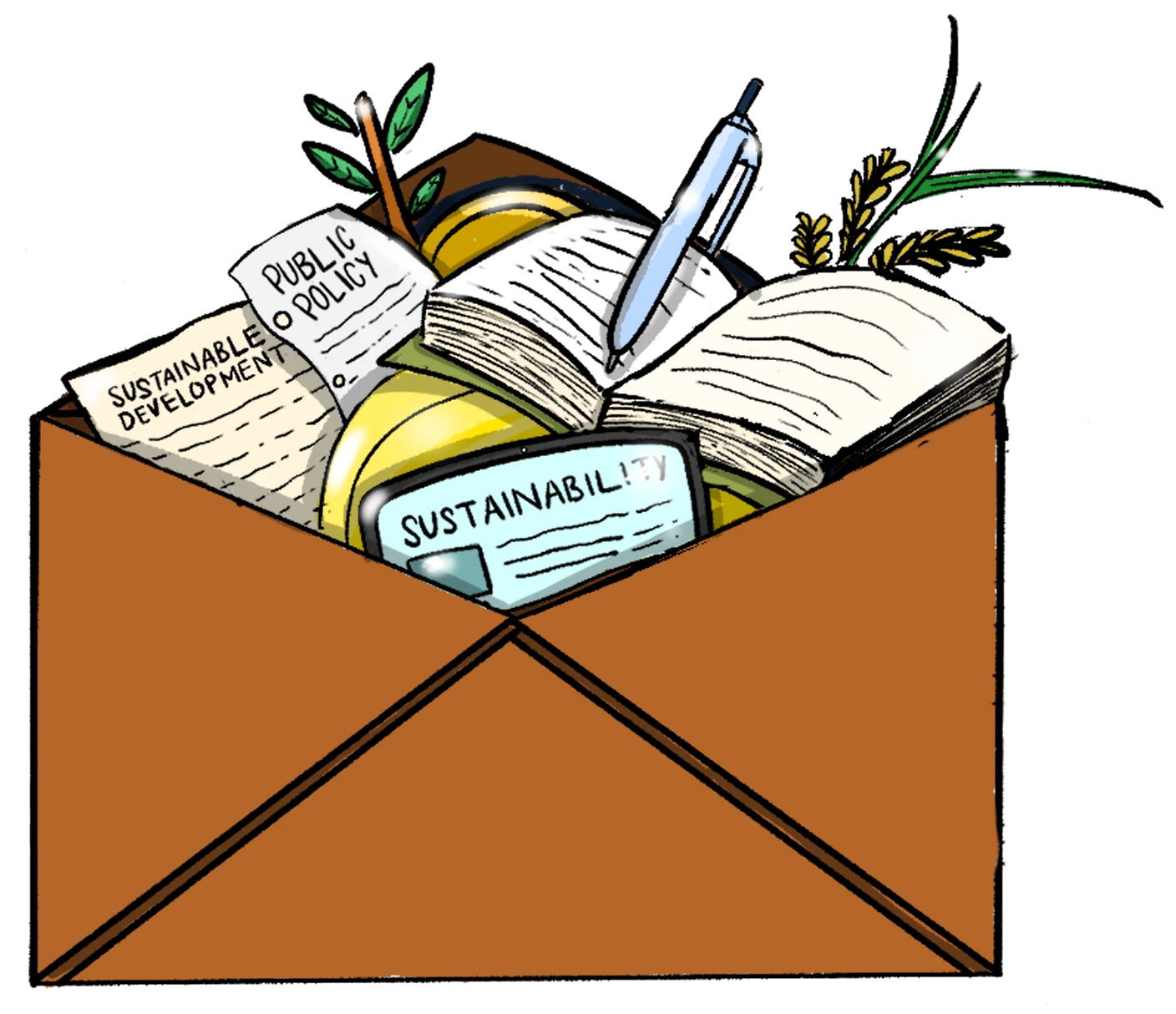
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender
Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender  Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati
Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati  Bagaimana Program PLTS 100 GW dapat Mendukung Ketahanan Energi
Bagaimana Program PLTS 100 GW dapat Mendukung Ketahanan Energi  Kontaminasi PFAS di Amerika Serikat dan Desakan Petani ke Pemerintah
Kontaminasi PFAS di Amerika Serikat dan Desakan Petani ke Pemerintah  Mengatasi Kemiskinan Waktu di Tengah Meningkatnya Isu Kesehatan Mental
Mengatasi Kemiskinan Waktu di Tengah Meningkatnya Isu Kesehatan Mental  Kemunduran Besar dalam Pencapaian SDGs di Asia Pasifik
Kemunduran Besar dalam Pencapaian SDGs di Asia Pasifik