Mengulik Manfaat dan Peluang Carbon Offset di Asia Tenggara

Foto: Ken Shono di Unsplash.
Dengan hutan tropis yang melimpah, dapatkah Asia Tenggara mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 melalui carbon offset? Apakah kawasan ini siap untuk membuka pasar karbonnya ke dunia?


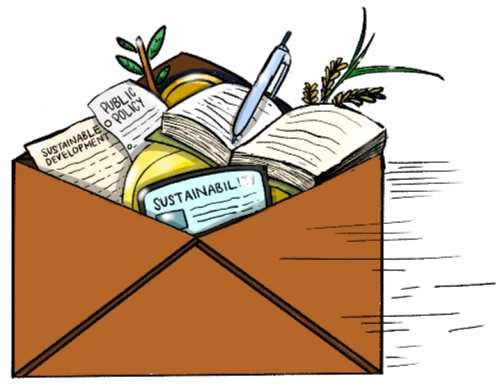
 Jerman Danai Proyek SETI untuk Dekarbonisasi Sektor Bangunan dan Industri di Indonesia
Jerman Danai Proyek SETI untuk Dekarbonisasi Sektor Bangunan dan Industri di Indonesia  Memutus Lingkaran Setan Kekerasan dalam Pendidikan Dokter Spesialis
Memutus Lingkaran Setan Kekerasan dalam Pendidikan Dokter Spesialis  Menengok Sekolah Terapung Bertenaga Surya di Bangladesh, Inisiatif Berbasis Komunitas di Tengah Krisis Iklim
Menengok Sekolah Terapung Bertenaga Surya di Bangladesh, Inisiatif Berbasis Komunitas di Tengah Krisis Iklim  Peluang dan Tantangan Industri Manufaktur Energi Terbarukan di Indonesia
Peluang dan Tantangan Industri Manufaktur Energi Terbarukan di Indonesia  UKRI Danai Enam Proyek untuk Atasi Kerawanan Pangan di Inggris Raya
UKRI Danai Enam Proyek untuk Atasi Kerawanan Pangan di Inggris Raya  Pelanggaran HAM dan Dampak Lingkungan Tambang Nikel di Pulau Kabaena
Pelanggaran HAM dan Dampak Lingkungan Tambang Nikel di Pulau Kabaena