Bayang-Bayang Deforestasi di Tengah Ambisi Hilirisasi Kemenyan

Foto: Wibowo Djatmiko di Wikimedia Commons.
Indonesia memiliki kekayaan hayati dan budaya yang beragam, salah satunya berupa kemenyan. Getah beraroma khas ini telah lama digunakan dalam berbagai ritual adat dan keagamaan di berbagai daerah, menjadikannya bagian penting dari warisan budaya dan spiritual Nusantara. Di samping itu, kemenyan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama karena diekspor sebagai bahan baku obat-obatan, aromaterapi, dan parfum ke berbagai negara. Dengan potensi ekonomi tersebut, pemerintah beberapa kali melontarkan rencana hilirisasi kemenyan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut di dalam negeri.
Namun, bayang-bayang deforestasi mengintai hutan kemenyan di balik ambisi tersebut.
Potensi Hilirisasi Kemenyan
Kemenyan adalah getah atau resin beraroma yang dihasilkan dari pohon kemenyan (genus Styrax spp.) yang kerap dijadikan sebagai bahan dupa sehingga identik dengan upacara atau ritual adat. Indonesia memiliki potensi kemenyan yang cukup besar, terutama karena adanya spesies pohon kemenyan yang hanya tumbuh di hutan Sumatera. Hutan kemenyan ini telah menjadi rumah dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat dari generasi ke generasi selama ratusan tahun.
Akan tetapi, pada pertengahan Juli 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut potensi hilirisasi kemenyan untuk menguatkan ekonomi lokal dan nasional. Kemenyan dinilai memiliki potensi besar dan dapat menjadi komoditas strategis seperti nikel, dengan mengolahnya di dalam negeri. Ide ini sebenarnya bukan hal baru. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Pandjaitan, juga pernah mendorong hilirisasi kemenyan yang dianggapnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara sebagai pusat penghasil kemenyan.
Selama ini, Indonesia memang menjadi salah satu negara pengekspor kemenyan terbesar di dunia. Pada tahun 2024, nilai ekspor kemenyan Indonesia mencapai 43.069 ton atau senilai 52 juta dollar AS. Kemenyan Indonesia dikirim ke berbagai negara, termasuk Singapura, India, Uni Emirat Arab, hingga beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Italia.
Sumatera Utara menjadi daerah penghasil kemenyan terbanyak di Indonesia, terutama di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan uas hutan produksi masing-masing 16.231 hektare dan 4.935 hektare. Dua kabupaten ini menyumbang hingga 85% dari total produksi kemenyan di Sumatera Utara yang mencapai 8.845 ton pada tahun 2021. Ada dua jenis kemenyan yang dibudidayakan di daerah ini, yaitu kemenyan durame (Styrax benzoin Dryand) dan kemenyan toba (Styrax sumatrana) yang memiliki kualitas getah lebih baik dengan harga jual relatif tinggi.
Dengan tingkat produksi dan nilai ekspor yang cukup tinggi selama ini, hilirisasi kemenyan dinilai cukup menjanjikan.
Hutan Kemenyan dan Ruang Hidup Masyarakat Adat
Budidaya dan pemanfaatan kemenyan di wilayah Tapanuli telah berlangsung lama, bahkan dapat ditarik hingga ke-abad ke-17. Kemenyan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi masyarakat lokal yang dikelola dalam bentuk hutan atau kebun campuran.
Bagi Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, misalnya, kemenyan bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas mereka. Hutan kemenyan yang mereka sebut tombak haminjon memiliki nilai historis dan spiritualitas yang tidak bisa ditebang atau dirusak sembarangan. Mereka bahkan memiliki ritual dan aturan khusus dalam budidaya kemenyan, misalnya proses pemanenan getah hanya dilakukan oleh laki-laki dan memukul sekeliling pohon yang disadap harus diiringi dengan nyanyian tradisional.
Akan tetapi, keberadaan tombak haminjon dan ruang hidup Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta terancam ketika negara memberikan izin hutan industri yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Izin yang diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada tahun 90-an, yang memasukkan kawasan tombak haminjon ke dalam area konsesi, berujung pada konflik lahan. Sengketa lahan ini terus berlarut hingga pada tahun 2009, PT TPL membabat hingga 400 hektare hutan kemenyan untuk ditanami dengan pohon eucalyptus.
Aktivitas PT TPL telah membuat mata air menjadi keruh atau bahkan mati sehingga mengurangi ketersediaan sumber air bagi masyarakat setempat. Penebangan pohon yang digantikan dengan eucalyptus juga mengurangi kesuburan tanah yang berdampak pada pertumbuhan pohon kemenyan. Akibatnya, penghasilan getah kemenyan ikut merosot signifikan, dari mulanya 400 kg per orang dalam sekali panen menjadi sekitar 200-250 kg.
Pada tahun 2016, angin segar asa datang ketika Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta menerima surat keputusan (SK) yang mengalokasikan 5.172 hektare untuk hutan adat tombak haminjon. Akan tetapi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) pada tahun 2020 mengeluarkan SK yang mengakui hutan adat hanya seluas 2.393 hektare. Sisanya, disebut akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan.
Ketahanan pangan yang dimaksud mengacu ke Proyek Food Estate yang di wilayah Sumatera Utara, yang pengembangannya ditetapkan seluas 31 ribu hektare di Humbang Hasundutan. Kawasan ini meliputi sebagian wilayah adat Pandumaan Sipituhuta (2.051 hektare) yang sebelumnya tumpang tindih dengan konsesi PT TPL.
Tidak hanya masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, wilayah adat masyarakat Pargamanan-Bintang Maria di kabupaten yang sama juga terdampak oleh proyek food estate. Luas kawasan lumbung pangan di wilayah adat ini diperkirakan mencapai 964,2 hektare dan menggusur hutan kemenyan yang telah bertahun-tahun menghidupi masyarakat adat Pargamanan-Bintang Maria.
Di sisi lain, deforestasi akibat aktivitas perusahaan/industri juga tidak kunjung berhenti meski masyarakat adat telah mendapat pengakuan resmi akan wilayahnya. Laporan Rainforest Action Network (RAN) menemukan bahwa setidaknya terdapat 392 hektare tutupan hutan yang hilang di wilayah konsesi PT TPL pada 2021-2023, yang melibatkan konflik lahan dengan masyarakat adat.
Oleh karena itu, ambisi hilirisasi kemenyan harus mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada keberadaan hutan kemenyan. Selama ini, mereka telah menghadapi kesulitan berlapis akibat deforestasi, ekspansi perusahaan/industri, hingga proyek nasional. Tanpa tata kelola yang memadai, terutama dalam memastikan kelestarian hutan kemenyan, hilirisasi kemenyan diperkirakan hanya akan semakin memperparah kondisi kehidupan mereka.
Kerangka Regulasi yang Jelas
Mendorong hilirisasi kemenyan untuk meningkatkan perekonomian nasional memerlukan kerangka regulasi yang jelas dengan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Regulasi ini dapat mencakup penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dilakukan dengan pemanfaatan kemenyan yang bertanggung jawab dan pelibatan masyarakat lokal secara aktif. Hilirisasi kemenyan juga harus menerapkan asas Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang memberi hak kepada masyarakat adat untuk setuju atau menolak segala program atau kebijakan yang berdampak pada segala aspek kehidupan mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah juga harus hadir secara aktif dalam menyelesaikan konflik lahan dan deforestasi yang membayangi keberadaan hutan kemenyan. Dengan begitu, hilirisasi dapat menjadi upaya pemberdayaan yang mempertahankan lingkungan dan nilai sosial budaya lokal, alih-alih hanya menjadi ambisi pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan keberlanjutan dan keadilan sosial.
Editor: Abul Muamar
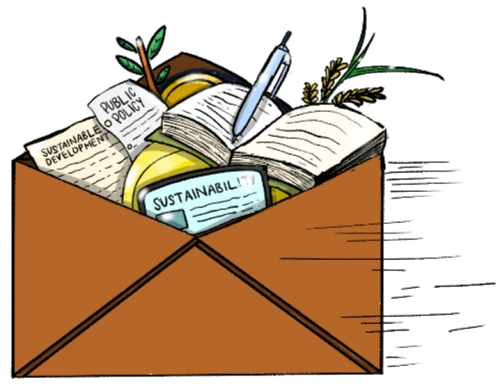
Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.
Nisa adalah reporter dan asisten peneliti di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki minat di bidang penelitian, jurnalisme, dan isu-isu seputar hak asasi manusia.


 Kolaborasi untuk Mendorong Peningkatan Pendanaan Adaptasi terhadap Bencana Iklim di ASEAN
Kolaborasi untuk Mendorong Peningkatan Pendanaan Adaptasi terhadap Bencana Iklim di ASEAN  Nestapa Nelayan di Dusun Sei Sembilang Banyuasin di Tengah Perubahan Iklim
Nestapa Nelayan di Dusun Sei Sembilang Banyuasin di Tengah Perubahan Iklim  Mempromosikan Koneksi Sosial sebagai Pilar Kesehatan dan Kesejahteraan
Mempromosikan Koneksi Sosial sebagai Pilar Kesehatan dan Kesejahteraan  Jerman Danai Proyek SETI untuk Dekarbonisasi Sektor Bangunan dan Industri di Indonesia
Jerman Danai Proyek SETI untuk Dekarbonisasi Sektor Bangunan dan Industri di Indonesia  Memutus Lingkaran Setan Kekerasan dalam Pendidikan Dokter Spesialis
Memutus Lingkaran Setan Kekerasan dalam Pendidikan Dokter Spesialis  Menengok Sekolah Terapung Bertenaga Surya di Bangladesh, Inisiatif Berbasis Komunitas di Tengah Krisis Iklim
Menengok Sekolah Terapung Bertenaga Surya di Bangladesh, Inisiatif Berbasis Komunitas di Tengah Krisis Iklim