Celako Kumali, Kearifan Lokal Suku Serawai untuk Pertanian Berkelanjutan

Pemandangan sawah di Desa Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara. | Foto: Rahmad Himawan di Wikimedia Commons.
Masyarakat adat di berbagai belahan dunia umumnya memiliki tradisi dan filosofi yang mendukung kehidupan yang harmonis dengan alam. Di Bengkulu, masyarakat adat Suku Serawai punya kearifan lokal yang dapat menjadi cara untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, bernama Celako Kumali. Celako Kumali berpijak pada keyakinan bahwa kelestarian lingkungan dapat terwujud dengan menjaga tata nilai dalam tradisi pertanian dan perkebunan, termasuk penerapan aturan dan nilai-nilai tabu untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem.
Ancaman Kepunahan Celako Kumali
Suku Serawai merupakan salah satu komunitas adat di Bengkulu yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma. Mayoritas penduduk Suku Serawai menggantungkan hidup pada pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan Celako Kumali sebagai tradisi yang telah mereka berlakukan secara turun temurun.
Guru Besar Ekologi Manusia Universitas Bengkulu (UNIB) Profesor Panji Suminar mengidentifikasi 19 kearifan lokal dalam Celako Kumali yang dapat menjadi dasar pengetahuan modern dalam adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, tiga di antaranya telah punah atau tidak lagi diterapkan karena alih fungsi lahan dan masifnya pembangunan. Tiga kearifan tersebut yakni “Kijang Ngulang Tai” (pengelolaan tanah pertanian hanya boleh dilakukan satu tahun sekali untuk menjaga kesuburan tanah); “Sepenetaan akaqh kayu (larangan menebang pohon di lereng bukit), dan “Umo tekeno tana tigo” (larangan membuka hutan di lembah yang dikelilingi tiga bukit untuk pertanian).
Sementara itu, lima kearifan lainnya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi otentik seperti sedia kala. Lima tradisi tersebut adalah “Manggang tetugu” (larangan menebang pohon yang berbatasan dengan tanah tempat tinggal roh leluhur; “Tana penyakitan” (larangan membuka lahan pertanian di daerah yang merupakan tempat tinggal roh leluhur); “Binti meretas tanjung” (larangan membuka lahan di delta sungai); “Tanam tungku buisi” (larangan membuka hutan untuk kegiatan pertanian); dan “Bemban teralai” (larangan menebang hutan di lereng bukit ketika sungai mengalir di lembah).
Kearifan Lokal sebagai Sumber Daya Pengetahuan
Dengan demikian, hanya tinggal 11 celako kumali yang masih diterapkan sepenuhnya. Sebelas kearifan tersebut adalah:
- Kijang melumpat: tata kelola pembukaan lahan dan sawah.
- Tanah siboan: larangan mengelola lahan pertanian di tempat ritual adat.
- Merabung bumi atau pematang kuburan: larangan membuka lahan untuk bercocok tanam jika lahan tersebut diapit oleh dua sungai atau anak sungai.
- Setabua gendang: larangan menebang hutan di hulu sungai.
- Ulu tulung betangisan: larangan membuka lahan di lereng yang terdapat dua mata air yang mengalir berlawanan arah.
- Sepelansaran mayat: jika seseorang menanam padi di setengah bagian lereng bukit pada tahun tertentu, maka setengah bagian sisanya dilarang ditanami pada tahun berikutnya.
- Sepelintasan perau atau mengakipitka aiak: larangan membuka lahan pertanian di sisi kiri dan kanan sungai; lahan pertanian hanya boleh dibuka di satu sisi sungai;
- Elang setepak atau ncapkkah tunggul rokok sampai ke sawah: larangan pembukaan lahan di daerah perbukitan jika di daerah lembah terdapat persawahan.
- Tikam luang atau nengakah ulu tulung buntu: larangan membersihkan lahan pertanian di hulu sungai atau di dekat mata air.
- Segelibak bangkai atau sebaliak badan: tata kelola pertanian di perbukitan.
- Macan merunggu: larangan membuka area persawahan yang ditumbuhi pepohonan lebat dan sering dijadikan sarang harimau atau tempat tinggal memedi.
“Indigenous ecological knowledge (IEK) atau pengetahuan ekologis masyarakat adat, muncul bukan hanya sebagai warisan masa lalu semata, tetapi sebagai sumber daya pengetahuan yang relevan dalam mendesain masa depan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Profesor Panji saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Ekologi Manusia UNIB, 30 September 2025. “Celako kumali sejatinya berisikan pesan keseimbangan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan pengetahuan yang seharusnya wajib dijadikan pertimbangan setiap pembangunan di Bengkulu.”
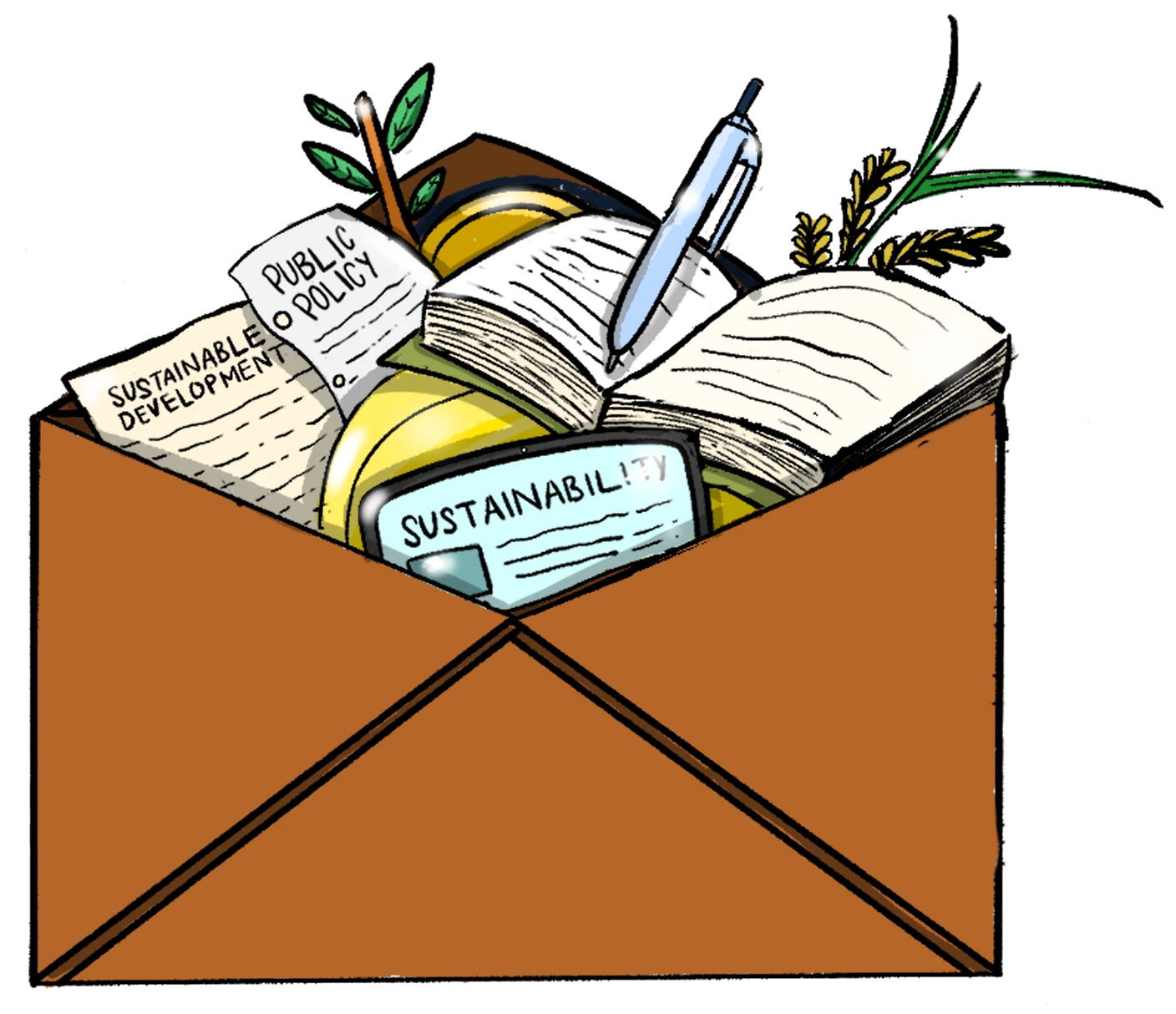
Join Membership Green Network Asia – Indonesia
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Memperkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan
Memperkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan  Mengulik Penyebab Utama Perubahan Pola Curah Hujan
Mengulik Penyebab Utama Perubahan Pola Curah Hujan  Tantangan Orang Muda Perkotaan dalam Penerapan Praktik Keberlanjutan
Tantangan Orang Muda Perkotaan dalam Penerapan Praktik Keberlanjutan  Memperkuat Tata Kelola Risiko Bencana di Tingkat Lokal
Memperkuat Tata Kelola Risiko Bencana di Tingkat Lokal  Memperkuat Perlindungan Perempuan dalam Kondisi Tanggap Darurat Bencana
Memperkuat Perlindungan Perempuan dalam Kondisi Tanggap Darurat Bencana  Sarjana jadi Petugas Kebersihan: Potret Merebaknya Lapangan Kerja Bergaji Rendah
Sarjana jadi Petugas Kebersihan: Potret Merebaknya Lapangan Kerja Bergaji Rendah