Menilik Risiko Pembangunan Pembangkit Panas Bumi di Kawasan Konservasi

Salah satu kawah geothermal di Suoh, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. | Foto: Eka Fendiaspara di Wikimedia Commons.
Pemerintah Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) di kawasan hutan hujan tropis yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Langkah ini memantik perdebatan lama yang belum selesai: sampai di mana batas kompromi antara pembangunan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan?
Antara Energi Bersih dan Jejak Eksploitasi
Sebagai upaya mempercepat transisi energi menuju target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 17-20 persen pada tahun 2025, pemerintah merencanakan pembangunan PLTP berkapasitas 5 gigawatt di Suoh dan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Rencana pembangunan tersebut beririsan dengan area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang merupakan bagian dari Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra/TRHS). Sejak tahun 2004, kawasan ini telah diakui UNESCO karena kekayaan biodiversitasnya. Namun, proyek ini memunculkan polemik setelah pemerintah mengajukan permohonan modifikasi batas kawasan (delineasi) kepada UNESCO agar wilayah Suoh dan Sekincau dikeluarkan dari taman nasional tersebut.
Langkah tersebut tak lepas dari perubahan mendasar dalam kerangka hukum nasional. Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi diberlakukan, kegiatan eksplorasi geothermal tidak lagi dikategorikan sebagai pertambangan, melainkan sebagai pemanfaatan jasa lingkungan. Perubahan ini membuka ruang bagi proyek panas bumi di kawasan hutan lindung dan taman nasional, meskipun secara ekologis, aktivitasnya tetap memiliki karakteristik industri ekstraktif.
Padahal, TRHS bukan sekadar hutan. Kawasan seluas 2,5 juta hektare ini mencakup tiga taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Wilayah ini telah menjadi rumah bagi lebih dari 10.000 jenis tumbuhan, 580 spesies burung, serta 201 spesies mamalia – termasuk orangutan Sumatera yang merupakan spesies endemik. Karena tekanan deforestasi dan aktivitas ilegal, UNESCO telah memasukkan TRHS ke dalam daftar World Heritage in Danger sejak tahun 2011. Hal ini berarti, usulan pelepasan wilayah Suoh dan Sekincau dari wilayah ini dapat berpotensi memperburuk status keterancaman tersebut.
Risiko di Balik Pembangunan Pembangkit Panas Bumi
Dalam pemahaman umum, eksplorasi geothermal sering kali dianggap sebagai solusi energi hijau, tetapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Pengeboran di bawah tanah dapat memicu berbagai risiko, mulai dari gangguan terhadap ekosistem, penurunan tanah, peningkatan angka pencemaran tanah dan udara, hingga potensi gempa mikro. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan manusia. Sedikitnya 7 orang telah menjadi korban jiwa dan 80 orang lainnya mengalami luka akibat ledakan dan semburan gas beracun antara tahun 2007-2022.
Bagi masyarakat Suoh dan Sekincau, ancaman lain datang dari sisi sosial dan ekonomi. Sebuah studi menunjukkan bahwa proyek PLTP cenderung minim dampak ekonomi langsung yang menguntungkan bagi komunitas lokal. Proyek PLTP Ijen, misalnya, hanya menyerap sekitar 0,85 persen tenaga kerja lokal dari total populasi usia produktif. Sementara di Nusa Tenggara Timur, operasi PLTP Ulumbu bahkan berkontribusi pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 368 miliar rupiah akibat berkurangnya produktivitas pertanian.
Kondisi serupa dikhawatirkan akan terjadi di Lampung Barat yang wilayahnya dikenal sebagai sentra pertanian dan penghasil kopi robusta. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian dapat terdampak oleh perubahan tata air dan risiko kekeringan akibat aktivitas eksplorasi panas bumi. Selain itu, pembangunan di kawasan konservasi berpotensi menimbulkan konflik sosial baru antara warga dan pengelola taman nasional.
Dari sisi diplomasi lingkungan, usulan ini turut menimbulkan dilema. Di satu sisi, Indonesia berkomitmen pada energi bersih dalam berbagai forum internasional. Namun di sisi lain, langkah redelineasi kawasan konservasi berpotensi menurunkan kredibilitas Indonesia di mata UNESCO dan mitra iklim global. Proyek PLTP di kawasan warisan dunia dapat dianggap sebagai bentuk greenwashing kebijakan, yang seolah-olah berorientasi pada pelestarian lingkungan, namun sejatinya memperluas ruang eksploitasi sumber daya.
Menyeimbangkan Risiko dan Ambisi
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan warisan dunia menuntut pemerintah untuk berpikir lebih strategis, bukan sekadar reaktif terhadap target bauran energi. Agar tidak terjebak dalam kontradiksi, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan redelineasi kawasan konservasi agar tidak menjadi preseden bagi proyek energi lain di masa depan. Kegiatan eksplorasi panas bumi seharusnya ditempatkan di wilayah dengan risiko ekologis rendah, bukan di jantung ekosistem yang nilainya tidak tergantikan.
Selain itu, dibutuhkan pula mekanisme tata kelola lintas sektor yang lebih tegas. Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Luar Negeri perlu berkoordinasi untuk menyusun pedoman tunggal tentang pemanfaatan energi di kawasan konservasi, termasuk penilaian dampak ekologis yang transparan sebelum izin diterbitkan. Koordinasi semacam ini penting agar ambisi energi nasional tidak berbenturan dengan komitmen konservasi internasional.
Transisi energi juga harus terus mengutamakan keadilan sosial melalui pendekatan people-centered. Artinya, masyarakat di sekitar lokasi proyek harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya menerima dampaknya di akhir. Skema bagi hasil, kompensasi ekologis, dan peningkatan ekonomi lokal bisa menjadi wujud nyata dari transisi energi yang berkeadilan.
Pada akhirnya, ambisi energi bersih tidak akan berarti jika dibangun di atas kompromi ekologis. Menjaga batas bukan berarti menolak kemajuan, tetapi memastikan bahwa setiap langkah menuju masa depan hijau tetap berpegangan pada prinsip keberlanjutan sejati.
Editor: Abul Muamar
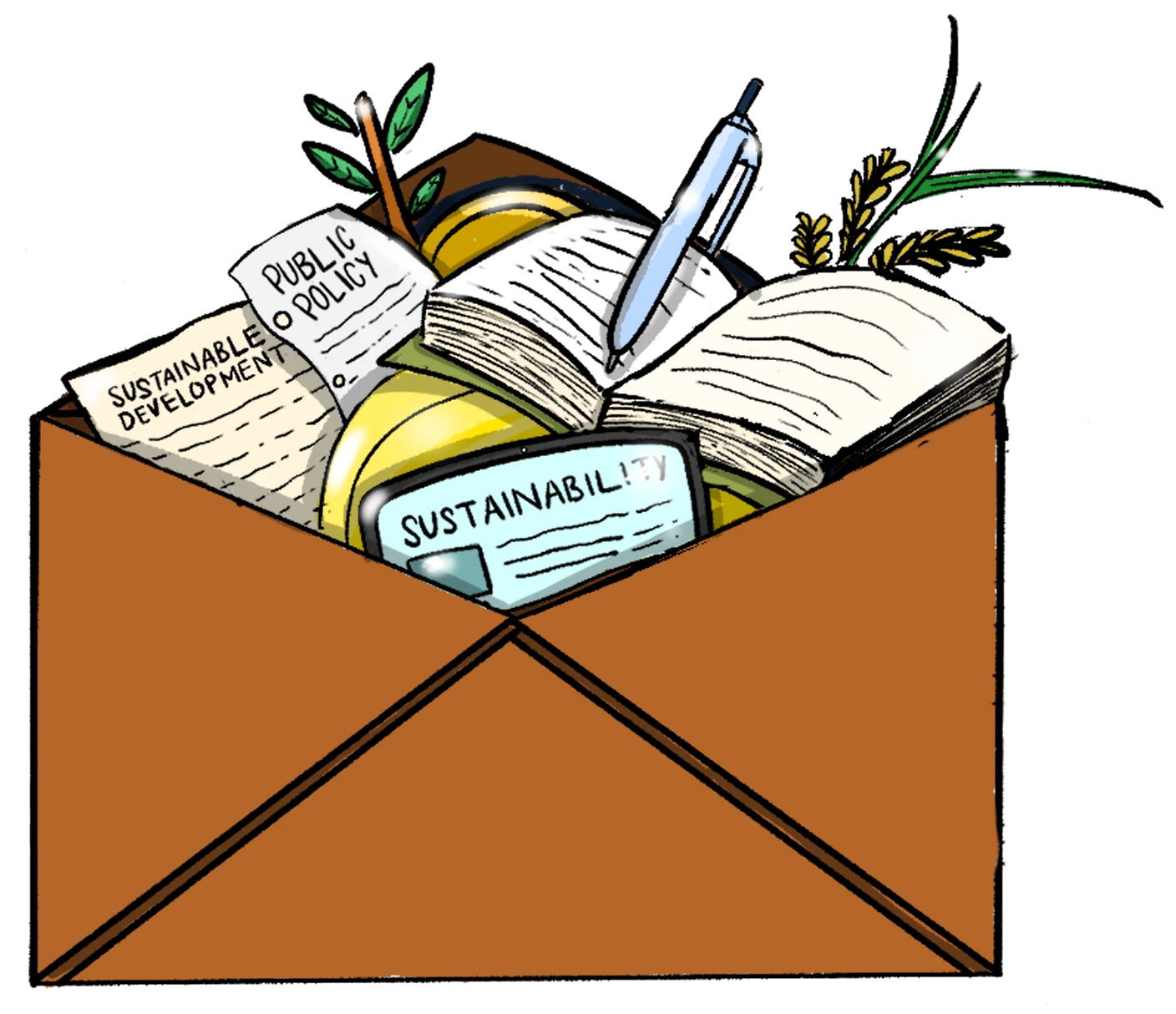
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan
Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan  Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut
Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut  Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data
Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data  Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara
Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara  Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh
Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh  Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia