Menepis Kolonialisme Hijau dalam Transisi Energi Indonesia

Foto: Francesco Ungaro di Unsplash.
Transisi energi kerap dipandang sebagai jalan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkeadilan. Namun pertanyaan muncul perihal pengendalian sumber daya dan investasi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi risiko baru, yakni menjadi korban “ambisi hijau” dunia tanpa benar-benar menikmati manfaatnya. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada bentuk baru kolonialisme dalam transisi energinya.
Ketimpangan Global dan Kolonialisme Hijau
Secara sederhana, kolonialisme hijau atau green colonialism merujuk pada sebuah situasi ketika proyek lingkungan atau iklim yang digagas oleh negara-negara Global North atau korporasi besar mengulang pola kolonialisme lama, yaitu memaksakan agenda lingkungan pribadi, mendikte dan mendominasi masyarakat lokal, dan mengeksploitasi sumber daya atas nama keberlanjutan. Skeptisisme ini muncul karena kebijakan “hijau” yang tampak progresif sering memberikan beban ekonomi, ekologis, dan sosial kepada negara-negara berkembang dan penduduknya.
Kolonialisme hijau dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Secara global, salah satu contoh fenomena ini terlihat dalam kebijakan lingkungan Uni Eropa. Menurut sebuah laporan, sejumlah regulasi, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), dianggap bertentangan dengan seruan transisi yang adil. Kebijakan tersebut, meski dimaksudkan untuk menekan emisi global, justru menimbulkan beban ekonomi bagi negara-negara berkembang. CBAM, misalnya, berpotensi mengurangi daya saing ekspor Afrika hingga USD 25 miliar akibat tambahan biaya atas jejak karbon untuk produk yang dikirim ke Eropa. Pada saat yang sama, CSDDD menuntut standar produksi yang mahal dan sulit dipenuhi oleh produsen di negara-negara berkembang.
Kolonialisme hijau bekerja tidak lewat penaklukan militer seperti kolonialisme masa lampau, melainkan melalui standar hijau dan mekanisme pasar yang menciptakan ketergantungan baru. Negara berkembang “dipaksa” untuk mengikuti jalur transisi energi yang ditentukan oleh negara maju. Dinamika ini menegaskan kembali ketimpangan lama dalam wujud yang lebih modern.
Indonesia dalam Pusaran Kolonialisme Hijau
Di atas kertas, Indonesia tampak menjadi pemain penting dalam ekonomi hijau dunia. Dalam ranah diplomasi internasional, Indonesia berupaya menarik investasi asing melalui proyek energi hijau seperti hilirisasi mineral, namun praktik ini malah menjadi contoh nyata kolonialisme hijau, dimana sumber daya alam dieksploitasi atas nama keberlanjutan tanpa memperhatikan keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, upaya membangun citra ramah lingkungan justru memperpanjang ketimpangan kekuasaan global dan melanggengkan pola eksploitasi yang mirip dengan praktik kolonialisme masa lalu.
Selama beberapa tahun terakhir, investasi di sektor mineral kritis mengalami lonjakan tajam. Sebagian besar proyek hilirisasi mineral di Indonesia saat ini dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing, dengan investasi yang tersebar di wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Menurut sebuah laporan, dari 155 tungku peleburan nikel yang beroperasi di Indonesia pada Desember 2022, sebanyak 144 di antaranya terafiliasi dengan perusahaan Tiongkok.
Pemerintah mengklaim hilirisasi berhasil meningkatkan nilai tambah hingga puluhan miliar dolar, tetapi sebagian besar keuntungan justru mengalir ke pemodal asing yang mendapat fasilitas luar biasa, seperti pembebasan pajak, keringanan royalti, dan akses ekspor produk olahan tanpa kewajiban sosial yang sepadan. Sementara itu, pelaku lokal hanya menjadi penyedia bahan mentah dengan ruang tawar yang makin sempit. Di sinilah logika kolonialisme hijau bekerja. Ketika sumber daya digerakkan atas nama energi bersih, tetapi manfaat ekonominya terkonsentrasi pada pihak luar.
Pola yang sama juga tampak dalam pembiayaan transisi energi. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia mendapat janji pendanaan sebesar USD 20 miliar dari sejumlah negara maju dan lembaga keuangan internasional. Namun, sebagian besar dukungan itu berupa pinjaman yang dinilai dapat membatasi ruang fiskal dan memperkuat ketergantungan terhadap korporasi global. Permasalahan tidak hanya perihal pendanaan, tetapi juga pada proyek energi terbarukan yang dibiayai oleh JETP. Pembiayaan ini dinilai tidak berpihak pada komunitas lokal karena tidak memberi ruang bagi pengembangan energi terbarukan yang digerakkan oleh masyarakat. Selama arah kebijakan hijau masih didorong oleh logika investasi dan bukan keadilan ekologis, transisi energi Indonesia berisiko terjebak dalam krisis iklim yang mewarisi pola eksploitasi kolonial.
Jalan Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan
Menepis kolonialisme hijau bukan berarti menolak transisi energi, melainkan menata ulang cara dan arah transisi. Selama ini, banyak kebijakan energi hijau yang melahirkan dominasi modal asing, beban utang yang tinggi, serta minimnya ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi. Transisi energi yang berkeadilan menuntut koreksi menyeluruh, mulai dari model pembiayaan, kepemilikan sumber daya, hingga tata kelola proyek di tingkat lokal.
Langkah pertama adalah memastikan kedaulatan dalam pendanaan dan teknologi. Indonesia perlu membangun mekanisme pembiayaan hijau yang tidak bergantung pada pinjaman luar negeri yang mengabaikan nilai-nilai keadilan. Model seperti Tropical Forest Forever Facility (TFFF) bisa menjadi pembanding karena menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat utama, bukan sekadar penerima dampak. Pendekatan berbasis hasil dan keadilan sosial seperti ini dapat mengembalikan fokus pendanaan iklim kepada tujuan awalnya, yaitu melindungi ekosistem dan manusia yang bergantung padanya.
Selain itu, prinsip local ownership harus menjadi dasar dalam setiap proyek energi bersih. Pemerintah dapat memperkuat peran lembaga riset domestik agar tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi impor. Di sisi lain, pengawasan publik dan transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa transisi energi tidak berubah menjadi proyek elite yang menyingkirkan rakyat.
Transisi energi yang berkeadilan hanya akan berarti jika ia tidak menjadikan masyarakat di garis depan krisis iklim sebagai korban baru dari perubahan. Dengan memulihkan hak atas tanah, memastikan keterlibatan komunitas, dan membangun teknologi yang dimiliki bangsa sendiri, Indonesia bisa menepis bayang-bayang kolonialisme hijau dan menapaki jalan transisi yang benar-benar berkeadilan.
Editor: Abul Muamar
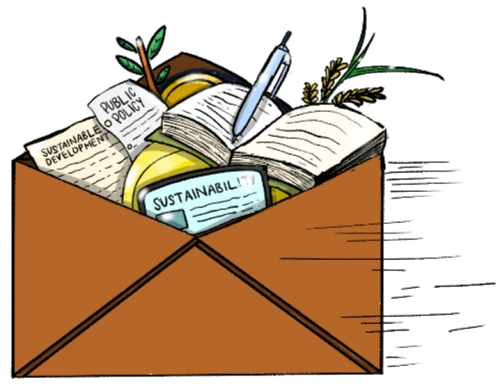
Join Green Network Asia – Ekosistem Nilai Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Dukung gerakan Green Network Asia untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.
Jadi Member Sekarang

 Bagaimana Wisata Mewah Ancam Suku Maasai Mara di Kenya
Bagaimana Wisata Mewah Ancam Suku Maasai Mara di Kenya  Korea Selatan Wajibkan Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF)
Korea Selatan Wajibkan Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF)  Mendorong Penghitungan Investasi yang Adil dalam Upaya Transisi Energi
Mendorong Penghitungan Investasi yang Adil dalam Upaya Transisi Energi  Memperkuat Peran Serikat Pekerja untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
Memperkuat Peran Serikat Pekerja untuk Mewujudkan Keadilan Sosial  Langkah Selandia Baru dalam Menghadapi Degradasi Laut di Teluk Hauraki
Langkah Selandia Baru dalam Menghadapi Degradasi Laut di Teluk Hauraki  Bagaimana Program Dokter Spesialis Keliling di Jateng Menjawab Tantangan Ketimpangan Akses
Bagaimana Program Dokter Spesialis Keliling di Jateng Menjawab Tantangan Ketimpangan Akses