Mengulik Akar Masalah Konflik Harimau Sumatera dengan Manusia di Lampung

Foto: Official Website of Ministry of Environment and Forestry Indonesia di Wikimedia.
Konflik antara satwa liar dengan manusia menjadi hal yang rentan terjadi seiring menyempitnya habitat alami mereka. Dalam hal ini, harimau tidak terkecuali. Ketika wilayah hutan yang menjadi habitat mereka semakin menyusut dan sumber daya makanan menipis, harimau akan terdorong untuk mendekati kebun dan permukiman manusia. Tanpa manajemen penanganan yang kuat dan efektif, hal ini akan menciptakan konflik berkepanjangan yang akan menciptakan dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan.
Berkurangnya Populasi Harimau dan Konflik dengan Manusia
Harimau sumatera merupakan satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia setelah punahnya harimau bali dan harimau jawa. Pada tahun 2024, populasi harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) diperkirakan tersisa sekitar 400 individu yang berada di beberapa wilayah populasi utama sepanjang Pulau Sumatera. Populasinya terus berkurang akibat fragmentasi dan penyusutan habitat, perburuan liar untuk dijual bagian tubuhnya, pemasangan jerat hewan yang membuat harimau turut menjadi korban, serta konflik dengan manusia.
Perburuan dan konflik dengan manusia menjadi faktor paling tinggi yang menyebabkan kematian harimau sumatera. Bukan hanya kematian pada harimau, konflik juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari manusia. Di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung Barat, sepanjang Februari 2024 – Agustus 2025 saja, diidentifikasi ada tujuh orang petani yang tewas diterkam harimau, dan dua lainnya mengalami luka-luka. Jumlah rata-rata konflik yang terjadi antara satwa liar dengan manusia di sekitar wilayah TNBBS tercatat 53 kejadian tiap tahunnya yang juga berakibat pada matinya hewan ternak milik warga.
Perambahan Liar dan Proyek Geothermal di TNBBS
Perambahan liar yang terjadi di sekitar wilayah TNBBS menjadi penyebab utama penyusutan habitat harimau sehingga mendorong eskalasi konflik dengan manusia. Harimau pada dasarnya adalah hewan yang cenderung menghindari kontak dengan manusia, tapi hal tersebut semakin tak terelakkan ketika manusia memasuki wilayah hidup mereka. Sementara itu,tiap-tiap individu harimau membutuhkan wilayah jelajah sekitar 10.000 hektare yang bebas dari jangkauan manusia.
“Dalam sehari, harimau dapat menjelajah hutan ratusan kilometer. Ketika wilayah jelajahnya terganggu, mereka menjadi tidak nyaman. Sementara ada 5 domain animal welfare (kesejahteraan satwa) yang harus terpenuhi, empat di antaranya aspek fisik (meliputi lingkungan, nutrisi, kesehatan, dan perilaku) dan satu aspek mental. Ketika salah satu aspek itu terganggu, harimau akan mencoba mencari kenyamanan baru. Misal ketika lingkungannya terfragmentasi, yang otomatis sumber makanannya juga terganggu, akhirnya juga mempengaruhi perilakunya. Yang seharusnya dia beristirahat atau tidur di bawah pohon atau rerumputan, tetapi karena hutannya berubah jadi perkebunan, dia tidak nyaman. Otomatis kesehatannya juga akan terganggu,” kata drh. Sugeng Dwi Hastono kepada Green Network Asia, Selasa (5/11/2025).
Dari tahun 2002 hingga tahun 2024, Lampung kehilangan 18.000 hektare wilayah hutan primer basah. Luas tersebut menyumbang 6 persen dari total kehilangan tutupan pohon. Hal tersebut juga diikuti oleh gangguan penebangan hutan, kebakaran liar, dan perladangan bergilir. Meskipun bukan faktor tunggal, hilangnya wilayah hutan ini turut berkontribusi pada meningkatnya konflik satwa liar, termasuk harimau, dengan manusia karena ruang hidup mereka semakin sempit.
Di wilayah TNBBS, sebagian besar serangan harimau terjadi ketika para korban sedang beraktivitas di kebun. Beberapa kebun tersebut berada di dalam kawasan taman nasional yang seharusnya menjadi area konservasi, bukan lahan perkebunan. Aktivitas perambahan hutan di kawasan TNBBS umumnya dilakukan untuk membuka kebun komersial, seperti tanaman kopi.
Hal ini menjadi masalah mengingat TNBBS merupakan habitat harimau sumatera dan satwa liar lainnya, serta merupakan wilayah konservasi yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera. TNBBS memiliki luas wilayah 256.800 hektare yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Oleh UNESCO, taman nasional ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Pegunungan Hutan Hujan Tropis Sumatera (Cluster Mountainous Tropical Rainforest Heritage Site of Sumatra/TRHS) bersama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) telah menghimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di dalam kawasan hutan yang merupakan habitat harimau sumatera dan tidak melakukan perburuan harimau serta satwa mangsanya. “Kami juga mengingatkan bahwa kawasan TNBBS merupakan habitat penting harimau sumatera yang populasinya terus menurun dan berstatus Kritis (Critically Endangered). Upaya pencegahan dan penanganan konflik memerlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak demi keselamatan manusia sekaligus kelestarian satwa liar,” kata Hifzon Zawahiri, Kepala Balai Besar TNBBS.
Namun, sebuah langkah kontradiktif muncul ketika pemerintah RI mengajukan modifikasi terhadap batas TRHS ini ke UNESCO karena menemukan potensi panas bumi (geothermal) yang ingin dimanfaatkan. Oleh pemerintah, wilayah Suoh dan Sekincau di Lampung Barat yang masih merupakan bagian dari TNBBS, diusulkan untuk dikeluarkan (delineasi) dari TRHS karena dianggap kondisinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai hutan warisan dunia sehingga lebih baik dimanfaatkan untuk proyek panas bumi. Namun, rencana ini berpotensi mengganggu keutuhan ekosistem TNBBS dan mempersempit habitat alami harimau sumatera dan satwa liar lainnya.
Mengulik Akar Masalah
Konflik antara harimau sumatera dengan manusia yang kerap berulang membutuhkan solusi yang menyentuh akar persoalan. Drh Sugeng menyebut bahwa isu ini erat kaitannya dengan alih fungsi hutan di kawasan konservasi yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lampung. Rencana pembangunan pembangkit panas Bumi di wilayah Suoh dan Sekincau, yang disertai pengajuan kepada UNESCO untuk mengeluarkan wilayah tersebut dari kawasan TNBBS, serta adanya 121 sertifikat tanah yang diterbitkan di kawasan konservasi tersebut, semakin menegaskan seriusnya masalah ini.
“Konflik antara harimau dengan manusia ini sangat berkorelasi dengan alih fungsi hutan yang menyebabkan penyusutan ruang hidup mereka. Ketika ada alih fungsi (hutan), orang-orang akan melihat bahwa ada potensi sumber penghasilan, akan ada lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Saya tidak bermaksud menyimpulkan, tetapi kalau kita melihat kenyataan yang ada, ini semua ada kemiripan. Pun begitu, ini tetap perlu kajian ilmiah lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti akar persoalannya,” ujar drh. Sugeng.
Drh. Sugeng mengingatkan bahwa alih fungsi hutan adalah akar masalah serius yang membutuhkan solusi yang kuat. Ketika hutan dirambah, tutupan hutan berkurang, akan terjadi fragmentasi habitat dan ruang jelajah harimau yang akan menyebabkan terganggunya kehidupan si Raja Hutan–dan pada gilirannya juga keseimbangan ekosistem hutan secara keseluruhan. Hal ini harus menjadi bagian dari edukasi yang perlu diperluas dan ditingkatkan di tengah masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan dan semua entitas yang hidup di dalamnya.
“Ketika jumlah harimau di hutan sebagai predator puncak berkurang, maka satwa mangsa yang di bawahnya akan berkembang biak pesat. Ini semakin berbahaya ketika hutan telah dirusak. Satwa-satwa yang harusnya menjadi mangsa harimau itu akan keluar mencari sumber makanan di luar hutan, termasuk tanaman manusia. Belum lagi ketika hutan dirusak, kemampuan menyerap air berkurang, risiko longsor akan semakin tinggi. Kalau terjadi longsor, masyarakat juga yang akan terdampak, bisa menyebabkan kerugian material maupun nyawa. Pemahaman masyarakat harus sampai sejauh itu,” tuturnya.
Memperkuat Penegakan Hukum
Semua akar masalah ini bukannya tidak dapat dicegah. Drh Sugeng menyebut bahwa salah satu kunci untuk mengatasi, bahkan mencegah, konflik harimau-manusia ada di penegakan hukum yang tegas, yang sayangnya tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
“Kalau kita bicara kawasan konservasi, apalagi masuk warisan dunia UNESCO, akar masalah dari isu ini seharusnya bisa dicegah. Soal masalah kemanusiaan, mata pencaharian masyarakat, dan sebagaimana, itu harusnya bisa diatasi dengan kebijakan dan program-program. Sebagai gambaran, berdasarkan UU No.5/1990 tentang KSDAE, kita tidak boleh masuk kawasan konservasi tanpa izin. Jadi ini soal masalah penegakan hukum. Masalahnya, masyarakat juga tidak mendapat teladan. ‘Mosok nambang panas bumi aja boleh, kami masyarakat ngambil kayu aja gak boleh’. Inilah masalah. Seharusnya hukum berlaku sama,” katanya.
Selain penegakan hukum yang harus diperkuat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas harus ditingkatkan. Di samping itu, juga harus ada pendampingan ekonomi kerakyatan. “Sembari memahamkan kembali bahwa orang tidak boleh merambah hutan, juga harus ada pendampingan dari aktivitas di luar hutan. Contoh, katakanlah di sekitar kawasan konservasi ada hutan rakyat yang bisa dikelola masyarakat. Misalnya ditanami kopi. Berilah pendampingan bagaimana agar hasil kopinya bisa optimal, nilai jualnya tinggi, sehingga kualitas dan kuantitas panennya meningkat, sehingga pendapatan petani bisa meningkat,” katanya.
Dan yang tak kalah penting, lanjut drh. Sugeng, adalah menghapus mitos-mitos yang masih bertahan di tengah masyarakat tentang organ-organ harimau yang selama ini menjadi faktor pendorong maraknya perburuan dan perdagangan liar. “Seperti misalnya, kalau ngantongin kumis harimau bisa bikin berwibawa. Atau kalau menyimpan taring harimau, orang-orang jadi segan. Ini mitos-mitos yang harus dibasmi, sehingga tidak ada lagi permintaan kulit harimau, taringnya, kukunya, kumisnya, dan sebagainya. Semua ini harus beriringan dengan penegakan hukum dan pendampingan ekonomi tadi. Ini penting agar populasi harimau di hutan tetap terjaga. Sebab jika semua harimau sudah ‘dikandangkan’, para perambah hutan akan semakin merajalela karena harimaunya sudah tidak ada. Mereka bisa masuk hutan dengan lebih leluasa. Ini sangat berbahaya,” imbuhnya.
Menyelamatkan Harimau, Menyelamatkan Hutan
Di tengah upaya menjaga populasi harimau sumatera dan mengurangi potensi konflik dengan manusia, tantangan baru muncul dari maraknya perambahan liar dan rencana pembangunan pembangkit geothermal di kawasan TNBBS. Ke depan, penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan berjalan selaras dengan prinsip konservasi yang melibatkan masyarakat lokal, lembaga konservasi, dan pemerintah daerah secara terbuka.
“Kawasan konservasi adalah benteng pertahanan terakhir keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun satwa yang notabene mereka menyediakan sumber daya bagi manusia: air bersih, udara bersih, dan sebagainya. Yang ditakdirkan oleh Allah hidup di kawasan konservasi harusnya bersyukur karena tidak semua orang diwarisi hal itu. Cara bersyukurnya adalah bersama-sama menjaga. Ketika masuk kawasan konservasi dilarang, mengambil sesuatu dari kawasan konservasi dilarang, maka kita jangan melanggar. Lalu bagaimana dengan ekonomi masyarakat? Nah di situ soal kebijakan. Itu tugas pemerintah: meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif, melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, bimbingan teknis di berbagai sektor seperti UMKM, pariwisata, pendidikan, dan sebagainya,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, “Bagi yang bukan pemerintah, yang bukan warga sekitar (seperti NGO, media, dan kita semua), kita bisa mengambil peran edukasi. Tentang apa itu kawasan konservasi, bahwa kita tidak perlu punya hiasan dari organ harimau, dan sebagainya. Ini perlu kerja sama banyak pihak untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya hutan beserta isinya untuk kehidupan anak cucu kita nanti. Setiap warisan harus dijaga. Jangan sampai nasib harimau sumatera seperti harimau jawa dan harimau bali yang sudah punah.”
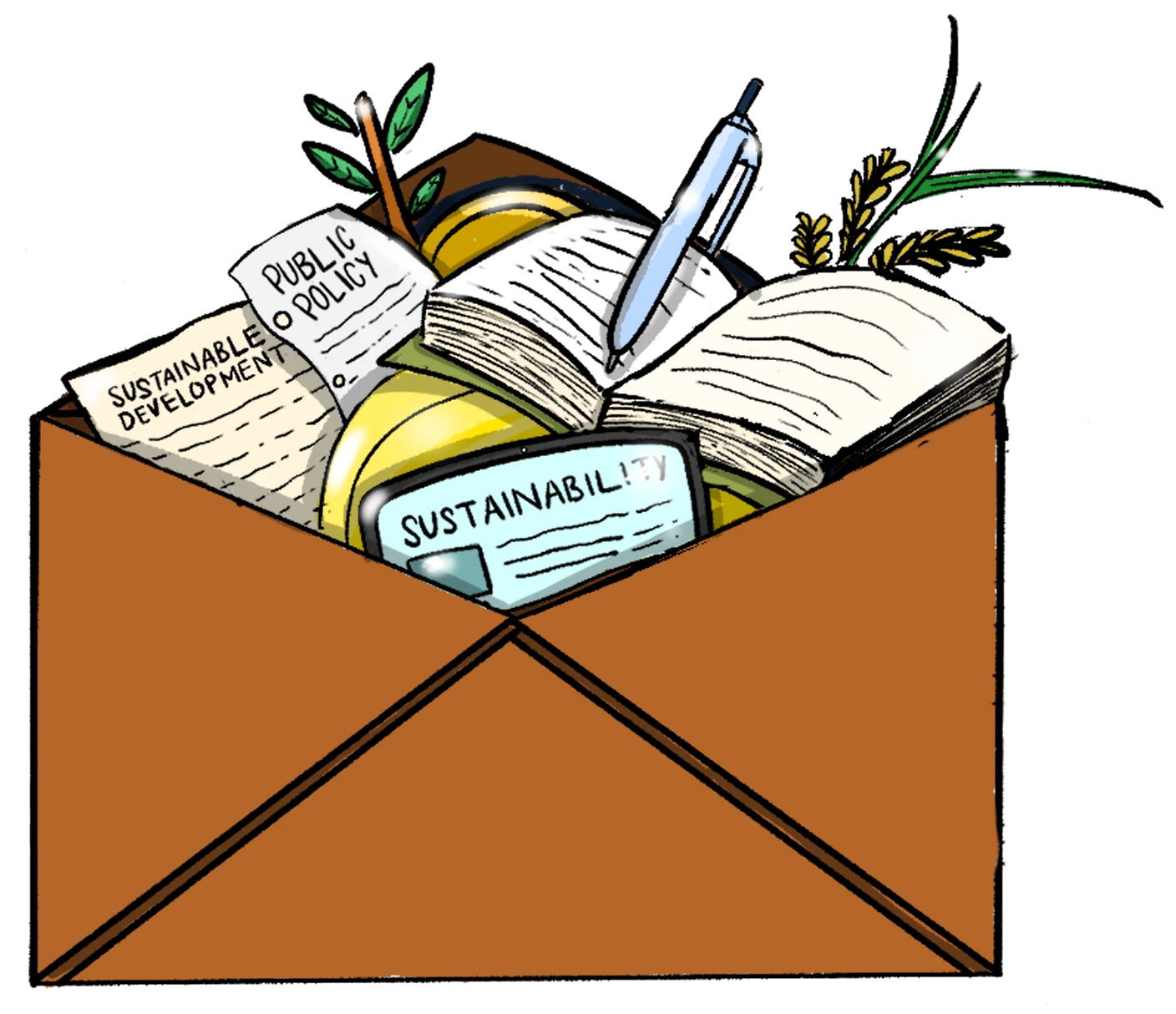
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut
Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut  Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data
Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data  Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara
Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara  Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh
Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh  Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia  Pergeseran Sistemik untuk Mewujudkan Lingkungan Gizi Sekolah yang Sehat
Pergeseran Sistemik untuk Mewujudkan Lingkungan Gizi Sekolah yang Sehat