Jalan Terjal Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual

Ilustrasi oleh Junejunia di Wikimedia Commons.
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Seolah tak berujung, kasus kekerasan seksual masih marak terjadi sehingga membatasi ruang aman dan menimbulkan dampak buruk yang luar biasa bagi perempuan yang menjadi korban. Sayangnya, perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual masih belum optimal meski sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya.
UU TPKS dan Pemenuhan Hak Korban
Angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2024 terjadi 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 14,7% dibanding tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, sebanyak 27% di antaranya merupakan kekerasan seksual.
Sejatinya, upaya untuk menghapus kekerasan seksual telah melewati jalan panjang nan terjal yang mencapai salah satu puncaknya ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada Mei 2022. Pengesahan UU ini menjadi momentum penting dalam pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia sekaligus menjadi tonggak baru yang memberikan kepastian akan pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
Namun sayangnya, UU tersebut tetap tak membuat kekerasan terhadap perempuan berakhir. Begitu pula dengan pemenuhan hak korban yang masih menemui jalan terjal.
Masih Belum Optimal
Meski telah berlaku selama lebih dari dua tahun, implementasi UU TPKS dalam pemenuhan hak korban masih belum optimal. CATAHU Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pada tahun 2024 misalnya, masih banyak korban kekerasan yang mendapat ketidakadilan hukum bahkan mengalami kriminalisasi, terutama perempuan lansia, difabel, anak perempuan, dan perempuan korban kehamilan tidak diinginkan. Ironisnya, kriminalisasi dan pembungkaman korban juga dilakukan dengan perangkat hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, hingga KUHP mengenai pencemaran nama baik.
Sementara itu, aparat penegak hukum (APH) yang mestinya berperan dalam memberikan perlindungan belum sepenuhnya berperspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Menurut riset dari Cakra Wikara Indonesia (CWI), APH cenderung memilih menggunakan perangkat hukum lain seperti KUHP ketika menangani kasus kekerasan seksual dengan alasan untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan korban.
Selain itu, masih banyak APH yang membuat korban merasa terpojok dan tidak nyaman ketika melapor sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses pelaporan. Hal ini diperparah oleh stigma yang dilekatkan kepada korban, yang akhirnya membuat banyak kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di luar jalur hukum, termasuk menikahkan korban dengan pelaku.
Komnas Perempuan juga mencatat bahwa hak atas kesehatan reproduksi secara komprehensif, termasuk layanan aborsi yang aman, juga belum diperoleh secara maksimal oleh perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Dari tahun 2018 hingga 2023, misalnya, terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan dan hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi yang aman. Padahal, aborsi untuk korban kekerasan seksual diperbolehkan dan dijamin oleh UU Kesehatan. Di sisi lain, banyak anak perempuan yang dipaksa putus sekolah ketika mengalami kehamilan tidak diinginkan karena dianggap sebagai aib yang mempermalukan sekolah ataupun keluarga. Hak mereka untuk melanjutkan pendidikan tercerabut dan mereka harus menanggung beban berlipat.
Kebijakan Mandeg, Layanan Tidak Merata
Menurut catatan Komnas Perempuan, belum optimalnya pemenuhan hak korban juga tidak terlepas dari lemahnya kebijakan, termasuk masih adanya tiga peraturan pelaksana UU TPKS yang belum disahkan. Ketiga peraturan pelaksana tersebut mengatur tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; Dana bantuan korban TPKS; dan Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual. Padahal, UU TPKS memandatkan agar seluruh peraturan pelaksana dibentuk dalam waktu dua tahun sejak UU tersebut disahkan.
Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang belum tersedia di banyak daerah juga menghambat pemenuhan hak korban. Riset CWI menyebut bahwa ketiadaan UPTD PPA membuat korban kesulitan mengakses berbagai jenis bantuan dan dukungan yang diperlukan, seperti layanan medis, konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Pada saat yang sama, UPTD PPA yang sudah ada pun masih menghadapi permasalahan seperti kurangnya sumber daya manusia, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah.
Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Korban
Kekerasan seksual berdampak besar terhadap perempuan yang menjadi korban, mulai dari kesehatan, luka fisik, hingga trauma psikologis yang dapat membekas sepanjang hidupnya. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual bahkan menghancurkan atau merenggut hidup perempuan tanpa pernah bisa dipulihkan. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban seperti yang diamanatkan dalam UU TPKS dapat menjadi kunci untuk memberikan perlindungan secara komprehensif bagi korban. Memperkuat sistem perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan memastikan akses yang mudah bagi korban terhadap layanan pendampingan, bantuan hukum, medis, dan rehabilitasi adalah kunci lainnya yang dibutuhkan.
Di samping itu, sosialisasi mengenai tindak kekerasan seksual dan pentingnya kesetaraan gender serta penghormatan terhadap perempuan harus digencarkan di tengah masyarakat. Pendidikan mengenai hal ini juga harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak di lingkungan keluarga dan di sekolah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya terkait pemahaman mengenai dampak kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak-hak korban, dan internalisasi perspektif korban dalam penanganan kasus, juga harus dilakukan dengan serius di semua daerah sampai ke tingkat paling bawah. Terakhir namun tak kalah penting adalah memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan komprehensif, termasuk pemulihan secara individual, kelompok, dan material, serta mendapatkan dukungan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.
Editor: Abul Muamar
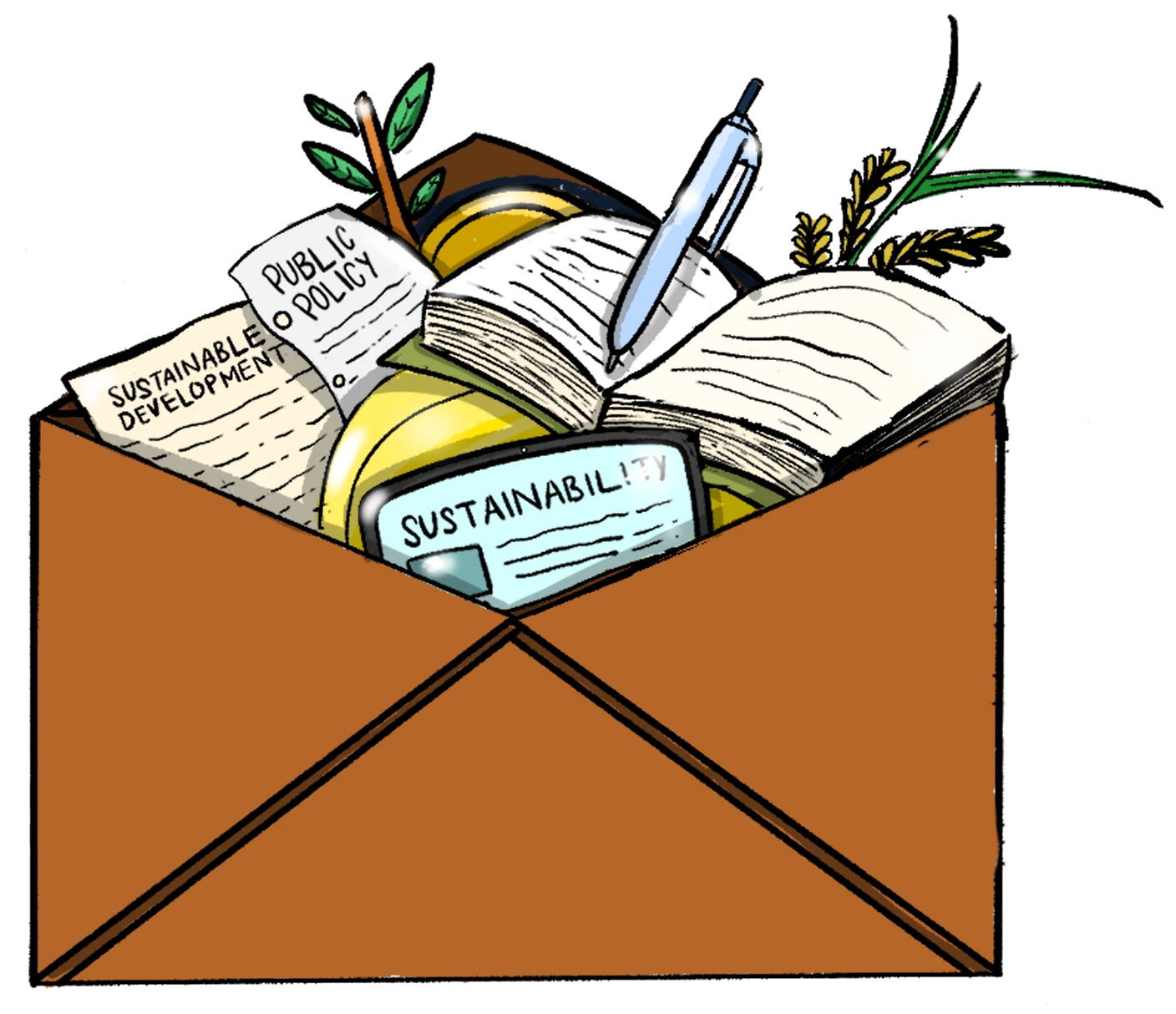
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Nisa is a Reporter & Research Assistant at Green Network Asia. She holds a bachelor's degree in International Relations from Gadjah Mada University. She has particular interest in research and journalism on social and environmental issues surrounding human rights.


 Mengatasi Banjir Jakarta dengan Solusi yang Mengakar
Mengatasi Banjir Jakarta dengan Solusi yang Mengakar  Memahami Keterkaitan antara Krisis Iklim dan Kerja Perawatan
Memahami Keterkaitan antara Krisis Iklim dan Kerja Perawatan  Menilik Potensi Digitalisasi Rantai Nilai Pangan untuk Mendukung Kesejahteraan Petani
Menilik Potensi Digitalisasi Rantai Nilai Pangan untuk Mendukung Kesejahteraan Petani  Bagaimana Bank Dapat Berperan dalam Mendorong Terciptanya Pekerjaan Layak
Bagaimana Bank Dapat Berperan dalam Mendorong Terciptanya Pekerjaan Layak  Menilik Tantangan dalam Pengembangan SAF berbasis Minyak Jelantah di Indonesia
Menilik Tantangan dalam Pengembangan SAF berbasis Minyak Jelantah di Indonesia  Mengintegrasikan Panas Perkotaan dalam Sistem Penanggulangan Bencana
Mengintegrasikan Panas Perkotaan dalam Sistem Penanggulangan Bencana