Salah Kaprah Penggunaan Istilah “Revenge Porn”
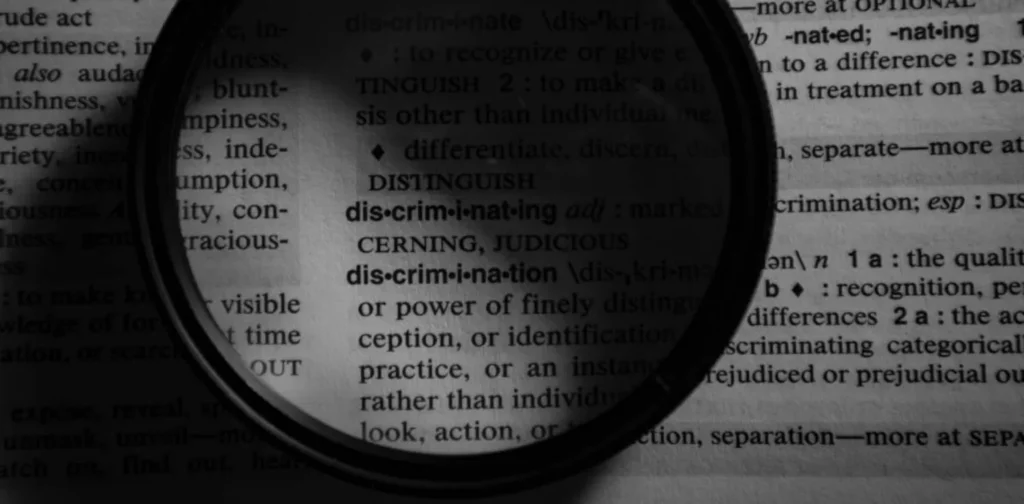
Foto: Nothing Ahead di Pexels.
Istilah “revenge porn” semakin populer di tengah masyarakat, terutama kalangan pengguna internet. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut bentuk kekerasan berbasis gender online atau kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni berupa penyebarluasan konten seksual atau konten intim seseorang tanpa persetujuan. Bentuk kekerasan seksual berbasis online semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penggunaan istilah revenge porn untuk menyebut kasus seperti ini merupakan salah kaprah yang mesti dipahami dan diluruskan.
Kasus di Beberapa Negara
Di tengah kemajuan teknologi, kasus kekerasan berbasis gender online meningkat di berbagai negara. Di Hong Kong, misalnya, lembaga Association Concerning Sexual Violence Against Women menyatakan bahwa mereka menangani 133 kasus terkait pelecehan seksual berbasis gambar di negara tersebut pada tahun 2020, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun 2019, sebelum pandemi terjadi.
Di Indonesia pun kondisinya serupa. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 510 kasus kekerasan berbasis gender siber yang mereka terima sepanjang tahun 2020, meningkat dari 126 kasus pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) mencapai 838 kasus—menjadikannya jenis Kekerasan Berbasis Gender terbanyak di Indonesia (66% dari total 1.271 kasus).
Di tengah meningkatnya kasus di berbagai tempat, kelompok advokasi telah memulai kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah ini. Sebagian masyarakat juga perlahan-lahan mulai berhenti menyalahkan korban dan memahami bahwa kesalahan sepenuhnya terletak pada pelaku.
Istilah “Revenge Porn” dan Salah Kaprah dalam Penggunaannya
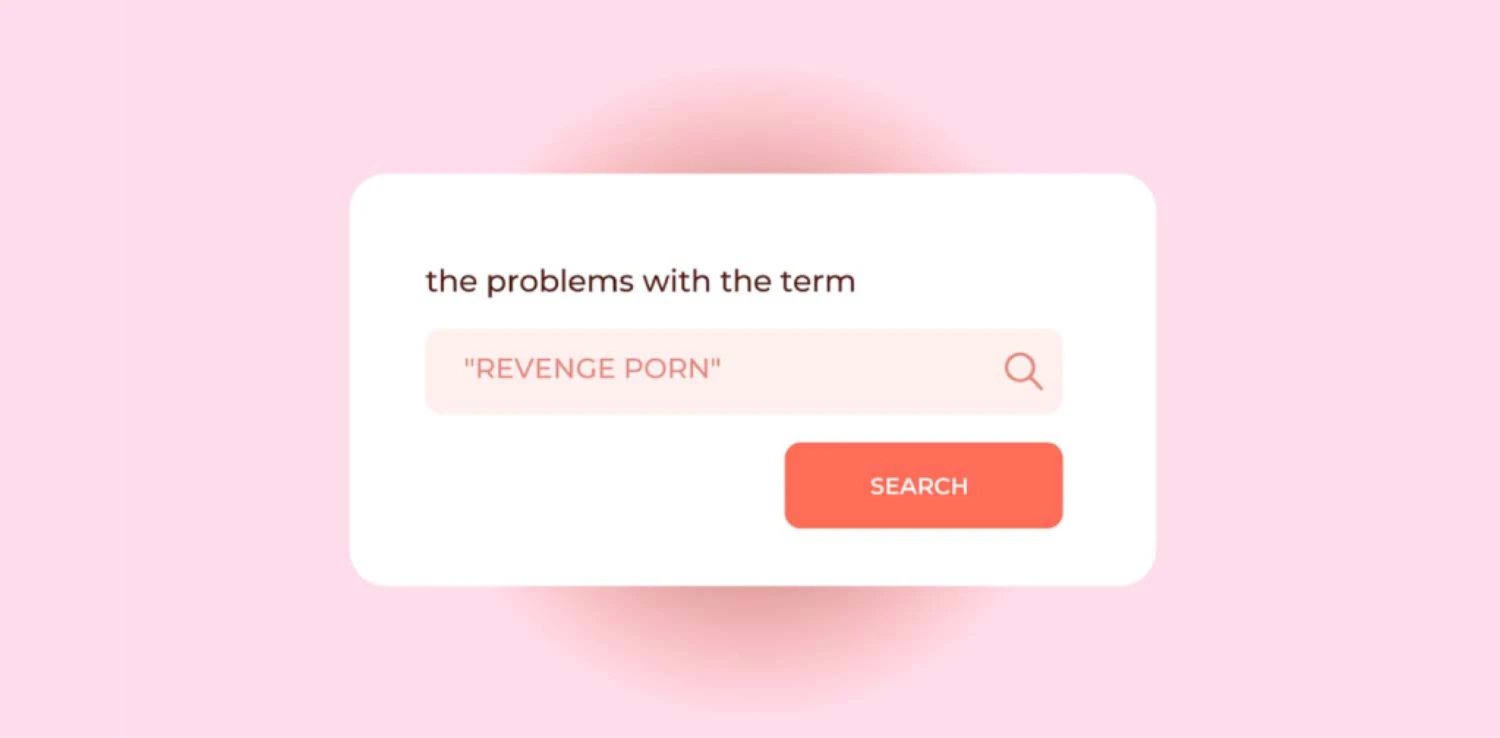
Yang menjadi persoalan, istilah “revenge porn” sering digunakan untuk menyebut bentuk-bentuk kekerasan yang telah disebutkan di atas. Ini merupakan persoalan serius karena penggunaan istilah ini seringkali keliru dan menyesatkan, serta sarat akan dampak yang merugikan, terutama terhadap korban.
Mary Anne Franks – yang penelitiannya banyak berfokus pada pelecehan online, kebebasan berbicara, diskriminasi, dan kekerasan – menunjukkan bahwa pelaku dari kasus-kasus yang disebut sebagai “revenge porn” tidak selalu termotivasi oleh balas dendam.
Purple Code, sebuah kelompok feminis di Indonesia, menunjukkan bahwa penyebarluasan konten intim yang dilakukan tanpa consent (persetujuan), seperti halnya kekerasan berbasis gender lainnya, sering kali dilakukan sebagai upaya untuk melanggengkan hierarki kekuasaan, yaitu kontrol dan dominasi terhadap korban, bukan atas dasar balas dendam.
Penggunaan istilah “balas dendam” sendiri sudah sesat sejak awal, karena seakan-akan menyiratkan bahwa korban telah menghasut pelaku dan melakukan sesuatu yang membuat pelaku pantas melakukan tindakan balas dendam. Disadari atau tidak, penggunaan istilah “revenge porn” dapat melanggengkan budaya menyalahkan korban.
Selain itu, terdapat mispersepsi dalam memaknai istilah “pornografi” di sini, yang menganggap bahwa memotret diri sendiri dalam keadaan telanjang atau melakukan tindakan seksual (atau mengizinkan orang lain mengambil gambar tersebut) dianggap sebagai pornografi. Padahal, membuat gambar eksplisit dalam konteks hubungan pribadi dan intim tidak boleh dianggap sebagai pembuatan pornografi.
Memang, pada saat penggunaan istilah “revenge porn” mulai booming, kasus yang menjadi contoh spesifik adalah adanya seseorang yang ‘membalas dendam’ dengan membagikan foto-foto mesra dengan pacarnya. Namun, istilah “revenge porn” kemudian juga digunakan untuk kasus-kasus lain, dimana banyak pelaku bertindak karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan, ketenaran, atau hiburan, termasuk peretas, penyedia rekaman kamera tersembunyi atau di bagian dalam rok, dan orang-orang yang menyebarkan foto ponsel curian.
Selain itu, “pornografi non-konsensual” dapat disalahartikan dengan merujuk pada genre pornografi tertentu yang menampilkan kurangnya persetujuan, dan bahkan pelecehan. Selain itu, istilah “pornografi” berisiko menimbulkan erotisme dari bentuk pelecehan seksual ini. Hal ini juga mendorong sensasionalisme di media massa ketika memberitakan kasus-kasus tersebut.
Erika Rackley, Profesor Hukum di Kent Law School, meyakini bahwa “revenge porn” adalah istilah yang digunakan oleh Hunter Moore, seorang pengusaha internet Amerika dan pendiri website pornografi ‘Is Anyone Up?’ yang memungkinkan pengguna memposting foto seksual orang lain tanpa persetujuan, disertai dengan informasi pribadi seperti nama dan alamat mereka. Moore menolak untuk menghapus foto-foto tersebut, dan dengan bangga menyebut dirinya sebagai “penghancur kehidupan profesional” dan akhirnya hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
Gunakan Istilah yang Lebih Akurat dan Inklusif
Lalu pertanyaannya: dengan istilah apa kita dapat menyebut kasus kekerasan seksual berupa penyebarluasan gambar intim tanpa persetujuan ini? Yang jelas, bentuk kekerasan seksual ini jauh lebih kompleks daripada “narasi balas dendam mantan kekasih”. Penelitian yang dilakukan oleh Nicola Henry dan Asher Flynn menemukan ada beragam cara membagikan gambar non-konsensual dalam berbagai komunitas online. Istilah “pelecehan seksual berbasis gambar” dibuat untuk merangkum berbagai bentuk kekerasan seksual online yang ada.
Para akademisi di balik “Beyond ‘Revenge Porn’: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse” mendukung penggunaan istilah ini. Mereka memandang bahwa istilah ini secara akurat menunjukkan bagaimana tindakan itu sendiri merupakan suatu bentuk pelecehan dan bagaimana bentuk pelecehan seksual ini terjadi melalui penyebarluasan gambar dan video seksual pribadi.
Pada akhirnya, memahami praktik-praktik ini sebagai pelanggaran seksual sangat penting untuk memastikan dukungan dan perlindungan yang tepat bagi para korban. Penting juga untuk mereformasi undang-undang yang menjamin anonimitas korban untuk mendorong mereka melaporkan kasus yang menimpa mereka. Penggunaan istilah “pelecehan seksual berbasis gambar” juga diharapkan dapat membatasi pembingkaian (framing) media dan masyarakat yang merugikan dan menjauhkan narasi yang menyalahkan korban.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Memastikan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan
Memastikan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan  Infrastruktur Tak Terlihat yang Dibutuhkan Pasar Karbon ASEAN
Infrastruktur Tak Terlihat yang Dibutuhkan Pasar Karbon ASEAN  Pemerintah Mulai Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo
Pemerintah Mulai Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo  Dari Sawah ke Tambak: Transformasi Desa Kecipir di Brebes dan Kerentanan Tersembunyi di Baliknya
Dari Sawah ke Tambak: Transformasi Desa Kecipir di Brebes dan Kerentanan Tersembunyi di Baliknya  Clean Cooking sebagai Pengganda Pembangunan di Afrika
Clean Cooking sebagai Pengganda Pembangunan di Afrika 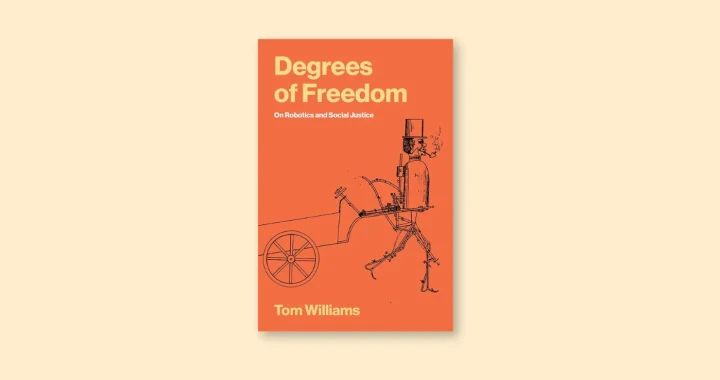 Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams
Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams