Komunitas Tuli dan Keberlanjutan: Mengubah Hambatan menjadi Modal Sosial untuk Pembangunan Inklusif
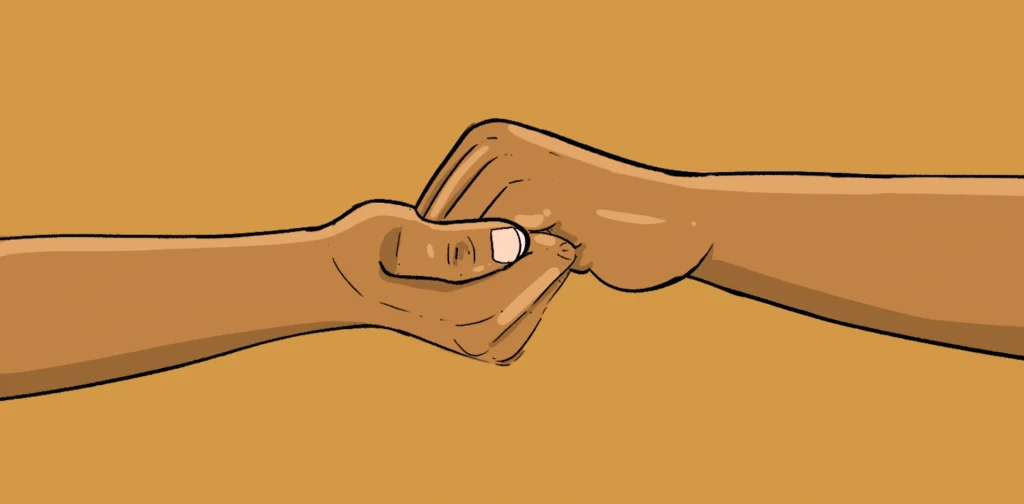
Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Ketika membicarakan keberlanjutan, perhatian publik cenderung lebih tertuju pada isu lingkungan dan ekonomi: energi bersih, ekonomi hijau, atau pengelolaan sumber daya alam. Namun, keberlanjutan sejati juga harus mencakup aspek sosial: keadilan, kesetaraan akses, dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat. Sayangnya, komunitas Tuli seringkali terpinggirkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, padahal peran mereka dapat menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat.
Sebagai anggota komunitas Tuli dan pegiat inklusi, saya mengalami sendiri sulitnya mengakses layanan publik dan informasi. Misalnya, proses mendaftar layanan administrasi atau mengakses informasi kesehatan sering membutuhkan usaha ekstra, seperti membawa juru bahasa isyarat (JBI) pribadi atau menghadapi staf yang tidak memahami bahasa isyarat. Situasi ini bukan hanya ketidaknyamanan individual, tetapi bentuk audisme struktural, gagasan diskriminasi sistemik yang menutup kesempatan komunitas Tuli untuk berpartisipasi penuh.
Hambatan Struktural dan Diskriminasi Sistemik
Data global dan nasional menunjukkan hambatan nyata bagi komunitas Tuli dalam berbagai aspek, termasuk ketenagakerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), penyandang disabilitas memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding populasi nondisabilitas, dan sering bekerja di sektor informal dengan upah rendah meskipun memiliki kompetensi yang setara. Di Indonesia, beberapa orang Tuli terpaksa bekerja sebagai juru parkir karena sulit memperoleh pekerjaan formal yang layak. Ketidaktersediaan akses bahasa isyarat di layanan publik memperkuat kesenjangan ini dan menegaskan bahwa eksklusi yang mereka alami bersifat struktural dan sistemik.
Selain hambatan pekerjaan, kurangnya representasi komunitas Tuli dalam perencanaan kebijakan juga menjadi masalah serius. Banyak kebijakan publik dibuat tanpa konsultasi dengan penyandang disabilitas, sehingga solusi yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan nyata mereka. Hal ini menunjukkan bahwa audisme tidak hanya terjadi dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga tertanam dalam sistem dan institusi.
Komunitas Tuli sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan
Di balik tantangan tersebut, komunitas Tuli memiliki potensi besar sebagai modal sosial. Bahasa isyarat dan jaringan komunitas membentuk solidaritas dan identitas kolektif yang memungkinkan partisipasi aktif dalam pendidikan, advokasi, dan pembangunan sosial. Potensi ini menjadi nyata ketika aksesibilitas dijamin. Misalnya, pelatihan bahasa isyarat Indonesia untuk ratusan petugas kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang bagi komunitas Tuli untuk mengakses layanan kesehatan secara penuh, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan kapasitas masyarakat.
Keterkaitan inklusi dengan keberlanjutan sosial semakin jelas jika dilihat dari perspektif SDGs dan prinsip “tidak ada seorang pun yang tertinggal”. Penyediaan akses bahasa isyarat dalam layanan publik, inklusi dalam dunia kerja, dan partisipasi komunitas Tuli dalam perencanaan kebijakan merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi sosial yang kuat. Tanpa langkah inklusif, diskriminasi struktural akan menghambat potensi modal sosial yang dimiliki komunitas Tuli, sehingga pembangunan berkelanjutan menjadi tidak merata.
Mewujudkan Pembangunan Inklusif melalui Transformasi Sistemik
Mewujudkan pembangunan yang inklusif memerlukan transformasi sistemik. Layanan publik harus menyediakan JBI dan mekanisme komunikasi alternatif agar informasi dapat diakses penuh oleh komunitas Tuli. Dunia kerja perlu memastikan rekrutmen dan proses penilaian yang inklusif, termasuk akomodasi wajar dan pelatihan kesadaran audisme untuk manajer dan staf HR. Partisipasi komunitas Tuli dalam perumusan kebijakan dan pembangunan harus dipastikan agar keputusan yang diambil relevan dan adil. Pendokumentasian pengalaman dan pengumpulan data komunitas Tuli penting sebagai dasar advokasi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih responsif.
Pada akhirnya, aksesibilitas bukan sekadar hak individu, tetapi fondasi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Mengalami sendiri audisme struktural dan keterbatasan akses informasi membuat saya semakin yakin bahwa komunitas Tuli harus dipandang sebagai aset sosial, bukan beban. Dengan memastikan inklusi bagi komunitas Tuli, kita membuka peluang bagi partisipasi aktif dalam ekonomi, pendidikan, dan advokasi sosial; memperkuat ketahanan masyarakat, dan memperkokoh fondasi keberlanjutan. Keberlanjutan sejati diukur dari kemampuan masyarakat untuk memastikan semua kelompok dapat berkontribusi, termasuk mereka yang selama ini sering terabaikan.
Editor: Abul Muamar
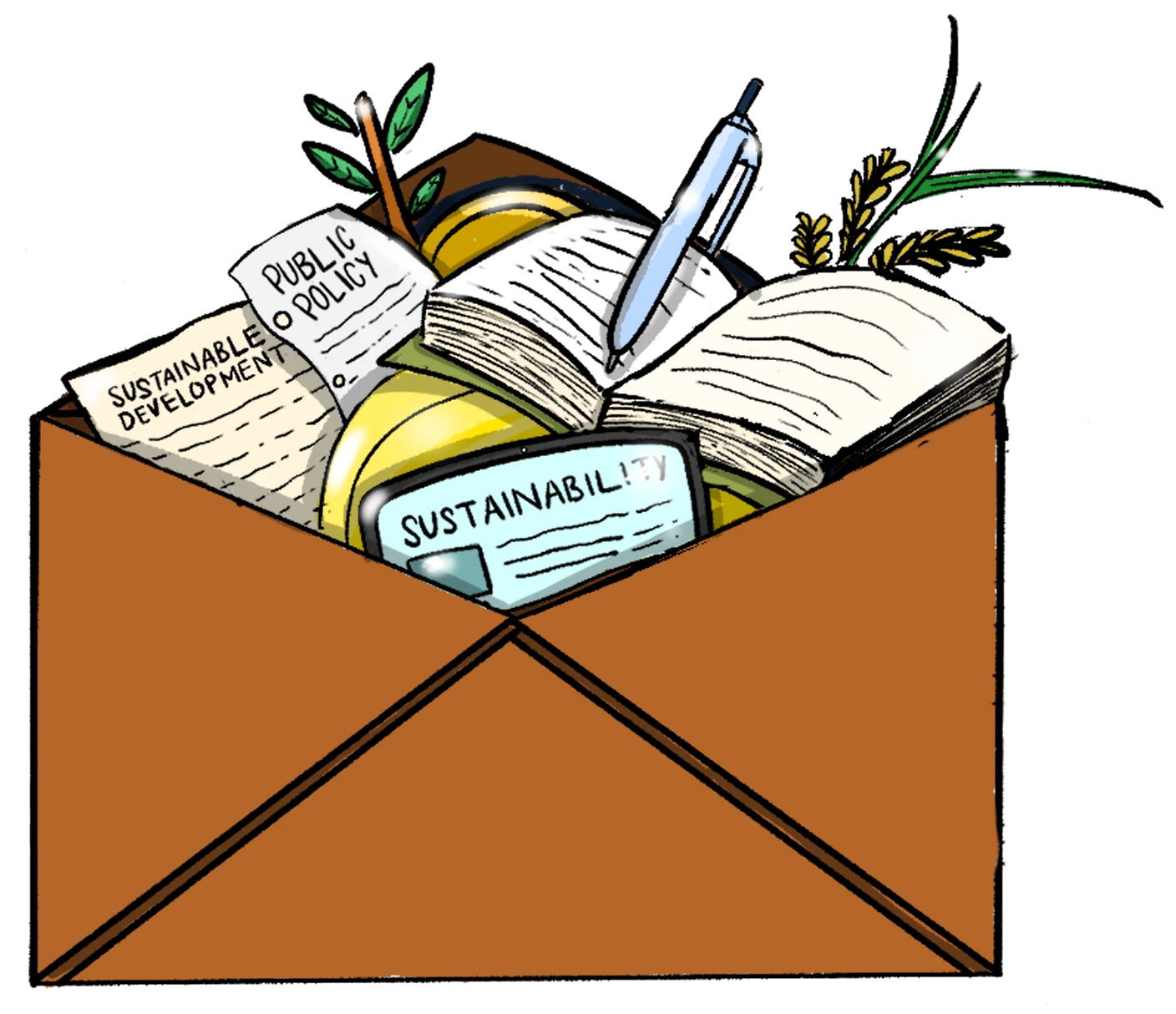
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Bagja adalah co-founder Silang.id dan praktisi budaya Tuli yang fokus pada isu media, aksesibilitas, keberagaman, dan inklusi.


 Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender
Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender  Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati
Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati  Bagaimana Program PLTS 100 GW dapat Mendukung Ketahanan Energi
Bagaimana Program PLTS 100 GW dapat Mendukung Ketahanan Energi  Kontaminasi PFAS di Amerika Serikat dan Desakan Petani ke Pemerintah
Kontaminasi PFAS di Amerika Serikat dan Desakan Petani ke Pemerintah  Mengatasi Kemiskinan Waktu di Tengah Meningkatnya Isu Kesehatan Mental
Mengatasi Kemiskinan Waktu di Tengah Meningkatnya Isu Kesehatan Mental  Kemunduran Besar dalam Pencapaian SDGs di Asia Pasifik
Kemunduran Besar dalam Pencapaian SDGs di Asia Pasifik