Upaya untuk Menghidupkan Kembali Tradisi Seke Maneke di Kepulauan Sangihe

Foto: Wiroj Sidhisoradej di Freepik.
Masyarakat daerah pesisir yang hidup berdampingan dengan laut memiliki beragam budaya dan tradisi bahari yang penting bagi kehidupan mereka. Tradisi ini dapat berupa sekumpulan nilai dan pengetahuan lokal, aktivitas, hingga kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun. Di daerah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, terdapat tradisi bahari bernama Seke Maneke yang merupakan tradisi penangkapan ikan tradisional yang ramah lingkungan. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan sempat berada di ambang kepunahan. Kini, masyarakat lokal berusaha menghidupkan kembali tradisi ini.
Potensi Perikanan Sangihe
Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 dan menjadi daerah untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan hingga konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Potensi perikanan Sangihe cukup besar, bahkan bisa mencapai 9% dari total keseluruhan potensi dari WPPNRI 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera.
Menurut data BPS, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sangihe pada tahun 2022 mencapai sekitar 3.700 ton per kuartal atau 14.800 ton dalam setahun. Sektor perikanan berkontribusi besar terhadap pendapatan dan pembangunan daerah sekaligus menjadi tumpuan hidup bagi nelayan di Sangihe.
Tradisi Seke Maneke
Seke Maneke adalah tradisi bahari di daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Dalam sebuah studi, seke dideskripsikan sebagai alat penangkapan tradisional yang terbuat dari bambu. Seke terdiri dari beberapa bagian, yaitu pandihe, elise, usu. Pandihe merupakan bagian utama dari seke, yaitu rakitan bambu yang disatukan dengan rotan hingga menyerupai pagar sepanjang 45 meter dan diberi ikatan daun kelapa di bagian atas dan bawahnya. Sementara elise adalah tali dari sabut kelapa yang mengikat kayu di kedua ujung agar pagar terhubung, sedangkan usu adalah bambu panjang yang digunakan untuk menopang seke agar tetap tegak dalam air. Kegiatan menangkap ikan yang menggunakan alat ini disebut dengan maneke.
Menangkap ikan dengan seke biasa dilakukan di permukaan sehingga tidak ada karang yang ikut terangkat. Dalam aturannya pun nelayan seke tidak diperbolehkan mengangkat karang. Selain itu, maneke hanya dilakukan selama 6 bulan dan 6 bulan sisanya adalah masa konservasi untuk pengembangbiakan ikan. Bagi masyarakat lokal, manake membawa kesadaran dan pengetahuan bahwa lingkungan adalah hal penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, adanya berbagai aturan dalam manake merupakan sebuah penghormatan terhadap alam semesta agar tidak ada eksploitasi sumber daya secara berlebihan.
Manake dilakukan oleh sekelompok nelayan berjumlah 40-50 orang yang memiliki struktur organisasi berdasarkan tugas yang dilakukan oleh setiap nelayan. Pemimpin manake disebut sebagai tonaseng pekuite yang bertugas tidak hanya memimpin pelaksanaan manake secara keseluruhan, tetapi juga memimpin upacara sebelum turun ke laut, melakukan ritual memanggil ikan, dan juga ikut menjaring ikan. Tonaseng dibekali oleh pengetahuan lokal yang diwarisi secara turun-temurun seperti soal pembagian wilayah laut hingga jenis-jenis ikan yang ada. Dalam satu pulau, biasanya terdiri dari banyak kelompok nelayan seke yang anggotanya dari satu pemukiman yang sama atau terikat oleh kelompok kekerabatan. Setiap kelompok mempunyai wilayah penangkapan masing-masing yang telah disepakati menurut kebiasaan untuk menghindari sengketa. Sekali melakukan mekane, nelayan bisa memperoleh hingga tiga sampai empat ton ikan yang kemudian diberikan kepada tokoh adat dan kelompok rentan terlebih dahulu sebelum dibagikan secara merata.
Dalam penelusuran sejarah, seke maneke diperkirakan bermula sejak tahun 1880-an. Sayangnya, praktik tradisional ini berangsur-angsur ditinggalkan sejak tahun 1990-an hingga awal 2000 karena nelayan yang beralih ke peralatan modern. Peralihan ini utamanya disebabkan karena faktor efisiensi mengingat proses pembuatan hingga pemeliharaan yang rumit sementara pengrajin seke semakin sedikit. Pada tahun 2003, tradisi ini juga mulai ditinggalkan di Pulau Para akibat adanya konflik perebutan wilayah penangkapan ikan.
Namun kini, masyarakat di Kepulauan Sangihe berupaya membangkitkan kembali tradisi seke maneke, seperti yang dilakukan oleh warga di Pulau Para Lelle pada Juni 2024. Upaya untuk menjaga agar keberadaan seke maneke juga dilakukan dengan menjadikannya sebagai salah satu daya tarik desa wisata. Dengan begitu, seke maneke dapat dilakukan sewaktu-waktu baik ketika ada kunjungan tamu ataupun jika ada wisatawan yang tertarik melihat dan terlibat langsung dalam kegiatan maneke.
Mendukung Nelayan Kecil
Tradisi seke maneke merupakan cerminan cara hidup masyarakat di Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dan menghargai alam, terutama laut, sebagai sumber utama penghidupan mereka. Upaya menghidupkan kembali dan melestarikan tradisi ini tidak dapat dibebankan kepada nelayan saja, tetapi juga butuh dukungan pemangku kepentingan terkait, terutama pemerintah daerah setempat. Dalam skala yang lebih luas, pemerintah juga dapat mengatasi berbagai hal yang mengancam sumber penghidupan nelayan, misalnya mengatasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing ataupun mengevaluasi ulang kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran laut. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memastikan akses nelayan kecil dalam mendapat sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan mereka.
Editor: Abul Muamar
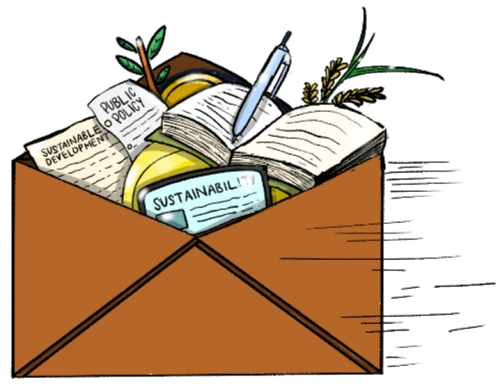
Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan GNA Indonesia.
Langganan Anda akan memberikan akses ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia, memperkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda sekaligus mendukung kapasitas finansial Green Network Asia untuk terus menerbitkan konten yang didedikasikan untuk pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder.
Pilih Paket LanggananNisa adalah reporter dan asisten peneliti di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki minat di bidang penelitian, jurnalisme, dan isu-isu seputar hak asasi manusia.


 Perempuan Penjaga Hutan di Negeri Patriarki: Kisah Mpu Uteun dan Ekofeminisme di Aceh
Perempuan Penjaga Hutan di Negeri Patriarki: Kisah Mpu Uteun dan Ekofeminisme di Aceh 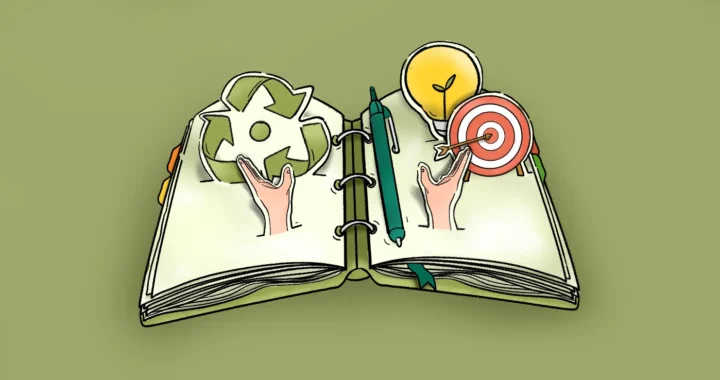 Menyampaikan Pengetahuan yang Dapat Diterapkan melalui Pelatihan Keberlanjutan
Menyampaikan Pengetahuan yang Dapat Diterapkan melalui Pelatihan Keberlanjutan  Menciptakan Keadilan Pajak untuk Kesejahteraan Bersama
Menciptakan Keadilan Pajak untuk Kesejahteraan Bersama 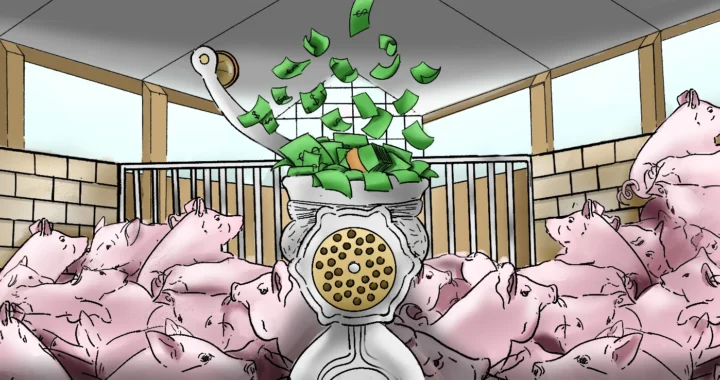 Menghentikan Pendanaan Peternakan Industri di Vietnam: Jalan Menuju Pendanaan Sistem Pangan yang Adil dan Berkelanjutan
Menghentikan Pendanaan Peternakan Industri di Vietnam: Jalan Menuju Pendanaan Sistem Pangan yang Adil dan Berkelanjutan  Pembaruan Kemitraan Indonesia-PBB dalam Agenda SGDs 2030
Pembaruan Kemitraan Indonesia-PBB dalam Agenda SGDs 2030  Bagaimana Para Perempuan di Kampung Sempur Bogor menjadi Aktor dalam Mitigasi Bencana Longsor
Bagaimana Para Perempuan di Kampung Sempur Bogor menjadi Aktor dalam Mitigasi Bencana Longsor