Bagaimana Memberi Makan Sembilan Miliar Orang Sembari Mendinginkan Langit?
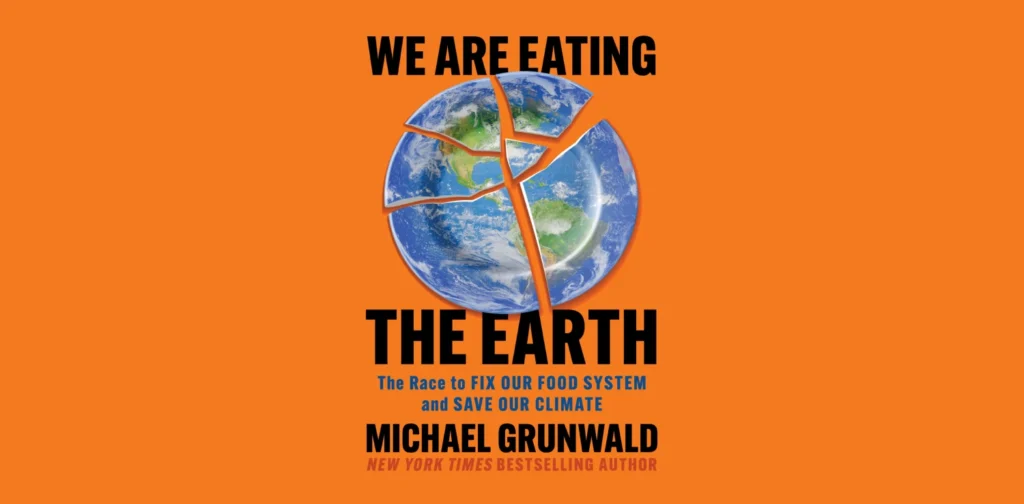
Cover buku “We Are Eating the Earth: The Race to Fix Our Food System and Save Our Climate” oleh Michael Grunwald. | Penerbit: Simon & Schuster (2025)
Ketahanan pangan Indonesia kini menghadapi ancaman berlapis. Mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, dan ketergantungan tinggi pada impor pangan strategis. Krisis iklim global telah mengacaukan siklus tanam, memperburuk kekeringan di kawasan timur, serta meningkatkan risiko gagal panen padi, jagung, dan kedelai. Pada saat bersamaan, urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian menggerus kemampuan produksi domestik. Kondisi ini jelas mengancam kemandirian pangan—yakni kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan sendiri dari sumber lokal—dan sekaligus menggerus kedaulatan pangan, yaitu hak rakyat untuk menentukan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai budaya setempat.
Sistem Pangan yang Ekstraktif
Indonesia tidak kekurangan tanah subur atau petani tangguh, tetapi sistem pangannya masih berpola ekstraktif dan bergantung sebagiannya pada komoditas global. Jika tidak segera dibenahi, negeri agraris ini bisa menjadi importir permanen di tengah krisis pangan dunia. Karena itu, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan harus dilihat bukan semata agenda ekonomi, melainkan strategi eksistensial bangsa di tengah percepatan krisis iklim global yang menekan sistem pangan dari hulu hingga hilir.
Untuk itu kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh soal sistem pangan, dan bagaimana mengupayakan keamanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan bagi bangsa sendiri; dan, bila mungkin, juga berkontribusi pada keamanan pangan di level regional dan global. Dalam keniscayaan seperti itu, karya jurnalis Michael Grunwald, We are Eating the Earth: The Race to Fix Our Food System and Save Our Climate (2025), yang baru saja saya temukan, menjadi sangat penting dan urgen untuk disimak.
Bumi dan Konsekuensi Penghuninya yang Rakus
Buku Grunwald adalah karya jurnalisme ilmiah yang brilian dan provokatif. Ia menelusuri akar persoalan bahwa sistem pangan dunia—lebih dari sektor energi—menjadi penyumbang utama kerusakan ekosistem bumi. Grunwald memusatkan kisahnya pada sosok ilmuwan Timothy Searchinger, peneliti dari Universitas Princeton yang mengubah cara dunia memahami hubungan antara lahan, pangan, dan iklim.
Pengantarnya, The Land Problem, membuka mata pembacanya dengan ironi besar: bahkan jika dunia berhenti memakai bahan bakar fosil, krisis iklim tetap tak teratasi jika kita terus “memakan Bumi” melalui ekspansi pertanian. Lahan pertanian kini seluas gabungan Asia dan Eropa, dan pertumbuhan populasi akan menuntut peningkatan produksi pangan 50% pada 2050. Jika cara bercocok tanam tak berubah, tambahan “selusin California” hutan akan musnah, menguapkan kemampuan Bumi menyerap karbon.
Lewat Bab 1 hingga 4, Grunwald menyuguhkan perjalanan intelektual Searchinger. Ia awalnya menentang bioenergi, gagasan bahwa menanam tanaman untuk bahan bakar adalah solusi hijau. Dalam artikelnya yang dimuat di jurnal Science, Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change (Searchinger, et al, 2008), Searchinger menunjukkan bahwa biofuel justru memperparah emisi karena mendorong pembukaan hutan baru untuk mengganti lahan pangan yang hilang. Ia memperkenalkan konsep carbon opportunity cost—setiap hektare yang digunakan untuk bahan bakar berarti kehilangan peluang menyerap karbon atau menanam pangan. Penemuan ini mengguncang dunia kebijakan sekaligus mematahkan mitos bioenergi sebagai solusi iklim.
Namun dalam perjalanan intelektualnya, Searchinger menyadari bahwa pertanian makanan jauh lebih destruktif lagi. Daging sapi, misalnya, menggunakan 80% lahan pertanian dunia tetapi hanya menyumbang sebagian kecil kalori global. Grunwald menyoroti bagaimana nafsu makan kita terhadap burger menjadi penyebab deforestasi Amazon dan naiknya emisi metana dari peternakan. Perbandingan mengejutkan muncul: “per kilogram, daging sapi menghasilkan 50 kali lebih banyak emisi dibanding batubara.” Dengan demikian, krisis iklim kemudian disadari bukan hanya akibat pembakaran bahan bakar fosil, tetapi juga akibat pola makan umat manusia.
Bab 5, The Menu, menjadi inti ilmiah buku. Di sini Grunwald menguraikan laporan raksasa Creating a Sustainable Food Future (WRI, 2019) karya Searchinger, yang menawarkan 22 solusi untuk menutup tiga celah global pada 2050, yang tujuannya: (1) meningkatkan produksi pangan 50%; (2) menurunkan emisi pertanian 75%; dan (3) melakukannya tanpa memperluas lahan. Solusi yang diajukan itu di antaranya meliputi: mengurangi konsumsi daging merah, meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, mencegah pemborosan pangan, membatasi bioenergi, serta mempercepat inovasi benih, pakan, dan teknik pertanian presisi.
Empat bab berikutnya, Bab 6–9 mengulas berbagai upaya manusia mengejar resep ideal itu. Bab It’s the Food That Needs to Change, misalnya, menceritakan pertemuan Searchinger dengan tokoh-tokoh seperti Bruce Friedrich dari Good Food Institute yang mempromosikan daging tiruan dari bahan nabati juga daging yang dibuat di laboratorium. Grunwald menilai inovasi seperti Impossible Burger atau cultivated meat bukanlah solusi tunggal, tetapi bagian dari transisi yang perlu: mengurangi permintaan terhadap sapi, sumber emisi paling tinggi. Bab The Fake Meat Hype Cycle memaparkan naik-turun euforia terhadap daging alternatif itu, dari lonjakan investasi hingga realitas pasar yang sulit.
Di sisi yang lain, bab The Soil Fantasy membongkar mitos kesaktian pertanian regeneratif. Grunwald memuji niat baik petani yang menanam cover crop dan mengurangi pupuk, tetapi menegaskan bahwa sekuestrasi karbon di tanah tidak bisa menandingi laju emisi dari deforestasi dan peternakan. Slogan “soil will save us” dianggap terlalu optimistis jika tidak dibarengi reformasi struktural dalam konsumsi dan kebijakan lahan.
Dua bab berikutnya, More Beef, Less Land dan More Crops, Less Land menyoroti keberhasilan lokal, misalnya peternakan tropis di Amazon yang menggandakan produktivitas tanpa memperluas hutan, serta inovasi agronomi yang memungkinkan panen ganda atau penggunaan sisa tanaman (seperti jerami padi) sebagai pakan. Ide “produce and protect” menjadi mantra baru yang menarik: meningkatkan hasil di lahan pertanian yang ada agar lahan alami seperti hutan bisa dilindungi.
Bab 10–11 serta Epilog bertajuk “Can We Do This?” menutup buku dengan realisme. Grunwald menegaskan bahwa perubahan sistem pangan tidaklah bisa sesederhana berhenti makan daging merah saja atau beralih sepenuhnya ke pertanian organik. Ia mengingatkan bahwa delapan miliar konsumen, yang terus bakal bertambah, dan enam ratus juta petani tidak bisa diubah hanya dengan seruan dan gerakan moral. Diperlukan investasi besar, penelitian terarah, dan kebijakan yang menilai setiap hektare sebagai aset pangan dan karbon sekaligus. “Every acre is sacred,” begitu kata Grunwald. Prinsip ini menggantikan anggapan lama bahwa lahan adalah sumberdaya bebas. Meski tantangannya berat, Grunwald optimistis. Seperti halnya energi terbarukan yang dulu tampak mustahil, perubahan pangan pun mungkin terjadi jika umat manusia cukup serius melakukannya. Begitu pesan Grunwald.
Menimbang Narasi Grunwald
Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuan Grunwald menjembatani sains, kebijakan, dan narasi manusia dengan lincah dan menarik. Ia bukan sekadar menulis laporan ilmiah, melainkan menyusun kisah yang benar-benar hidup tentang bagaimana ide—dan keengganan manusia untuk berubah—membentuk masa depan Bumi. Dengan menjadikan Searchinger sebagai karakter sentral, Grunwald mengubah laporan teknis WRI menjadi kisah epik intelektual: perjuangan seorang ilmuwan melawan arus politik, ekonomi, dan ego sektor energi yang luar biasa besar, bahkan menakutkan.
Kelebihan kedua adalah kerangka berpikirnya yang sistemik. Grunwald menolak pandangan parsial yang memuja satu solusi—baik bioenergi, veganisme, maupun pertanian regeneratif—dan mengingatkan bahwa “tidak ada peluru perak” dalam menyelesaikan isu pangan dan iklim sekaligus. Pendekatannya realistis: dunia harus menanam lebih banyak, memelihara lebih sedikit ternak, membuang lebih sedikit makanan, dan memuliakan setiap hektare Bumi. Dengan caranya yang demikian, buku ini menjadi jembatan penting antara literatur ilmiah—seperti laporan IPCC atau WRI—dan perbincangan publik yang lebih luas.
Bahasanya juga berwarna, bahkan jenaka, membuat tema berat menjadi mudah diikuti. Gaya jurnalisme Grunwald yang kaya metafora—misalnya “menyapu rumah sambil menghancurkan vacuum cleaner”—memberi kekuatan retoris yang jarang ditemukan dalam literatur lingkungan kontemporer. Ia mampu menulis dengan empati tanpa kehilangan ketajaman logika.
Namun, tentu saja, buku ini juga memiliki ruang perbaikan. Pertama, fokusnya sangat Amerika dan Eropa-sentris. Meski menyebut contoh dari Amazon dan Afrika, ia kurang memberi ruang bagi perspektif Global South, termasuk Asia Tenggara yang menghadapi dinamika pangan dan lahan yang unik. Kedua, walau menyatakan perlunya keragaman, pendekatan Grunwald cenderung techno-optimistic—percaya bahwa inovasi genetik, bioteknologi, dan rekayasa pasar akan menyelamatkan sistem pangan—tanpa cukup mengulas dimensi keadilan sosial, kepemilikan lahan, dan hak petani kecil. Padahal, transisi pangan berkelanjutan tidak hanya soal efisiensi, tapi juga distribusi kekuasaan dan akses.
Selain itu, narasi personal Searchinger meski menarik, membuat buku ini agak terasa seperti biografi, bahkan cerita kepahlawanan seorang ilmuwan. Sementara, isu pangan dan iklim sesungguhnya bersifat kolektif dan punya ragam yang luas. Menurut selera saya, akan lebih kuat jika Grunwald menampilkan lebih banyak suara dari petani, aktivis, atau komunitas adat yang menjaga lahan.
Meski demikian, kekuatan analitik dan kedalaman risetnya menjadikan buku ini tetap bakal menjadi referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami hubungan antara pangan dan krisis iklim. Termasuk bagi saya, yang membaca buku ini dari latar belakang situasi keindonesiaan mutakhir. Para penulis isu-isu lingkungan favorit saya juga luar biasa positif dalam mendukung buku ini. David Wallace-Wells bersaksi bahwa “We Are Eating the Earth is the most vivid and inspiring reckoning with this wicked problem written in this age of climate crisis.” Demikian juga, “We Are Eating the Earth is a savory, science-salted meal of provocative thinking about food.” Begitu kata Jeff Goodell.
Membangun Sistem Pangan Climate-Smart di Indonesia
Terus terang, membaca buku ini membuat saya mengunyah dan menelan kenyataan pahit. Pangan yang kita makan setiap hari adalah salah satu penyebab utama Bumi memanas. Ketika menuliskan artikel resensi ini, saya mengunyah tahu yang sungguh nikmat. Saya tak tahu dari mana kedelainya berasal. Yang jelas, ia datang dari tempat jauh, sangat mungkin ribuan kilometer jaraknya dari tempat produksi tahu itu, dan entah berapa jauhnya lagi dari tempat saya mengunyahnya. Dan lantaran digoreng di kedai tempat saya duduk, hampir pasti ada juga jejak karbon lain dari kebun sawit, dari mana minyak gorengnya berasal.
Namun dari kepahitan seperti itu juga lahir kesadaran baru—bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita menanam, memelihara, dan mengonsumsi pangan sekarang dan di masa mendatang. Grunwald mengingatkan bahwa setiap hektare sawah, hutan, dan laut dari mana makanan kita berasal adalah sakral. Prinsip every acre is sacred patut menjadi etika baru bagi sistem pangan kita.
Indonesia yang luar biasa luas dan subur jelas memiliki peluang besar menjadi pelopor climate-smart food system. Kita bisa membangun pertanian rendah emisi, melakukan diversifikasi protein nabati dan sumber laut, serta menegakkan perlindungan terhadap lahan gambut dan mangrove sebagai penopang pangan sekaligus penyerap karbon. Untuk itu, kita perlu ilmuwan setajam Searchinger, jurnalis seberani Grunwald, aktivis segigih Bruce Friedrich, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada petani kecil.
Buat saya, buku ini bukan sekadar bacaan sumber asupan gizi pengetahuan yang penting, melainkan panggilan moral yang begitu nyaring. Grunwald menyeru kita semua untuk menghentikan kebiasaan ‘memakan’ Bumi, sebelum Bumi benar-benar tak (mau atau bisa) lagi memberi makan kita semua. Dan, pilihan untuk itu, lagi-lagi ada di tangan kita semua.
Editor: Abul Muamar
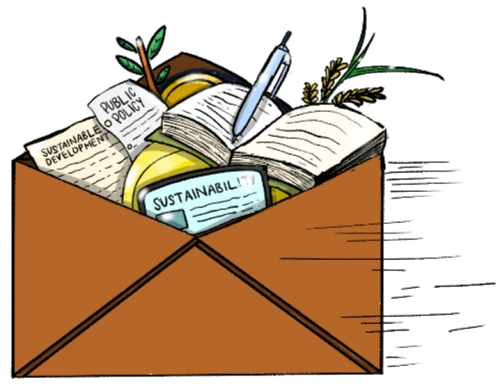
Join Membership Green Network Asia – Indonesia
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Join SekarangJalal is a Senior Advisor at Green Network Asia. He is a sustainability consultant, advisor, and provocateur with over 25 years of professional experience. He has worked for several multilateral organizations and national and multinational companies as a subject matter expert, advisor, and board committee member in CSR, sustainability, and ESG. He has founded and become a principal consultant in several sustainability consultancies as well as served as a board committee member and volunteer at various social organizations that promote sustainability.


 Menghidupkan Kembali Sungai-Sungai yang Tertimbun dengan Daylighting
Menghidupkan Kembali Sungai-Sungai yang Tertimbun dengan Daylighting  Menilik Simpul Antara ‘Gajah Terakhir’ dan Banjir di Sumatera
Menilik Simpul Antara ‘Gajah Terakhir’ dan Banjir di Sumatera  Meningkatnya Angka Pengangguran Sarjana dan Sinyal Putus Asa di Pasar Kerja Indonesia
Meningkatnya Angka Pengangguran Sarjana dan Sinyal Putus Asa di Pasar Kerja Indonesia  Wawancara dengan May Tan-Mullins, CEO dan Rektor University of Reading Malaysia
Wawancara dengan May Tan-Mullins, CEO dan Rektor University of Reading Malaysia  Memperkuat Ketahanan Masyarakat di Tengah Meningkatnya Risiko Bencana
Memperkuat Ketahanan Masyarakat di Tengah Meningkatnya Risiko Bencana  UU KUHAP 2025 dan Jalan Mundur Perlindungan Lingkungan
UU KUHAP 2025 dan Jalan Mundur Perlindungan Lingkungan