Mengeksplorasi Potensi Logam Tanah Jarang sebagai Kunci Transisi Energi di Indonesia
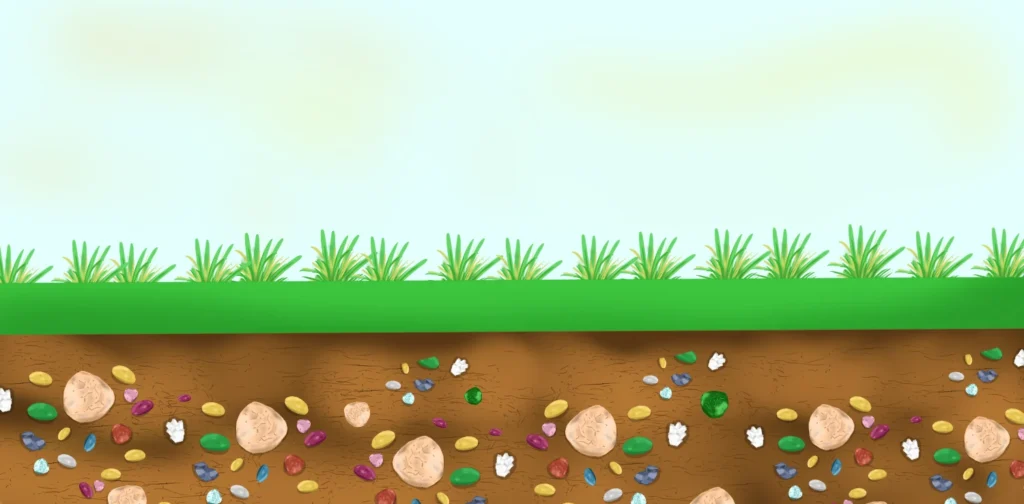
Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Bumi kita tengah berada dalam keadaan darurat iklim. Menurut World Meteorological Organization (WMO), tahun 2024 mencatat kenaikan suhu global sebesar 1,5°C—menjadikannya tahun terpanas dalam 175 tahun terakhir. Pemanasan ini tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga memicu berbagai fenomena cuaca ekstrem: banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga naiknya permukaan laut. Akar dari masalah ini adalah ketergantungan manusia pada energi fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) dalam jumlah besar.
Untuk menekan laju pemanasan global, dunia harus mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Namun, transisi ini tidak bisa terwujud tanpa bahan baku penting—salah satunya adalah logam tanah jarang (rare earth elements/REEs).
Apa Itu Logam Tanah Jarang?
Logam tanah jarang (LTJ) merupakan sebuah kelompok dalam golongan mineral kritis, dimana kelompok ini terdiri dari 17 unsur kimia yaitu Scandium (Sc), Yttrium (Y), serta 15 unsur dalam golongan lantanida–Lantanum (La), Serium (Ce), Praseodymium (Pr), Neodymium (Nd), Promethium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Tulium (Tm), Ytterbium (Yb), dan Lutium (Lu). Meski dinamakan “tanah jarang”, unsur-unsur ini sebenarnya cukup melimpah di kerak bumi, bahkan beberapa di antaranya lebih umum dari emas. Namun, unsur-unsur ini memang jarang ditemukan dalam bentuk yang terkonsentrasi atau mudah diekstrak.
REE/LTJ memiliki sifat-sifat unik—magnetik, konduktif, tahan suhu tinggi, dan luminesen—yang menjadikannya bahan baku utama dalam teknologi modern: magnet permanen, baterai kendaraan listrik, layar ponsel, lampu LED, hingga perangkat militer dan satelit.
Peran Vital dalam Transisi Energi
Dalam konteks energi bersih, logam tanah jarang dapat menjadi material kunci. Menurut Jyothi et al. (2020), Neodymium (Nd) dan Dysprosium (Dy) dapat digunakan untuk membuat magnet kuat pada motor kendaraan listrik dan turbin angin. Sel bahan bakar menggunakan Yttrium (Y) sebagai katalis; sedangkan Europium (Eu), Terbium (Tb), dan Cerium (Ce) digunakan dalam lampu LED dan panel surya.
Tanpa pasokan logam tanah jarang yang stabil, produksi teknologi rendah karbon akan terganggu. Karena itu, REE bukan hanya soal teknologi, tetapi juga isu strategis dalam geopolitik energi global.
Pemanfaatan Strategis REE di Pasar Global
Saat ini, China mendominasi pasar logam tanah jarang dunia. Menurut USGS (2025), China memiliki sekitar 44 juta ton cadangan REE dari total global 90 juta ton, dan memproduksi lebih dari 270 ribu ton per tahun. Ketergantungan global terhadap satu negara menimbulkan risiko besar, apalagi di tengah ketegangan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara lain berlomba memperkuat rantai pasok REE dan mendorong daur ulang logam tanah jarang dari barang elektronik bekas.
Beberapa produk yang telah memanfaatkan logam tanah jarang dapat ditemukan di berbagai industri. Pesawat tempur F-35 Amerika Serikat mengandung 418 kg material REE, iPhone 12 memanfaatkan 98% REE daur ulang, Nissan Leaf dan Toyota Prius yang diproduksi di Jepang menggunakan REE dalam baterai dan sistem motoriknya. Di Jerman, turbin angin Siemens Gamesa memakai Neodymium (Nd) dan Praseodymium (Pr) untuk magnet permanennya.
Potensi Besar REE di Indonesia
Indonesia tidak ketinggalan dalam potensi sumber daya ini. Berdasarkan data Badan Geologi (2019), sumber daya logam tanah jarang Indonesia tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Sulawesi, hingga Papua. Potensi ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar ton, sebagian besar sebagai mineral ikutan dari penambangan timah, seperti di Bangka Belitung; dan sebagian lain dari penambangan mineral-mineral lainnya seperti nikel, bauksit, dan bahkan batu bara.
Di Bangka Belitung saja, potensi REE mencapai 7 juta ton. Namun sayangnya, pengembangan industri logam tanah jarang di Indonesia masih dalam tahap awal. Belum ada fasilitas pengolahan skala besar karena proses ekstraksi yang kompleks, mahal, serta memerlukan penanganan limbah radioaktif secara hati-hati. Hingga saat ini, hanya ada pilot plant kecil berkapasitas 50 kg/hari yang dikembangkan oleh BRIN, salah satunya untuk mendukung produksi baterai kapal listrik.
Eksplorasi REE Membutuhkan Pendekatan Geofisika
Penambangan REE telah diatur dalam PP 96/2021 Pasal 2 Ayat 1 (b), yang mengkategorikan REE ke dalam golongan mineral logam yang dapat dieksplorasi melalui izin pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut, PT Timah tbk bersama MIND ID tengah mengupayakan pengembangan REE melalui revitalisasi dan modifikasi Pilot Plant untuk pengolahan mineral monasit sebagai sumber REE di Bangka Belitung. Pilot Plant REE ini mendukung program hilirisasi mineral nasional.
Namun, meski secara regulasi pemerintah telah memberikan dukungan, keterbatasan teknologi canggih masih menjadi tantangan utama yang menghambat eksplorasi dan inventarisasi cadangan secara optimal. Padahal, eksplorasi REE sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 2015, menunjukkan bahwa isu ini bukanlah hal baru dan seharusnya bisa ditangani secara progresif.
Karena sulitnya melakukan eksplorasi REE, dibutuhkan pendekatan geofisika untuk dapat melihat pemetaan bawah permukaan tanpa pengeboran langsung. Metode ini dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan eksplorasi geologi yang membutuhkan pengeboran langsung. Beberapa metode geofisika yang relevan untuk eksplorasi REE antara lain:
- Magnetik: mendeteksi perubahan medan magnet akibat variasi suseptibilitas batuan.
- Elektromagnetik: memetakan konduktivitas batuan.
- Radiometrik: menelusuri kandungan unsur radioaktif alami.
- Seismik refleksi: memetakan lapisan dan struktur geologi berdasarkan pantulan gelombang seismik.
- Tomografi geolistrik: mengidentifikasi zona konduktif berdasarkan variasi resistivitas batuan.
Penelitian Nugroho et al. (2023) di Papua menggunakan survei udara elektromagnetik dan radiometrik untuk mendeteksi dan memetakan potensi REE. Zulfikar et al. (2021) di Bintan menggunakan seismik refleksi untuk memetakan endapan alluvial yang memiliki potensi REE. Sementara Tang et al. (2024) di China menunjukkan keberhasilan pemetaan zona REE pada zona retakan menggunakan tomografi geolistrik yang menunjukkan resistivitas rendah (bersifat konduktif).
Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi
Logam tanah jarang adalah kunci masa depan energi bersih. Indonesia memiliki sumber daya, lokasi strategis, dan regulasi pendukung untuk memanfaatkannya. Namun, kolaborasi global, investasi pada pengembangan teknologi, dan riset berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Dengan mengembangkan ekosistem industri REE, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan nasional dan menjadi pemain penting dalam rantai pasok energi bersih global, terutama di tengah krisis iklim yang mendesak.
Editor: Abul Muamar dan Lalita Fitrianti
Terbitkan thought leadership dan wawasan berharga Anda bersama Green Network Asia, pelajari Panduan Artikel Opini GNA.
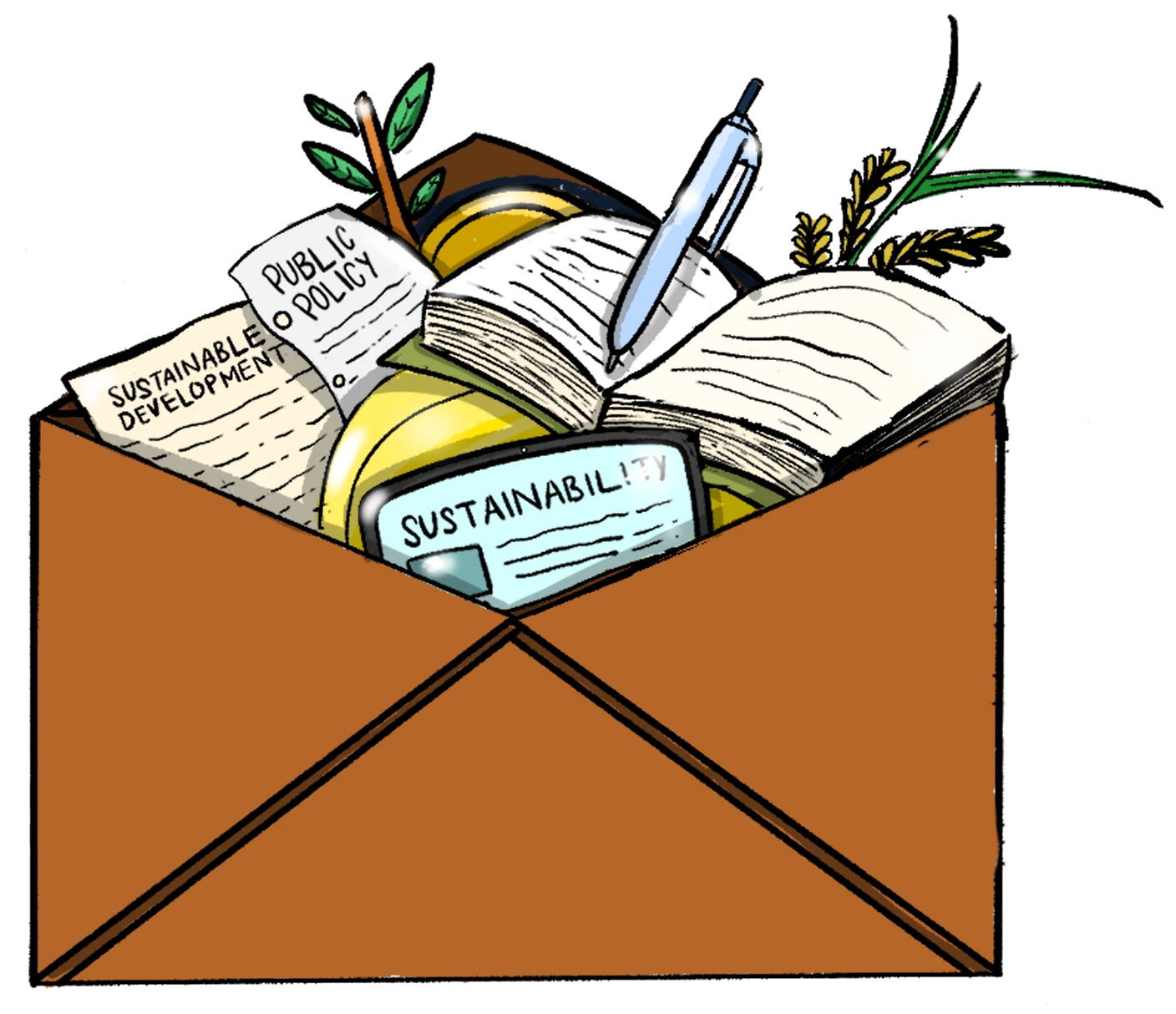
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Nova adalah mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia memiliki minat dalam eksplorasi sumber daya alam, energi berkelanjutan, dan geofisika terapan.


 Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya  Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air
Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air  PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut  Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa  Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?
Overpopulasi Ikan Sapu-Sapu di Sungai Ciliwung: Pemulihan Lingkungan atau Bahaya?  Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit
Perlawanan Pekerja Gig di India terhadap Tekanan Layanan Pengantaran 10 Menit