Meninjau Second NDC Indonesia dan Tantangan dalam Penerapannya

Foto: Famingjia Inventor di Unsplash.
Krisis iklim yang terjadi saat ini dan kurang memadainya tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasinya memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil langkah yang lebih kuat. Sebagai bagian dari komitmen global di bawah Persetujuan Paris, Indonesia telah menerbitkan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) sebagai pembaruan dari komitmen sebelumnya untuk memperkuat target pengurangan emisi. Apa yang ditegaskan dalam Second NDC Indonesia dan apa saja tantangan yang menanti di depan?
Dampak Krisis Iklim
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu bumi sekitar 1°C dibandingkan masa pra-industri, dengan kisaran antara 0,8°C hingga 1,2°C. Kondisi tersebut memicu cuaca ekstrem dan terjadinya bencana iklim di berbagai belahan dunia.
Indonesia termasuk dalam negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sepanjang tahun 2025, telah terjadi 2.684 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem. Kondisi tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur, produksi pertanian dan kerawanan pangan, hilangnya mata pencaharian, hingga jatuhnya korban jiwa. Di sisi lain, deforestasi dan ketergantungan terhadap energi fosil secara nasional masih cukup tinggi sehingga turut memperparah kenaikan emisi yang terjadi.
Langkah Indonesia dalam Mengatasi Krisis Iklim
Komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai Net Zero Emission 2060 telah ditegaskan sejak menjadi bagian dari Perjanjian Paris tahun 2015. Dari perjanjian tersebut kemudian terbit First National Determined Contribution (FNDC) pada tahun 2016 sebagai komitmen nasional dalam mengurangi emisi. Seiring perjalanan, FNDC mengalami beberapa perkembangan untuk penguatan komitmen iklim nasional, hingga pada tahun 2025 terbit Second National Determined Contribution (Second NDC).
Second NDC atau NDC 3.0 diklaim disusun dengan lebih menyesuaikan pada target Persetujuan Paris dan target rencana pembangunan nasional 2025-2029. Dalam dokumen ini, level emisi tahun 2019 yang selaras dengan hasil Global Stocktake Decision dijadikan sebagai patokan perhitungan skenario emisi, berbeda dari FNDC yang menggunakan dasar Business as Usual (BAU) yang menentukan target persentase pengurangan emisi menggunakan patokan perkiraan jumlah emisi yang akan muncul ketika ekonomi berjalan seperti biasa tanpa intervensi.
Second NDC hadir dengan skenario Low Carbon Compatible Pathway (LCCP) yang memiliki dua asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi yakni: LCCP_Low (LCCP_L) yang mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030 mencapai 6,0 persen, dan 6,7 persen pada tahun 2035; dan skenario LCCP_High (LCCP_H) yang mengasumsikan pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029. Second NDC memberikan perbandingan skenario kebijakan saat ini (Current Policy Scenario/CPOS) yang menggambarkan upaya pengurangan emisi berdasarkan kemampuan sumber daya domestik dengan skenario LCCP yang dianggap lebih selaras dengan Perjanjian Paris.
Pada skenario CPOS, diperkirakan emisi akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 2.000.000 Gg CO2eq (2 juta gigagram / 2 gigaton emisi setara karbon dioksida) pada tahun 2050 dan baru akan menurun setelahnya. Pada skenario LCCP_L, emisi akan mencapai puncaknya sekitar 1.000.000 Gg CO2eq – 1.400.000 Gg CO2eq pada tahun 2030 dan menurun secara bertahap setelahnya hingga mendekati nol emisi pada tahun 2050 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060. Pada skenario LCCP_H, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, emisi tertinggi pada tahun 2030 mencapai 1.500.000 Gg CO2eq, kemudian stagnan hingga tahun 2035, dan menurun secara signifikan setelahnya hingga mencapai nol emisi pada tahun 2060.
Second NDC Indonesia dan Tantangan yang Dihadapi
Adapun hal utama dari mitigasi yang ditargetkan dalam Second NDC mencakup lima sektor yakni energi, limbah, Industrial Processes and Product Use (IPPU), pertanian, dan Forestry and land-use (FOLU).
Sektor energi adalah penyumbang emisi paling besar, yakni hingga 55 persen. Target pada sektor ini adalah peningkatan bauran energi terbarukan sebesar 27-33 persen pada tahun 2035 dan puncak emisi pada tahun 2038. Aksi mitigasi kunci pada sektor ini masih tetap bertumpu pada penggunaan energi terbarukan, efisiensi penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik. Namun, hal tersebut akan sulit dilakukan ketika energi penghasil emisi tinggi seperti batubara masih tetap dimanfaatkan secara masif. Indonesia memiliki armada batubara terbesar kelima di dunia dan masih akan menambah kapasitasnya hingga 2030. Selain itu, meskipun pada tahun 2022 telah diterbitkan moratorium pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru, pembangkit listrik yang telah tercantum dalam rencana nasional dan pembangkit listrik yang dikelola secara mandiri oleh industri masih dikecualikan.
Di sektor limbah, ditargetkan penurunan emisi sebesar 10 juta ton CO2e dengan berorientasi pada pemanfaatan sampah menjadi sumber energi. Hal ini dilakukan dengan merehabilitasi tempat pembuangan sampah terbuka untuk sampah padat dari kegiatan rumah tangga menjadi tempat pembuangan sampah tertutup yang dilengkapi dengan sistem pemulihan gas metana. Untuk limbah cair; dilakukan pengelolaan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), biodigester yang dilengkapi dengan penangkapan dan pemanfaatan metana, dan penerapan fasilitas pengolahan air limbah hitam. Untuk limbah industri; dilakukan pengolahan limbah cair untuk pemulihan metana dan lumpur agar dapat digunakan kembali sebagai sumber energi atau bahan, serta pemanfaatan empty fruit bunch (EFB/limbah tandan kosong kelapa sawit). Namun, upaya ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Dari 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun, sekitar 12,37 juta ton masih dibuang melalui open dumping (menimbun sampah), dan 22,12 juta ton terbuang ke lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan sampah masih belum memadai.
Di sektor IPPU ditargetkan pengurangan 655 ribu ton CO2e dengan langkah mitigasi menggunakan bahan material ramah lingkungan dan peningkatan teknologi. Upaya mitigasinya meliputi penggunaan semen campuran, revitalisasi pabrik amonia, penerapan teknologi efisiensi energi dan pemanfaatan limbah logam di industri, serta pengurangan penggunaan hydrofluorocarbon (HFC/gas pendingin) melalui alternatif yang lebih rendah carbon. Namun, tantangannya adalah ketergantungan industri seperti semen dan baja pada penggunaan energi fosil, dan lemahnya pengendalian terhadap penggunaan pendingin ruangan yang terus meningkat dan berdampak pada peningkatan emisi.
Di sektor pertanian, ditargetkan penurunan emisi 250 ribu ton CO2e melalui pendekatan penggunaan varietas beremisi rendah, dan pengurangan penggunaan pupuk nitrogen melalui alternatif pupuk kandang untuk produksi biogas. Namun, yang menjadi tantangan adalah masih rendahnya adaptasi teknologi rendah emisi di kalangan petani seperti teknologi pengelolaan air di sawah, dan tingginya emisi metana dari peternakan yang masih sulit dikendalikan.
Di sektor FOLU, pada tahun 2020 ditargetkan bisa menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dilepaskan, yakni sebesar 114 juta ton CO2e. Pada tahun 2035, penyerapannya diperkirakan bertambah hingga 88 juta ton CO2e. Dalam skenario Second NDC, sektor FOLU merupakan penyumbang serapan emisi terbesar, namun juga berpotensi menghasilkan emisi yang besar apabila terjadi bencana seperti kebakaran lahan gambut. Maka dari itu, mitigasinya adalah dengan merestorasi 2 juta hektare lahan gambut, pengendalian deforestasi menjadi di bawah 0,3 juta hektare per tahun, dan rehabilitasi 8,3 juta hektare lahan yang mengalami degradasi. Namun, target ini menghadapi tantangan besar karena deforestasi yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan secara terencana dan legal dalam konsesi kehutanan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), konsesi hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, skema pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, dan perizinan perhutanan sosial.
Perlunya Langkah Konkret Lintas Sektor
Keberhasilan penerapan Second NDC Indonesia akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata lintas sektor. Tantangan seperti ketergantungan pada energi fosil, lemahnya kapasitas pengelolaan limbah, hingga deforestasi yang merajalela, membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan konsisten. Ke depan, transparansi dalam pelaksanaan, peningkatan kapasitas pendanaan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi kunci untuk memastikan target penurunan emisi bisa diaplikasikan dalam langkah konkret menuju pembangunan rendah karbon yang menjamin kelestarian dan keselamatan alam dan manusia.
Editor: Abul Muamar
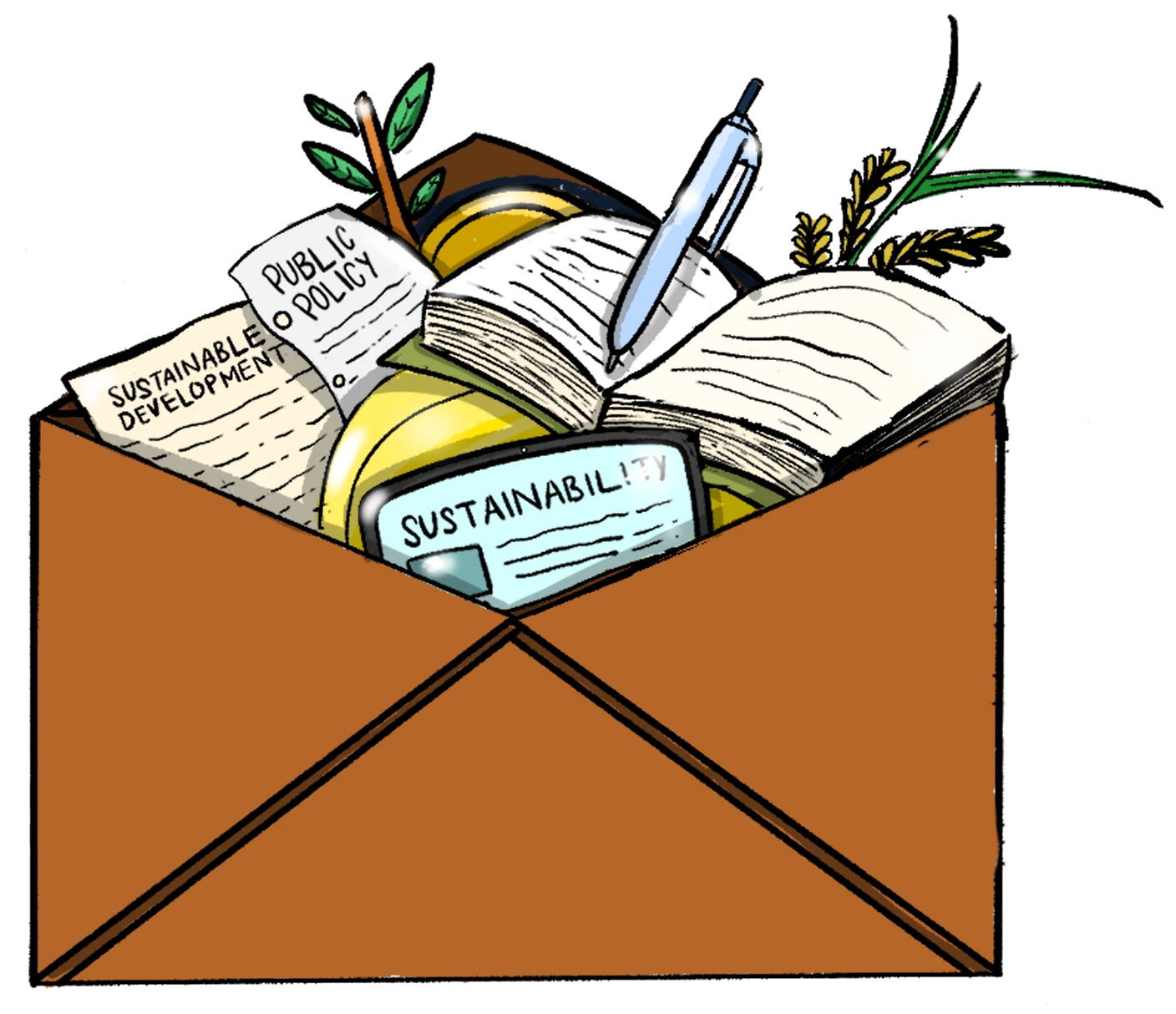
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Inflasi Harga Pangan: Hampir Separuh Warga Indonesia Tak Mampu Menjangkau Pola Makan Sehat
Inflasi Harga Pangan: Hampir Separuh Warga Indonesia Tak Mampu Menjangkau Pola Makan Sehat  Integrasi Praktik Adat dalam Penanganan Gelombang Panas di Australia
Integrasi Praktik Adat dalam Penanganan Gelombang Panas di Australia  Menetapkan Standar Nutrisi Berbasis Bukti untuk Atasi Keracunan MBG yang Berulang
Menetapkan Standar Nutrisi Berbasis Bukti untuk Atasi Keracunan MBG yang Berulang  Menilik Isu Kekurangan Bidan di Tingkat Global
Menilik Isu Kekurangan Bidan di Tingkat Global  Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya  Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air
Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air