Obat Manjur bagi Kegelisahan Para CEO
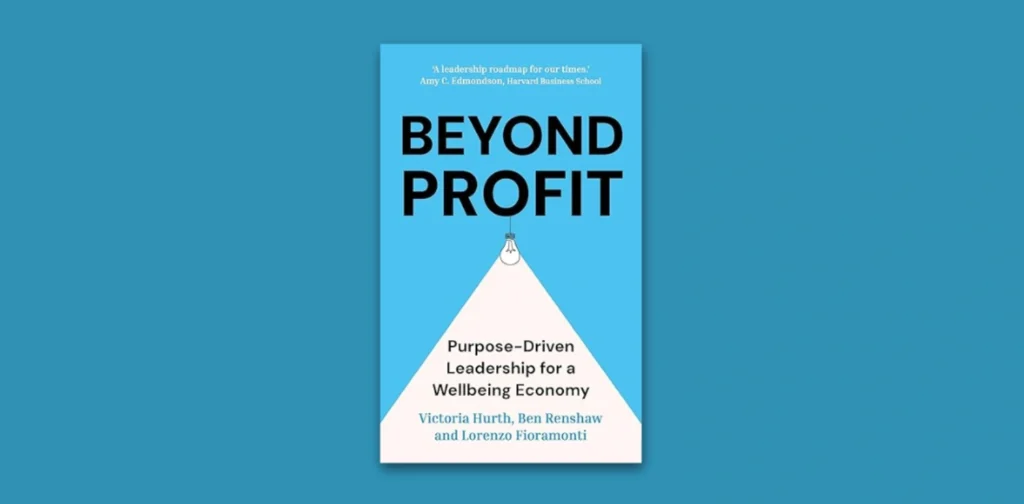
Cover buku “Beyond Profit: Purpose-Driven Leadership for a Wellbeing Economy” karya Victoria Hurth, Ben Renshaw, dan Lorenzo Fioramonti. | Penerbit: John Murray Business (2025)
“Each of us is put here in this time and in this place
to personally decide the future of humankind.
Do you think you were put here for something less?”
– Chief Arvol Looking Horse –
Suatu pagi di London, seorang CEO yang tidak ingin disebutkan namanya duduk di kantornya yang menghadap Thames, menatap spreadsheet yang penuh warna hijau—semua indikator menunjukkan pertumbuhan. Saham naik 12% setahun. Dividen dibagikan tepat waktu. Analis di Bloomberg menulis catatan positif. Namun ketika ia pulang malam itu, putrinya yang berusia sebelas tahun bertanya dengan nada yang agaknya terlalu serius untuk anak seusianya: “Papa, apa perusahaanmu membantu menyelamatkan Bumi atau malah merusaknya?”
Pertanyaan itu, diceritakan kembali dalam sebuah wawancara untuk penelitian buku “Beyond Profit: Purpose-Driven Leadership for a Wellbeing Economy”, menghantui sang CEO selama berbulan-bulan. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki jawaban yang jujur. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa sistem yang ia layani tidak dirancang untuk mengajukan, apalagi menjawab, pertanyaan semacam itu.
Kitab Beyond Profit ini—hasil kolaborasi antara Dr. Victoria Hurth, ahli tata kelola yang memimpin pengembangan ISO 37000; Ben Renshaw, coach kepemimpinan yang kliennya mencakup Unilever dan Heathrow; dan Prof. Lorenzo Fioramonti, mantan Menteri Pendidikan Italia dan kritikus ekonomi berbasis PDB—adalah upaya untuk menjawab pertanyaan anak sebelas tahun itu dengan serius. Buku ini, yang diterbitkan pada 20 November 2025, bukan sekadar manual self-help untuk eksekutif yang merasa bersalah, juga bukan manifesto anti-kapitalis yang naif. Ia adalah sesuatu yang lebih langka sekaligus lebih ‘berbahaya’: diagnosis sistemik yang disampaikan dengan kejelasan luar biasa, disertai resep yang menuntut rekayasa ulang tujuan fundamental organisasi modern. Dan karena itulah, dalam pendirian saya, buku ini menjadi istimewa.
Logika yang Telah Runtuh
Para penulis menyebut sistem yang kini mendominasi dunia bisnis—di mana kepentingan finansial jangka pendek dianggap bakal secara ajaib menghasilkan kesejahteraan kolektif—sebagai ‘Logika 1’. Ia tertanam begitu dalam di dalam benak dan hati kita semua, sehingga mempertanyakannya terasa seperti mempertanyakan gravitasi. Bedanya, gravitasi tidak membuat Bumi ini semakin panas, sementara Logika 1 menyebabkannya.
Angka-angka yang ditampilkan dalam bagian awal buku ini sederhana dan brutal. PDB global telah melonjak dari USD4,5 triliun menjadi lebih dari USD100 triliun dalam beberapa dekade terakhir. Namun kesejahteraan kolektif—yang sebenarnya diinginkan manusia: kesehatan mental, kohesi sosial, udara yang bisa dihirup anak cucu—menurun. Bukan sekadar melambat, melainkan menurun. Lebih dari tujuh puluh persen negara OECD kini mengukur kesejahteraan secara langsung, dan hasilnya mengkhawatirkan. Di luar titik tertentu, pertumbuhan ekonomi tidak lagi berkorelasi dengan kehidupan yang lebih baik; ia malahan berkorelasi dengan kecemasan yang lebih tinggi, komunitas yang lebih terfragmentasi, dan sistem ekologi yang semakin rapuh.
Fioramonti, yang menghabiskan kariernya mempelajari apa yang ia sebut sebagai “tyranny of GDP”, menulis bagian dalam buku ini jelas dengan kemarahan walau coba ia kendalikan. Ia menggambarkan ekonomi modern sebagai mesin yang secara metodis mengekstraksi nilai dari alam dan masyarakat untuk dikonsentrasikan pada segelintir pemegang saham, sambil secara simultan menghancurkan fondasi yang memungkinkan mesin itu beroperasi. Ini bukan metafora, kata Fioramonti, melainkan deskripsi literal dari cara kerja banyak perusahaan besar saat ini.
Perangkat Keras dan Lunak untuk Transformasi
Apa yang membuat buku ini berbeda dari banyak buku dengan judul mirip—yang menjanjikan Conscious Capitalism—yang telah saya baca adalah kombinasi antara idealisme moral dan kepresisian teknis yang hampir seperti obsesif. Hurth—yang saya kenal ketika ia menghabiskan lima tahun memfasilitasi pengembangan ISO 37000, standar tata kelola yang disetujui oleh seratus enam puluh empat negara—tidak bicara dalam abstraksi. Ketika ia berbicara tentang tujuan organisasi, ia merujuk pada definisi yang telah dikodifikasi dalam PAS 808:2022, standar konsensus nasional (Inggris) pertama tentang organisasi berbasis tujuan. Definisinya: alasan untuk eksis yang merupakan kontribusi strategis optimal terhadap kesejahteraan jangka panjang bagi semua orang dan planet.
Kalimat itu—yang terasi kering, birokratis, dan presisi—sesungguhnya mengandung daya revolusi yang tinggi. Ia membalikkan asumsi fundamental: profit bukanlah tujuan perusahaan, melainkan sarana. Perusahaan tidak dibentuk dan eksis untuk menghasilkan uang; mereka ada untuk berkontribusi pada kesejahteraan, dan uang adalah salah satu sumberdaya yang memungkinkan kontribusi itu terus mewujud. Ketiga penulis menggunakan metafora oksigen: vital untuk kehidupan, tetapi tidak seorang pun akan mengatakan bahwa tujuan hidup adalah menghirup sebanyak mungkin oksigen. Sudah bertahun-tahun saya menggunakan metafora makanan untuk profit ini, tetapi agaknya oksigen sama baiknya, kalau bukan lebih baik lagi.
Namun mendefinisikan ulang tujuan tidak cukup. Inilah mengapa buku ini menghabiskan bab-bab panjang pada yang Hurth sebut sebagai hardware, perangkat keras transformasi—mekanisme tata kelola aktual yang memastikan bahwa tujuan yang mulia itu tidak menguap ketika tekanan kuartalan atau tahunan tiba. ISO 37000 menguraikan tiga fungsi tata kelola: arahan (untuk apa organisasi ada), pengawasan (apakah kita bergerak ke arah itu), dan akuntabilitas (siapa yang bertanggung jawab jika kita tidak mengarah ke sana). Tanpa hardware ini—manajemen puncak yang mandatnya diubah, sistem metrik yang mengukur dampak sosial dan ekologi sama seriusnya dengan EBITDA, mekanisme pelaporan yang sepenuhnya transparan—tujuan itu hanyalah latihan public relations.
Lalu ada software-nya, yaitu kepemimpinan. Di sinilah Renshaw masuk, dan nada bukunya bergeser dari teknis menjadi hampir-hampir spiritual. Ia menulis tentang kepemimpinan sebagai ‘praktik pelayanan yang berani’, tetapi bukan dalam pengertian heroik yang mungkin dipahami kebanyakan orang. Heroik berarti melihat kemanusiaan karyawan bukan sebagai hambatan yang harus dikendalikan melalui ketakutan dan insentif finansial, melainkan sebagai aset terpenting perusahaan yang harus dipelihara. Ia menggambarkan para pemimpin yang ia latih—eksekutif senior di perusahaan multinasional—kebanyakan mengaku bahwa mereka lebih takut pada pertemuan dewan dengan pemegang saham yang menuntut pertumbuhan kuartalan daripada pada kegagalan pengelolaan iklim yang akan dihadapi anak-anak mereka. Dan ini sangat penting untuk diubah.
Ada momen-momen dalam buku ini di mana narasi Renshaw terasa hampir terlampau intim—seorang CEO yang menangis ketika menyadari bahwa ia telah menghabiskan dua puluh tahun kariernya melayani tujuan yang tidak ia percayai; seorang direktur yang mengundurkan diri setelah dewan menolak usulannya untuk mengintegrasikan metrik kesejahteraan karyawan dalam kompensasi eksekutif. Namun momen-momen itu sangatlah penting—dan saya sendiri telah berkali-kali menjadi saksi sesenggukannya para pemimpin perusahaan yang mengalami momen pencerahan. Mereka mengingatkan bahwa transformasi sistemik bukan sekadar soal spreadsheet dan pergeseran kecil dalam struktur organisasi, melainkan tentang manusia yang harus menemukan keberanian untuk berkata ‘tidak’ pada sistem yang membuat mereka bertambah kaya namun hati mereka menjadi hampa.
Ekonomi yang Melayani Kehidupan
Konsep Wellbeing Economy yang diadvokasi Fioramonti sebagai pengganti PDB bisa jadi terdengar seperti oksimoron buat banyak orang yang bernyali untuk bertanya. Ekonomi yang tujuannya bukan pertumbuhan? Mana ada? Namun para penulis berhati-hati untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah fantasi. Selandia Baru, Skotlandia, dan Islandia—bukan negara-negara yang dikenal karena radikalisme ekonomi—telah mengadopsi apa yang disebut sebagai well budgets, di mana alokasi fiskal benar-benar dipandu oleh dampak terhadap kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan. Inisiatif Michelle Obama untuk reformasi makanan di sekolah-sekolah Amerika, meski kontroversial, adalah contoh lain dari logika yang sama: kadang-kadang—atau mungkin seringnya?—kebaikan jangka panjang memerlukan penolakan terhadap kepentingan industri jangka pendek.
Buku ini menguraikan empat prinsip Ekonomi Kesejahteraan dengan ketelitian yang mengingatkan pada manifesto politik: Purpose (ekonomi harus melayani kesejahteraan, bukan sebaliknya), Prevention (mencegah kerusakan sebelum terjadi), Pre-Distribution (merancang sistem yang adil sejak awal, bukan memperbaikinya setelah kerusakan terjadi), dan People-Powered (partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan ekonomi).
Yang membuat argumen ini kemudian sangat meyakinkan adalah data. Selama periode 2020-2022—ketika pasar bergejolak dan banyak perusahaan teknologi kehilangan hingga 80% valuasi nilai mereka—perusahaan dengan model bisnis regeneratif menunjukkan ketahanan yang mencolok. Mereka tidak kebal terhadap krisis, tetapi mereka pulih lebih cepat dan mempertahankan kepercayaan investor dengan lebih baik. Alasannya, menurut para penulis, adalah modal sosial: ketika pemangku kepentingan—terutama karyawan, pelanggan, masyarakat—percaya bahwa organisasi peduli pada lebih dari sekadar profit, mereka tetap setia bahkan ketika angka kuartalan jelek. Ini bukan altruisme; ini adalah strategi untuk survive bahkan thrive. Mereka membuktikan bahwa berbuat baik tidaklah bertentangan dengan berbisnis dengan baik—bila dilihat dalam jangka panjang, keduanya adalah hal yang sama.
Kesenjangan yang Menganga
Namun saya jelas merasakan ada jurang yang menganga antara visi yang diuraikan dalam Beyond Profit dengan realitas yang dihadapi kebanyakan pemimpin sekarang. Para penulis mengakui ini—mereka tidak naif—tetapi mungkin belum cukup serius menjawabnya. Bagaimana, tepatnya, sebuah perusahaan publik yang tunduk pada analisis kuartalan dan investor aktivis yang bisa menjual saham dalam hitungan milidetik, mengadopsi horizon keputusan yang bersifat antar-generasi? Bagaimana dewan direksi yang anggotanya dipilih berdasarkan komitmen mereka pada shareholder value, tetiba mengubah mandat mereka menjadi melayani kesejahteraan semua orang dan Bumi?
Para penulis berargumen bahwa ini memerlukan perubahan aturan main dalam ekonomi makro—reformasi kebijakan, insentif fiskal, infrastruktur legal baru yang ditegakkan oleh negara. Mereka benar, tentu saja. Tetapi aturan main itu tidak akan berubah tanpa koalisi politik yang kuat, dan membangun koalisi semacam itu memerlukan menantang kepentingan oligarki yang sangat kuat dan sangat berakar di banyak negara. Buku ini, saya rasa, belum cukup menggali pertarungan politik yang sebenarnya bakal diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut pada mayoritas perusahaan. Tentu sudah ada perusahaan-perusahaan macam Patagonia yang bisa mewujudkannya tanpa perlu perubahan politik sama sekali. Tetapi, tidak semua CEO itu Yvon Chouinard.
Ada juga ketegangan yang tidak sepenuhnya terselesaikan antara idealisme moral dan pragmatisme bisnis. Para penulis menunjukkan data bahwa perusahaan berbasis tujuan mengungguli pesaing dalam jangka panjang. Tetapi ‘jangka panjang’ sendiri adalah konsep yang licin. Bagi seorang CEO yang kontraknya tiga tahun dan kompensasinya terikat pada kinerja saham, jangka panjang adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli—secara harfiah.
Lebih jauh lagi, ada pertanyaan tentang siapa, tepatnya, yang dimaksud dengan ‘semua orang dan planet’. Ketika kepentingan di antara ‘semua orang’ itu bertentangan—dan mereka akan bertentangan—siapa yang akan memutuskan trade-off yang perlu diambil? Para penulis menawarkan kerangka kerja (stakeholder engagement, transparansi, akuntabilitas) tetapi tidak cukup menggali bagaimana kerangka kerja itu akan bekerja dalam situasi konflik kepentingan yang nyata. Saya membayangkan ketika perusahaan farmasi harus memilih antara memaksimalkan akses ke obat penyelamat nyawa di negara berkembang versus mempertahankan margin profit yang memungkinkan investasi R&D untuk penyakit masa depan, bagaimana ‘kesejahteraan semua orang’ itu diterjemahkan menjadi keputusan yang konkret? Selama saya mendampingi manajemen puncak perusahaan, deliberasi seperti ini sangatlah kompleks, dan saya berharap ada wawasan mendalam yang bisa memandu pemuncak perusahaan dalam urusan ini.
Pertanyaan Anak Sebelas Tahun
Namun, melancarkan kritik atas buku ini karena tidak memberikan jawaban yang lengkap mungkin malah bisa melewatkan poinnya. Beyond Profit bukan manual teknis untuk transisi tanpa rasa sakit menuju Kapitalisme yang baik hati. Ia adalah, pada intinya, sebuah provokasi—undangan untuk mengajukan pertanyaan yang sebagian besar dari kita terlalu takut untuk diajukan dengan serius.
Beberapa bulan lalu saya bercakap-cakap dengan seorang SVP sebuah bank. Yang kami obrolkan adalah tentang tata kelola, kehandalan data ESG, juga tentang ketahanan perusahaan berbasis tujuan. Dan ketika saya bercerita soal metafora makanan terhadap manusia sama dengan profit terhadap perusahaan, ia kurang lebih menyatakan bahwa: “Uang itu cuma simbol, dan simbol jelas tidak pernah bisa menjadi tujuan akhir. Tentu saya selalu tahu itu benar. Tetapi seluruh karier saya diajarkan untuk memperlakukan simbol itu seolah-olah ia adalah tujuan. Dan sekarang saya tidak tahu bagaimana caranya berhenti.”
Itulah, mungkin, kontribusi terpenting dari kitab ini. Ia mengerti bahasa dan menawarkan kerangka kerja untuk kegelisahan yang sudah dirasakan banyak pemimpin bisnis. Ia mengatakan bahwa perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem ini bukan hanya kelemahan moral individual—itu adalah respons rasional terhadap sistem yang memang rusak. Dan ia menawarkan sesuatu yang lebih langka: bukti bahwa alternatif bukan hanya mungkin tetapi, dalam beberapa kasus, bahkan sudah ada.
CEO yang putrinya bertanya tentang peran perusahaannya terhadap Bumi saya bayangkan memulai proses perlahan dan kerap menyakitkan untuk mengubah mandat dewan, mengadopsi metrik baru, dan membangun koalisi internal yang percaya bahwa perubahan mungkin. Beberapa tahun berselang, perusahaannya belum menjadi model sempurna dari Ekonomi Kesejahteraan. Sahamnya sempat turun ketika ia menolak akuisisi yang akan menguntungkan tetapi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang telah ia artikulasikan. Beberapa investor mungkin keluar. Tetapi perusahaan masih ada, masih menguntungkan, dan—yang mungkin paling penting—ketika putrinya sekarang bertanya tentang apa yang ia lakukan, ia memiliki jawaban yang bisa ia katakan dengan jujur.
Mungkin itulah, pada akhirnya, ukuran kesuksesan pemimpin perusahaan yang paling penting: bukan sekadar pertumbuhan kuartalan atau valuasi pasar, tetapi kemampuan untuk melihat mata anak-anak mereka dan bisa menjelaskan, tanpa rasa malu, bahwa mereka telah melakukan yang optimal bagi masa depan dengan waktu yang tersedia bagi mereka selama di dunia ini. Persis seperti kata-kata bijak Chief Arvol Looking Horse yang saya kutip di bagian awal tulisan ini.
Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.


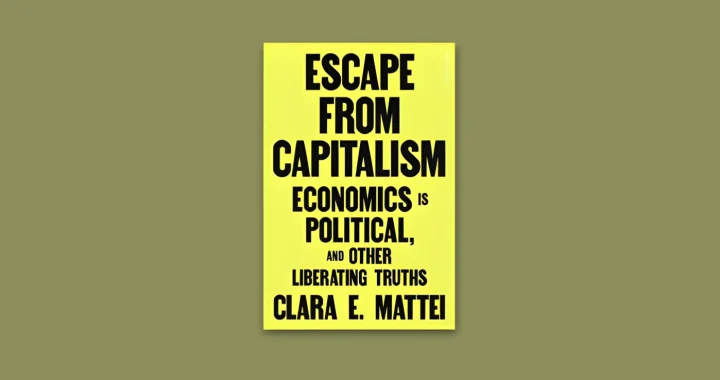 Kapitalisme Bukanlah Takdir: Membaca Clara Mattei di Tengah Kelelahan Kolektif
Kapitalisme Bukanlah Takdir: Membaca Clara Mattei di Tengah Kelelahan Kolektif  Mengintegrasikan Pertanian dalam Permukiman Perkotaan dengan Konsep Agrihood
Mengintegrasikan Pertanian dalam Permukiman Perkotaan dengan Konsep Agrihood  Meningkatkan Pelindungan Anak di Ruang Digital dengan Pendekatan Tanggung Jawab Bersama
Meningkatkan Pelindungan Anak di Ruang Digital dengan Pendekatan Tanggung Jawab Bersama  Merangkul Nilai Bisnis Keberlanjutan
Merangkul Nilai Bisnis Keberlanjutan  Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender
Perempuan dalam Pengelolaan Sampah: Mewujudkan Sirkularitas yang Responsif Gender  Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati
Potensi dan Tantangan Biodiversity Credits dalam Penguatan Pembiayaan Keanekaragaman Hayati