Robohnya NZBA: Kritik, Analisis, dan Seruan untuk Perbankan Indonesia

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Ketika dunia semakin panas dan bencana iklim tak lagi bisa kita sebut “kejadian luar biasa”, sektor keuangan yang konon pandai berhitung risiko seharusnya berdiri di garis depan penyelamatan. Bank—dengan kekuatan modal, akses terhadap seluruh sektor ekonomi, dan kemampuan menentukan arah arus investasi dan pembiayaan—memegang peran yang jauh melampaui fungsi intermediasi biasa. Dalam dunia yang sedang terbakar, keputusan kredit sama pentingnya dengan–kalau bukan malah lebih penting daripada–keputusan politik. Karena itu, pembubaran Net-Zero Banking Alliance (NZBA) pada awal Oktober 2025 bukanlah sekadar berita organisasi yang biasa; melainkan tanda bahwa sistem keuangan global belum cukup kuat untuk menanggung tanggung jawab moral dan ekonomi terbesar abad ini: menyelamatkan masa depan dari krisis iklim.
Kesadaran akan hal itu membuat saya sedih dan kecewa.
Lemahnya Komitmen Moral
Aliansi yang dibentuk di bawah naungan UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) pada April 2021 itu semula memantik harapan besar. Dengan lebih dari 140 bank anggota dari seluruh dunia yang mewakili sekitar 40% total aset perbankan global, NZBA diciptakan untuk menyatukan upaya sektor keuangan dalam menyalurkan modal menuju ekonomi beremisi nol bersih pada 2050. Ia lahir dari kesadaran bahwa tanpa reformasi fundamental dalam pembiayaan, dunia tidak akan mampu menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°C sebagaimana disepakati dalam Persetujuan Paris.
Namun pada 3 Oktober 2025, aliansi itu resmi dibubarkan setelah gelombang kepergian anggota utama—terutama bank-bank besar dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Kanada—dan menyebabkan vakumnya legitimasi dan efektivitas organisasi. Voting internal memutuskan penghentian operasi NZBA setelah tekanan politik dan gugatan hukum yang dialami sejumlah anggota pentingnya menghasilkan ketegangan internal yang tak lagi tertahankan.
Keputusan tersebut segera menimbulkan gelombang kritik dari berbagai pihak, terutama terhadap bank-bank yang memilih mundur. Banyak pengamat yang ulasannya saya baca menilai langkah itu sebagai bentuk penyerahan diri terhadap kepentingan jangka pendek dan bukti lemahnya komitmen moral terhadap krisis global yang nyata. Dengan meninggalkan inisiatif yang bertujuan menyelaraskan pembiayaan dengan target iklim, mereka menunjukkan bahwa tekanan pasar jangka pendek, risiko hukum, dan kalkulasi politik domestik masih lebih kuat dibanding tanggung jawab ekologis yang bersifat eksistensial. Dalih yang diajukan, yaitu bahwa NZBA terlalu membatasi fleksibilitas bisnis anggotanya benar-benar mempertegas betapa mudahnya prinsip keberlanjutan dikorbankan begitu ia menantang kenyamanan ekonomi konvensional. Lebih tepatnya, menurut saya, keberlanjutan ternyata bukanlah prinsip bagi mereka yang mundur.
Kritik lain diarahkan pada keputusan keluar yang pada dasarnya menghindari akuntabilitas kolektif. NZBA menyediakan kerangka yang memungkinkan peer review dan evaluasi publik atas kemajuan setiap bank menuju target emisi nol bersih. Dengan keluar dari forum itu, para anggota besar justru memilih ruang yang lebih tertutup, di mana pengaturan dan klaim keberlanjutan bersifat sepihak dan sulit diverifikasi. Akibatnya, publik kehilangan kemampuan untuk menilai apakah janji net zero benar-benar ditindaklanjuti dengan perubahan nyata, atau sekadar menjadi topeng hijau yang menutupi wajah bopeng praktik status quo pembiayaan mereka yang masih saja tinggi karbon. Risiko greenwashing pun meningkat: semakin banyak institusi menyatakan klaim komitmen iklim tanpa standar yang ditegakkan bersama, semakin kabur pula makna transisi itu sendiri.
Tekanan Politik
Namun, saya juga memahami bahwa runtuhnya NZBA tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali arus politik pro-bahan bakar fosil di beberapa negara, disertai retorika anti-ESG yang makin keras. Di Amerika Serikat, sejumlah legislator bahkan menuduh inisiatif seperti NZBA melanggar hukum antitrust karena ‘mengatur’ strategi investasi kolektif yang dianggap membatasi kebebasan pasar. Tekanan politik semacam itu membuat keanggotaan dalam aliansi global menjadi beban reputasi di beberapa yurisdiksi. Di sisi lain, polarisasi geopolitik memperlemah solidaritas internasional. Kerja sama lintas-negara dalam agenda iklim tergusur, atau setidaknya terpinggirkan, lalu digantikan posisi sentralnya oleh persaingan ekonomi dan ketegangan perdagangan energi.
Dari sisi kelembagaan, NZBA juga menghadapi paradoks yang sulit diatasi. Sebagai inisiatif sukarela, ia bergantung pada keinginan baik para anggotanya untuk bertindak sejalan. Namun, sebagaimana yang banyak dituliskan para pakar, pendekatan sukarela memiliki batas. Ia sangat mudah goyah ketika kepentingan bisnis jangka pendek bertabrakan dengan tuntutan perubahan struktural. Sebagian bank menganggap kerangka kerja NZBA terlalu ketat, sementara sebagian lainnya menilai ia terlalu longgar dan tidak ambisius.
Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan regulasi formal dan insentif ekonomi yang kuat, aliansi berbasis komitmen moral semata sulit bertahan di tengah realitas ekonomi yang masih sangat tergantung pada energi fosil, walau pembiayaan terkait energi terbarukan sudah jauh melampauinya. Lebih parah lagi, pada tahun 2024–2025 NZBA sempat didera kontroversi akibat usulan pelonggaran standar penyelarasan terhadap jalur 1,5°C. Langkah itu menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil yang menuduh aliansi mulai berkompromi terhadap ambisinya sendiri. Pada titik itu, reputasi NZBA mulai goyah, dan kepergian sejumlah anggota besar menjadi pukulan terakhir.
Momentum Perbaikan Tata Kelola
Meski begitu, bubarnya NZBA tidak boleh dimaknai sebagai kegagalan cita-cita menuju ekonomi hijau, melainkan sebagai bukti tambahan bahwa model sukarela tak pernah cukup untuk menghadapi tantangan sistemik. Risiko iklim—baik fisik, transisi, maupun reputasi—tetap nyata dan semakin meningkat. Bank yang terus menyalurkan pembiayaan ke sektor intensif karbon sedang menumpuk risiko jangka panjang bagi dirinya sendiri dan sistem keuangan secara keseluruhan. Karena itu, peristiwa ini harus dilihat sebagai panggilan untuk memperkuat mekanisme internal maupun eksternal perbankan, bukan sebagai dalih untuk berhenti memperjuangkan keuangan berkelanjutan.
Bagi sektor perbankan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, inilah saatnya mempertegas arah. Pembubaran NZBA bukan peluang untuk beristirahat, melainkan momentum untuk membangun tata kelola keberlanjutan yang lebih kuat dan kontekstual. Komitmen menuju emisi nol bersih harus dipertahankan bahkan diperkuat melalui target antara yang terukur, transparansi metodologis, dan audit independen. Laporan pembiayaan berbasis sektor serta peta jalan transisi klien perlu dipublikasikan secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga. Hanya dengan transparansi, keuangan berkelanjutan bisa menjaga legitimasinya.
Dalam konteks nasional, peran regulator menjadi kunci. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempercepat integrasi risiko iklim ke dalam kerangka pengawasan, stress test, dan kebijakan permodalan. Pemerintah juga harus menciptakan kerangka kebijakan yang memberikan insentif pada pembiayaan hijau dan disinsentif bagi investasi karbon tinggi. Dengan demikian, seluruh pelaku perbankan memiliki kepastian dan insentif untuk bergerak bersama tanpa rasa khawatir akan kehilangan daya saing.
Selain memperkuat sisi tata kelola, bank juga harus aktif membantu kliennya menjalani transisi. Pembiayaan transisi (transition finance) yang kredibel dapat menjadi instrumen penting dalam membantu sektor energi, pertambangan, transportasi laut, dan industri berat di Indonesia beralih ke model bisnis yang lebih rendah karbon. Bank perlu memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan memiliki peta jalan yang jelas, indikator kemajuan yang terukur, dan dampak sosial yang adil bagi pekerja serta komunitas sekitar.
Pendekatan just transition ini akan memperkuat legitimasi sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi selama proses dekarbonisasi berlangsung. Dalam situasi di mana aliansi global seperti NZBA telah bubar, kerjasama domestik dan regional agaknya menjadi lebih dan semakin penting. Kolaborasi antar-bank di tingkat ASEAN, bersama regulator dan masyarakat sipil, dapat membangun standar pembiayaan hijau dan sosial yang lebih sesuai konteks lokal namun tetap selaras dengan tujuan global. Upaya ini akan menghindarkan kawasan ini dari ketergantungan terhadap arah politik negara-negara besar yang kini cenderung tidak stabil dalam komitmen iklimnya.
Pentingnya Keberanian Moral
Yang paling penting, menurut saya, sektor perbankan harus memiliki keberanian moral sekaligus strategis untuk menghentikan pendanaan projek baru berbasis bahan bakar fosil yang tidak memiliki rencana transisi yang kredibel. Langkah semacam ini bukan sekadar bermakna simbolis, tetapi merupakan perwujudan strategi mitigasi risiko jangka panjang. Dalam dunia yang sedang bergerak menuju dekarbonisasi, setiap investasi pada proyek tinggi karbon adalah taruhan berbahaya terhadap masa depan ekonomi.
Akhirnya, kita semua perlu mafhum bahwa pembubaran NZBA adalah kegagalan pengelolaan organisasi belaka, bukan kegagalan tujuan. Visi untuk menahan pemanasan global di bawah 2 bahkan hingga mendekati 1,5°C tetap sahih dan harus terus diperjuangkan. Bank-bank di seluruh dunia kini dihadapkan pada pilihan moral dan strategis, yaitu menjadikan peristiwa ini sebagai dalih untuk mundur, atau menggunakannya sebagai katalis untuk memperkuat tata kelola, kolaborasi, dan inovasi yang lebih berani. Sains sudah jelas, dampak sudah terasa, dan waktu sudah hampir habis. Dunia perbankan, sebagai jantung dan urat nadi pembiayaan ekonomi global, harus memutuskan perannya—apakah akan menjadi motor penggerak transisi, atau sekadar saksi bisu dari kegagalan kolektif manusia menghadapi krisis iklim.
Pelajaran terbesar dari bubarnya NZBA, bagi saya, adalah bahwa keberlanjutan bukan soal niat baik, melainkan soal prinsip, konsistensi, keberanian, struktur, bahkan budaya. Komitmen iklim yang bermakna menuntut akuntabilitas publik, dukungan kebijakan, dan keberanian untuk menolak kompromi terhadap masa depan. Bagi perbankan Indonesia, inilah momen untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab global bisa diwujudkan dalam konteks nasional. Jika sektor ini berani mengambil pelajaran dari kegagalan global, dengan memperkuat transparansi dan memimpin pembiayaan transisi yang berkeadilan, maka ia bukan hanya menyelamatkan reputasinya, tetapi juga ikut memastikan masa depan Bumi yang layak huni bagi semua.
Editor: Abul Muamar
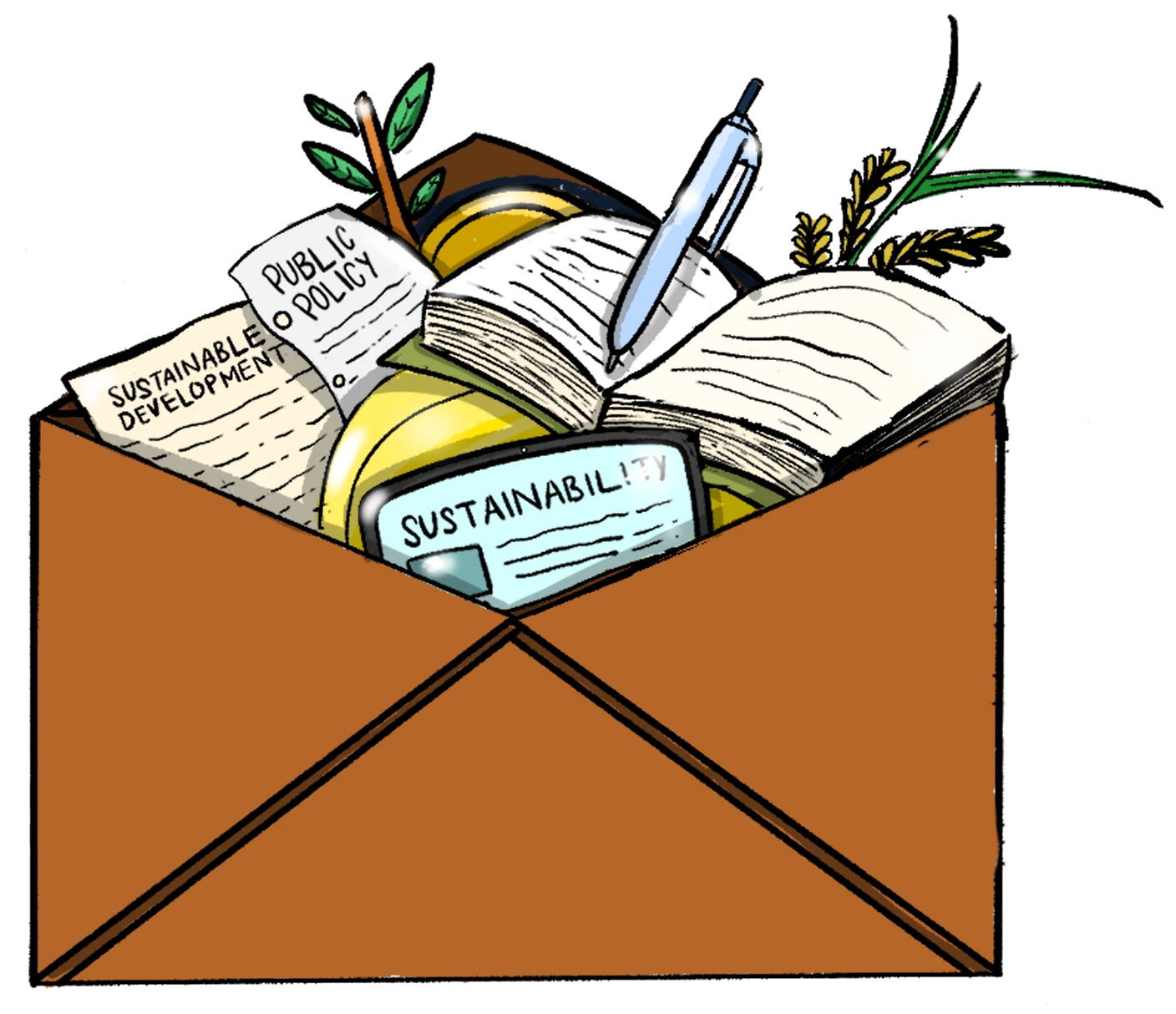
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.


 Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB  Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global  Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan  Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia  Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah  Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja