Mungkinkah Kita Melepaskan Diri dari Jeratan Sampah Plastik?
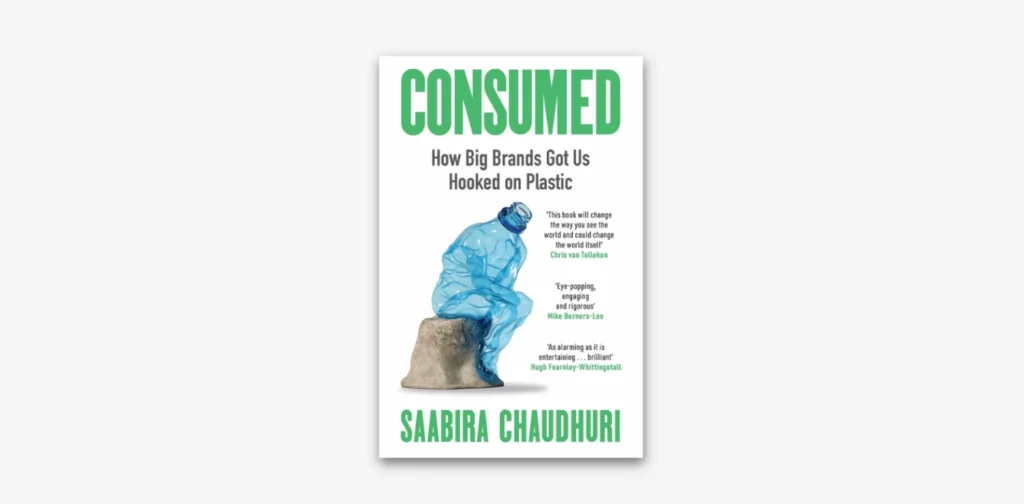
Cover buku “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic” karya Saabira Chaudhuri. | Penerbit: Bonnier Books UK (2025).
Pada suatu pagi di bulan Maret 1987, sebuah kapal tongkang berwarna biru-putih yang tidak menarik perhatian, Mobro 4000, didorong keluar dari pelabuhan Long Island City. Muatannya: lebih dari tiga ribu ton sampah dari New York. Ini adalah muatan yang biasa, sebuah ritual pembuangan yang banal, yang seharusnya berakhir dengan pembakaran di North Carolina. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah pembuangan, melainkan sebuah pelayaran yang seakan tak akan berakhir.
Gubernur North Carolina, atas desakan senator yang sangat sadar atas masalah ini, menolak Mobro. Lantaran ditolak, kapal itu berlayar ke selatan, bak menjadi warga pariah yang mengambang. Louisiana kemudian menolaknya. Meksiko, dengan sopan tapi tegas, mengerahkan angkatan lautnya untuk mengawalnya pergi. Belize, yang mendengar kabar kedatangannya, memberlakukan larangan darurat. Selama lima bulan, Mobro menjadi lelucon nasional dan internasional, dan tampil sebagai subjek berbagai kartun editorial. Yang paling penting, Mobro menjadi sebuah metafora untuk masalah yang terus mengambang dan tidak dapat dibuang. Ia adalah perwujudan fisik dari keengganan kolektif kita untuk menatap ke dalam tempat sampah kita sendiri.
Mobro, Coca-Cola, dan Throwaway Living
Perjalanan Mobro yang malang, bagi kebanyakan orang hanyalah pertanyaan logistik: Ke mana seharusnya sampah ini pergi? Dan saya sangat bahagia lantaran buku baru karya Saabira Chaudhuri yang diteliti dengan cermat dan ditulis dengan prosa yang tajam, tidak berhenti di situ. Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic, jelas tidak terlalu tertarik pada pertanyaan ‘ke mana’ itu. Sebaliknya, buku ini membongkar pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan meresahkan: Dari mana sampah berasal, dan mengapa kita memiliki begitu banyak sampah untuk dibuang? Mobro yang ditulis di bagian awal buku adalah cerita yang kuat, tetapi ia hanyalah pengantar bagi cerita yang jauh lebih dahsyat.
Cerita yang lebih dahsyat itu, bagi Chaudhuri, adalah soal kegagalan berulang Coca-Cola dalam memenuhi target keberlanjutan yang dibuatnya sendiri. Sejak 1990, perusahaan tersebut telah menetapkan setidaknya delapan target keberlanjutan dan gagal memenuhi hampir semuanya. Ia mencatat dengan telaten bagaimana sejak awal tahun 1990-an, Coca-Cola menjanjikan botol dengan 25 persen konten daur ulang, hanya untuk kemudian diam-diam membatalkan target tersebut ketika harga minyak turun dan resin daur ulang menjadi lebih mahal. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan operasional; ini adalah pola. Mengapa perusahaan-perusahaan paling canggih di dunia, yang memiliki sumberdaya hampir tak terbatas untuk logistik dan pemasaran, terus ‘gagal’ pada hal yang sama selama tiga dekade? Jawabannya, menurut analisis Chaudhuri, adalah karena plastik bukan sekadar bahan kemasan; ia adalah infrastruktur dasar dari Kapitalisme modern yang tak terkendali.
Sebelum Perang Dunia II, dunia kita sebagian besarnya adalah dunia yang mengenal konsep pengisian ulang. Susu datang dalam botol kaca yang dikembalikan ke pengantar; popok adalah kain yang dicuci dan dipakai kembali. Namun setelahnya, industri petrokimia menemukan diri mereka dengan kapasitas produksi polimer yang melimpah dan tidak ada pasar yang cukup besar untuk menyerapnya.
Di sinilah letak ‘dosa asal’ industri modern: penciptaan kebutuhan akan sesuatu yang sekali pakai. Chaudhuri menggali arsip-arsip lama untuk menunjukkan bagaimana pada 1956 dan 1963, Lloyd Stouffer, editor majalah Modern Plastics, dengan tegas memberitahu para eksekutif bahwa “masa depan plastik ada di tempat sampah.” Ia berpendapat bahwa industri harus berhenti memikirkan penggunaan kembali dan fokus pada pasar berulang yang diukur dalam miliaran unit sekali pakai. Munculnya narasi Throwaway Living—yang dirayakan dalam majalah Life 1955 dengan gambar keluarga melemparkan piring dan gelas plastik dengan gembira—bukanlah evolusi alami dari keinginan manusia, melainkan sebuah kampanye manipulasi psikologis yang masif untuk mengubah warga negara menjadi konsumen yang patuh.
Mitos Daur Ulang
Bagi saya, salah satu bagian paling provokatif dari buku ini adalah ketika Chaudhuri membongkar mitos daur ulang yang telah menjadi tempat persembunyian favorit bagi departemen PR korporasi. Pada 1988, ketika ratusan undang-undang lokal diusulkan untuk membatasi plastik menyusul skandal Mobro, tujuh raksasa kimia—termasuk Amoco, Dow, DuPont, dan Mobil—masing-masing menyumbang satu juta dolar untuk membentuk Council for Solid Waste Solutions. Mereka dijuluki ‘Million Dollar Boys’ Club’, dan dipimpin oleh lobbyist Donald Shea, kelompok ini memahami bahwa jika industri ingin menghindari larangan, mereka perlu secara publik terlihat merangkul daur ulang, meskipun hanya satu persen plastik yang benar-benar didaur ulang pada saat itu. Dalam kata-kata salah satu eksekutif mereka, Ronald Liesemer, industri perlu mengejar daur ulang hanya untuk “membuktikan kepada publik bahwa itu bisa dilakukan” lalu secara efektif mengubah daur ulang menjadi kampanye pemasaran raksasa.
Simbol tiga panah melingkar yang kita lihat pada hampir setiap kemasan plastik seringkali merupakan bentuk penyesatan visual yang paling sukses dalam sejarah modern. Dikembangkan pada 1988 oleh Society of the Plastics Industry, kode identifikasi resin ini menggunakan simbol daur ulang yang dirancang oleh mahasiswa Gary Anderson untuk kompetisi industri kertas tahun 1970. Meskipun eksekutif industri bersikeras kode tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan daur ulang kepada konsumen, mereka memilih simbol daur ulang yang paling dikenal untuk mewakilinya. Hasilnya? Dalam polling 2019, 92 persen orang Amerika mengaku tidak memahami kode tersebut, namun hampir 70 persen berasumsi bahwa apapun dengan gambar panah tersebut bisa didaur ulang. Faktanya, Chaudhuri mengungkap bahwa tingkat daur ulang plastik global tetap mandek di angka yang sangat menyedihkan—hanya sembilan persen—sementara volume plastik perawan yang diproduksi justru terus melonjak. Daur ulang, dalam banyak hal, kata Chaudhuri, telah menjadi “daur-kebohongan.”
Pertempuran serupa terjadi di kamar bayi. Pada 1988, Procter & Gamble menghadapi temuan bahwa 18 miliar popok sekali pakai dibuang setiap tahun, menjadikannya produk konsumen terbesar di tempat pembuangan sampah setelah koran. Respons P&G bisa dianggap sebagai masterclass dalam pengalihan korporasi. Mereka meminta Life Cycle Assessment (LCA) dari Arthur D. Little yang mengklaim popok kain menggunakan lebih banyak energi dan air, mendanai pembentukan Solid Waste Composting Council untuk memberikan kesan bahwa kompos dari popok sudah di ambang pintu. Pada kenyataannya, polimer superabsorben dalam popok tersebut adalah forever chemicals yang akan bertahan dalam ekosistem hingga akhir zaman. Meskipun sepuluh jaksa agung negara bagian menuntut P&G atas penipuan itu, manuver PR-nya berhasil dengan gemilang. Pada tahun 1996, catat Chaudhuri, 94% orang tua Amerika mengandalkan popok sekali pakai sepenuhnya.
Untuk kita yang hidup di konteks Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, bab mengenai strategi pasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah memberikan perspektif yang sangat menyakitkan. Chaudhuri menjelaskan bagaimana pada 1990-an, ketika pasar Barat melambat, raksasa seperti Unilever dan P&G membidik pasar negara berkembang seperti India. Untuk menciptakan permintaan di daerah pedesaan yang belum melek media massa, Unilever menggunakan van bioskop keliling yang menayangkan film Bollywood diselingi dengan puluhan iklan sabun. Kunci ekspansi ini adalah saset sekali pakai—kantong plastik multilayer yang membuat merek seperti sampo Sunsilk terjangkau bagi orang-orang dengan upah harian. Unilever merekrut 200.000 para Shakti Ammas, perempuan desa miskin, untuk bertindak sebagai distributor mikro. Pada 2004, saset menyumbang 90% penjualan sampo di pedesaan India. Di panggung-panggung konferensi internasional, ini sering dipasarkan sebagai demokratisasi konsumsi. Namun, realitanya adalah sebuah bentuk kolonialisme limbah. Kemasan multilayer ini secara teknis mustahil untuk didaur ulang secara ekonomi dalam sistem yang ada saat ini, dan kini menyumbang 80% plastik yang berakhir di laut. Perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari volume penjualan saset di pasar yang padat penduduk, sementara beban sampahnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang kekurangan dana dan ekosistem sungai yang rapuh.
Peringatan yang Wajib Didengar
Melalui Consumed, Chaudhuri mengingatkan kita bahwa plastik kini telah merasuk ke dalam eksistensi biologis kita secara harfiah. Reaksi balik modern dipicu bukan oleh tongkang, tetapi oleh video 2015 tentang penyu laut dengan sedotan plastik tersangkut di hidungnya—video yang dibuat oleh ahli biologi kelautan Christine Figgener. Namun krisis telah berevolusi dari sampah yang terlihat menjadi ancaman tak terlihat dari mikroplastik dan nanoplastik, yang sekarang ditemukan di segala hal mulai dari darah manusia hingga jaringan otak.
Sebuah studi 2024 yang dikutip Chaudhuri mengaitkan keberadaan mikroplastik dalam plak arteri dengan risiko serangan jantung atau stroke 4,5 kali lebih tinggi. Lebih lanjut, para peneliti telah mengidentifikasi 16.000 bahan kimia yang digunakan dalam plastik—termasuk BPA, ftalat, dan PFAS—banyak di antaranya “mengkhawatirkan” karena toksisitas dan kemampuan mereka untuk mengganggu hormon manusia. Hanya 6 persen dari bahan kimia ini yang diatur secara global. Kita telah sampai pada titik di mana kita tidak lagi sekadar konsumen plastik; tubuh kita telah menjadi wadah bagi polimer-polimer tersebut.
Sebagai seseorang yang telah lama bergelut dalam isu keberlanjutan korporasi, saya melihat hasil pengungkapan Chaudhuri sebagai panggilan untuk melakukan dekonstruksi total terhadap cara kita menangani isu plastik, terutama di wilayah yang rentan seperti Indonesia. Kita harus berhenti mengandalkan janji-janji sukarela dari industri dan mulai menuntut perubahan struktural yang fundamental. Langkah pertama yang paling mendesak adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) secara tegas dan berdaulat. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan perusahaan hanya melakukan kegiatan sosial yang bersifat kosmetik, seperti mendanai beberapa unit bank sampah kecil yang tidak sebanding dengan jutaan ton plastik yang mereka produksi. Perusahaan harus dipaksa secara hukum untuk memikul beban finansial dan fisik dari pengelolaan sampah produk mereka.
Selanjutnya, kita membutuhkan desain ulang yang radikal terhadap sistem distribusi barang, yang berarti kita harus berani mengakhiri era saset sekali pakai. Inovasi korporasi saat ini terlalu banyak difokuskan pada upaya membuat plastik yang sedikit lebih baik, padahal yang kita butuhkan adalah penghapusan plastik itu sendiri dari mayoritas rantai pasok. Buku ini menyoroti potensi sistem penggunaan ulang yang terstandarisasi, seperti program cangkir Aarhus di Denmark, yang menggunakan sistem deposit-return digital untuk mencapai tingkat pengembalian 86%. Di Indonesia, kita memiliki tradisi belanja curah di pasar tradisional yang seharusnya bisa dimodernisasi dengan teknologi digital untuk menciptakan sistem pengisian yang higienis, terstandarisasi, dan terjangkau di setiap minimarket.
Transparansi kimiawi juga merupakan garis depan baru yang harus kita perjuangkan. Publik berhak mengetahui setiap bahan kimia tambahan yang digunakan dalam kemasan plastik mereka. Dampak kesehatan dari peluruhan bahan kimia ini ke dalam makanan dan minuman kita, terutama pada anak-anak, adalah bom waktu medis yang tidak boleh diabaikan. Kita membutuhkan regulasi yang mewajibkan pengungkapan penuh atas profil toksisitas kemasan, memaksa industri untuk beralih ke bahan-bahan yang benar-benar aman bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang.
Terakhir, dan yang paling penting, kita harus secara kolektif menolak narasi yang meletakkan tanggung jawab utama pada konsumen yang selama ini digunakan sebagai senjata oleh industri untuk melakukan gaslighting terhadap publik. Selama puluhan tahun, kita telah dididik untuk merasa bersalah jika kita tidak mendaur ulang dengan benar, sementara produsen terus membanjiri pasar dengan kemasan yang sesungguhnya tidak dirancang untuk didaur ulang. Beban moral dan logistik ini harus dikembalikan ke tempat asalnya: di ruang-ruang rapat dewan direksi perusahaan FMCG, atau bahkan lebih jauh lagi, ke perusahaan-perusahaan petrokimia dan minyak dari mana plastik berasal.
Saabira Chaudhuri telah menulis sebuah karya yang sangat krusial karena ia tidak hanya memaparkan data yang kering, tetapi berhasil mengungkap jiwa dari krisis ini: sebuah ketakutan korporasi akan kehilangan bisnis bila tidak didorong oleh pemborosan. Di Indonesia, di mana sungai-sungai kita seringkali lebih menyerupai aliran plastik daripada air, urgensi ini terasa begitu nyata dan menyesakkan. Kita tidak bisa lagi menerima retorika keberlanjutan yang manis dari perusahaan yang secara bersamaan terus memperluas kapasitas produksi plastik mereka.
Consumed adalah sebuah pengingat keras bahwa plastik adalah sebuah pilihan desain, bukan sebuah keniscayaan takdir. Jika kita mampu mendesain sebuah dunia yang begitu terjerat pada plastik hanya dalam waktu beberapa generasi, kita jelas memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk mendesain jalan keluar darinya. Pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki teknologinya, tetapi apakah kita memiliki keberanian politik untuk melepaskan diri dari jeratan sampah plastik dengan melawan hegemoni industri yang menganggap bahwa masa depan Bumi adalah harga yang pantas untuk dibayar demi kenyamanan yang sementara. Saat kita merobek saset plastik berikutnya, kita harus sadar bahwa itu bukan sekadar sampah; itu adalah bagian dari masa depan yang sedang kita kotori. Chaudhuri jelas menunjukkan bahwa sudah saatnya kita berhenti dikonsumsi oleh cara kita mengonsumsi barang, dan mulai merebut kembali integritas dunia kita.
Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.


 Kematian dan Bunuh Diri Anak sebagai Isu Struktural: Kurangnya Pemenuhan Hak Anak
Kematian dan Bunuh Diri Anak sebagai Isu Struktural: Kurangnya Pemenuhan Hak Anak  Mengatasi Kesenjangan yang Dihadapi Perempuan di Bidang STEM
Mengatasi Kesenjangan yang Dihadapi Perempuan di Bidang STEM  Finding Harmony: Pencarian Harmoni dengan Alam di Benak Sang Raja
Finding Harmony: Pencarian Harmoni dengan Alam di Benak Sang Raja  Mengatasi Eksploitasi di Balik Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara
Mengatasi Eksploitasi di Balik Program Migrasi Tenaga Kerja Sementara  Mewujudkan Kondisi Kerja yang Layak bagi Pekerja Platform
Mewujudkan Kondisi Kerja yang Layak bagi Pekerja Platform  Memetakan Kebutuhan Konservasi Hiu dan Pari secara Global
Memetakan Kebutuhan Konservasi Hiu dan Pari secara Global