Mengarusutamakan Spiritualitas Ekologis dalam Praktik Keagamaan

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Modernitas telah memberikan banyak hal, mulai dari kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, hingga perluasan jangkauan ilmu pengetahuan. Namun, di balik semua kemilau kemajuan itu, Bumi menanggung luka yang kian dalam. Gunung dan bukit-bukit hijau digunduli tanpa belas kasih, laut tercemar oleh limbah, udara sesak oleh racun-racun buatan manusia, dan tanah—tempat kehidupan berpijak—menjerit dalam diam. Kita hidup di era ketika alam diperas demi keuntungan sementara, dan kita kehilangan makna terdalam dari relasi kita dengan alam.
Dalam pusaran krisis ekologis ini, muncul sebuah pertanyaan mendesak: apakah manusia modern telah kehilangan bukan hanya akal sehat ekologis, tetapi juga kesadaran spiritual terhadap Bumi?
Spiritualitas Ekologis
Thomas Berry, seorang imam Katolik dan sejarawan budaya, dalam The Great Work: Our Way into the Future (1999), menyatakan bahwa Bumi bukanlah sekadar sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan “komunitas suci kehidupan” yang harus dihormati. Ia mengusulkan sebuah spiritualitas ekologis lintas agama—suatu kesadaran batiniah yang melihat alam sebagai bagian dari relasi sakral, bukan objek pasif untuk ditaklukkan. Dalam setiap tetes air, dalam setiap guguran daun, dalam setiap butiran pasir di sungai dan laut, dan banyak entitas lainnya, tersembunyi pesan Ilahi tentang keseimbangan dan kasih.
Bagi Berry, tugas besar umat manusia pada era kontemporer—yang ia sebut sebagai The Great Work—adalah melakukan transisi dari masyarakat industri yang merusak menjadi masyarakat ekologis yang menjalankan kehidupan secara selaras dengan alam. Ini bukan sekadar perubahan teknis atau kebijakan, melainkan transformasi mendalam dalam narasi budaya dan orientasi spiritual manusia. Berry percaya bahwa setiap peradaban memiliki “cerita besar” yang membentuk cara pandang terhadap dunia, dan krisis ekologis saat ini menunjukkan bahwa narasi modern—yang memisahkan manusia dari alam—telah gagal.
Oleh karena itu, tugas kita adalah membangun kembali sebuah kisah bersama yang menempatkan manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan, bukan penguasanya. Dalam kerangka pemikiran ini, spiritualitas ekologis menjadi fondasi etis dan emosional bagi perubahan peradaban yang lebih selaras dengan ritme Bumi.
Gerakan Ekologis sebagai Ibadah
Di luar angka dan kalkulasi, spiritualitas ekologis mengajak kita menapaki Bumi dengan hati yang penuh hormat. Merawat lingkungan bukan semata kewajiban moral, melainkan bagian dari zikir, ibadah yang hidup dalam tindakan. Dan Indonesia—dengan keragaman spiritualitas dan kekayaan alamnya—memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor penyatuan iman dan keberlanjutan ekologis.
Gerakan Islam Hijau (Green Islam) menjadi contoh konkret bagaimana spiritualitas dapat melahirkan inovasi ekologis. Di Garut, misalnya, dua masjid kembar dibangun menggunakan 12 ton plastik daur ulang dan 24 ton kulit padi. Menurut Irfan Amali dari Peacesantren Welas Asih, upaya ini bukan hanya soal teknologi ramah lingkungan, melainkan juga tindakan ibadah—penghormatan pada Bumi sebagai ciptaan Tuhan.
Langkah-langkah seperti ini penting, terutama dalam konteks Indonesia yang menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahun dengan plastik sebagai salah satu penyumbang utama. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berada di garis depan krisis iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pesisir.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya teknis, tetapi juga dalam mengerahkan sumber daya potensial yang ada untuk mengatasinya. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah komunitas umat beragama dan praktik keagamaannya. Dalam banyak kasus, praktik keberagamaan di Indonesia masih sering terjebak pada ritual formal. Seperti disorot dalam studi bertajuk “Religion and Social Values for Sustainability” (Springer Nature, 2019), nilai-nilai ekologis dalam agama kerap terhenti pada level simbolik atau gaya hidup pribadi, belum menjelma menjadi gerakan kolektif atau perubahan struktural yang mendalam.
Melampaui Simbolisme
Spiritualitas ekologis yang ditawarkan dalam banyak narasi hari ini, meskipun menyentuh, kerap terjebak dalam idealisme. Pertanyaannya: sejauh mana gagasan ini telah benar-benar mengakar dalam praktik keberagamaan masyarakat?
Pandangan teologi kontekstual dan teologi pembebasan menekankan bahwa iman sejati teruji dalam keberpihakan pada yang tertindas. Dalam konteks ekologi, alam adalah korban yang tak bersuara. Maka, menyatukan iman dengan keadilan ekologis bukan hanya soal narasi indah, tetapi soal membangun sistem keagamaan yang berani mengkritik struktur ekonomi-politik yang eksploitatif. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya.
Di sinilah kita perlu melampaui simbolisme. Seperti dikemukakan oleh Mircea Eliade dalam The Sacred and The Profane (1987), yang sakral bukan hanya hadir dalam ritus, tetapi juga dalam pola hidup sehari-hari. Sementara Rudolf Otto dalam The Idea of the Holy (2018) menyebut pengalaman akan yang Ilahi sebagai mysterium tremendum et fascinans—rasa gentar sekaligus takjub di hadapan kehadiran suci. Dalam kerangka ini, Bumi bukan sekadar “aset ekologis”, melainkan mitra dalam perjanjian suci manusia dengan Tuhan.
Indonesia punya modal besar: warisan kosmologis Nusantara yang mengajarkan relasi spiritual dengan tanah, air, dan langit. Tradisi dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia menyimpan nilai-nilai kosmis yang bisa menjembatani antara iman dan pelestarian lingkungan. Namun, ini hanya akan menjadi kekuatan transformatif jika spiritualitas ekologis benar-benar diinternalisasi sebagai gerakan kolektif lintas kelas, bukan sekadar wacana kalangan elite atau akademik.
Menjaga Bumi sebagai Zikir Terindah
Merawat Bumi bukan sekadar tugas ekologis; melainkan panggilan spiritual. Ia bukan utopia, tapi jalan hidup yang menghubungkan iman dengan tanggung jawab. Dalam setiap langkah kecil—mengurangi sampah, menanam pohon, membersihkan sungai—tersimpan kekuatan transenden yang menghubungkan manusia dengan penciptanya.
Indonesia, dengan keberagaman iman dan kekayaan hayatinya, memiliki kesempatan langka untuk menunjukkan kepada dunia: bahwa mencintai Bumi adalah bagian dari zikir yang paling indah. Namun untuk itu, spiritualitas kita harus lebih dari sekadar simbol. Ia harus menjadi kesadaran yang hidup, yang menyatu dalam tubuh dan jiwa masyarakat, dan bergerak menuju perubahan nyata.
Editor: Abul Muamar
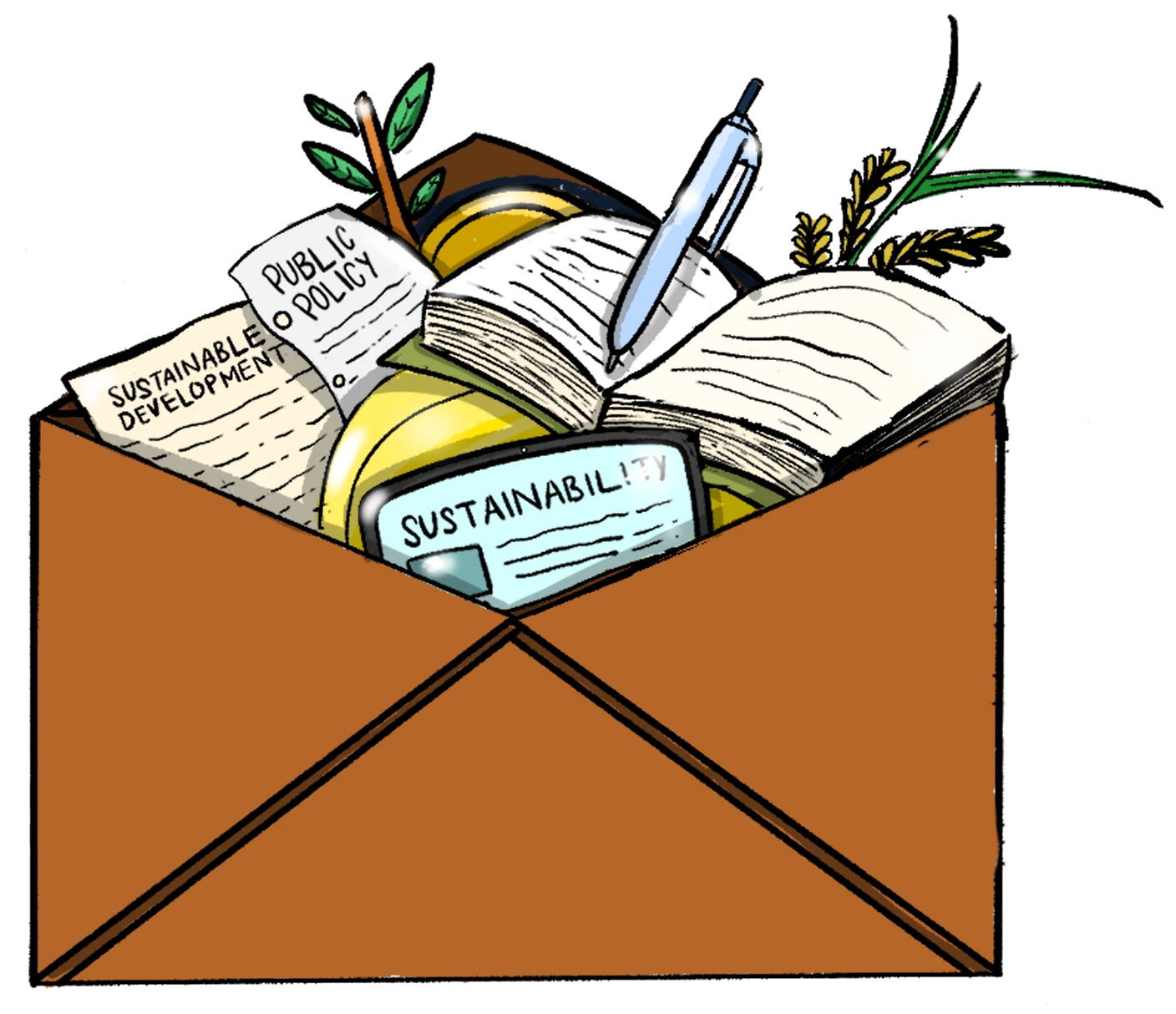
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Polykarp adalah dosen Teologi Fundamental pada Sekolah Tinggi Teologi KHKT (Kölner Hochschule für Katholische Theologie), Keuskupan Agung Köln, Jerman.


 Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB  Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global  Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan  Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia  Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah  Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja