Lian Gogali, Menghidupkan Kembali Harmoni di Poso Lewat Sekolah Perdamaian

Lian Gogali. | Foto: Arsip Institut Mosintuwu.
Awal Reformasi adalah masa-masa yang mencekam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Perselisihan antarpemuda pada malam Natal 1998 berkobar menjadi konflik komunal syarat kekerasan setelah disulut provokasi dan agitasi berbalut sentimen keagamaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerusuhan berkali-kali meletus hingga perdamaian disepakati pada 20 Desember 2001 melalui Deklarasi Malino I. Diperkirakan, dalam rentang waktu tersebut, lebih dari 550 orang meninggal dunia dengan ribuan rumah dan bangunan publik dibakar.
Meskipun Perjanjian Damai telah ditandatangani, spektrum kerusuhan di Poso masih terus berlanjut pada tahun-tahun setelahnya, apalagi dengan kehadiran kelompok-kelompok garis keras yang melancarkan aksi terorisme. Sayangnya, sisi kelam itu banyak disebarluaskan di berbagai saluran media tanpa cerita yang utuh.
Sebagai orang yang lahir dan tumbuh besar di Poso, Lian Gogali memandang bahwa konflik sektarian yang terjadi di Poso saat itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. “Konflik terjadi akibat kepentingan ekonomi-politik. Di tataran pemuda, bentrok sering terjadi hanya karena ego anak muda, termasuk karena masalah asmara. Jadi, ketika mendengar narasi Islam dan Kristen saling bunuh, saya merasa ada yang hilang dari cerita yang disampaikan oleh media massa,” katanya.
Mendirikan Sekolah Perdamaian Berupa Sekolah Perempuan

Kegelisahan Lian tidak hanya sebatas soal penyebaran narasi tidak utuh yang berdampak pada citra Poso. Ia juga melihat bahwa dalam proses pembangunan pascakonflik, peran perempuan kerap diabaikan. Padahal, menurutnya, perempuan Poso punya andil dan potensi besar dalam menjaga harmoni dan perdamaian di Poso sejak dulu.
Seiring waktu bergulir, Lian mulai menemukan jalan untuk mewujudkan kegelisahannya ke dalam bentuk tindakan. Itu bermula ketika ia mengerjakan penelitian untuk pendidikan masternya di Universitas Sanata Dharma pada 2003-2004. Mengambil topik ‘Politik Ingatan Perempuan dan Anak dalam Konflik Poso’, Lian mewawancarai ratusan perempuan dan anak-anak yang kehidupannya terdampak konflik di Poso. Suatu ketika, dari seorang perempuan tua yang ia wawancarai di pengungsian di Desa Silanca, Kecamatan Lage, ia mendapat satu pertanyaan yang menghantuinya sampai bertahun-tahun kemudian.
“Saya ingat sekali. Ibu itu sedang memasak mi instan waktu itu. Dia bertanya ke saya, ‘Terus kalau kamu sudah menulis penelitian tentang kami, lalu apa? Apa yang akan berubah dari kehidupan kami?’ Pertanyaan itu menjadi pukulan telak di wajah saya, menjadi utang buat saya,” kata perempuan kelahiran Poso, 28 April 1978 ini.
Karena itu, begitu menyelesaikan studinya di Yogyakarta, ia memantapkan diri untuk pulang ke Poso alih-alih berkarier di kota perantauan. Setelah memikirkan langkah yang dapat ia lakukan dan merancang konsep selama lima tahun, akhirnya, pada tahun 2009, ia mendirikan Institut Mosintuwu, sebuah komunitas akar rumput yang bekerja untuk mewujudkan perdamaian. Sekolah Perempuan Mosintuwu menjadi program pertama yang ia buat. Kata ‘mosintuwu’ sendiri diambil dari bahasa Pamona, salah satu suku di Poso, yang berarti ‘bekerja bersama-sama’.
“Ketika mengerjakan tesis itu, saya tidak hanya mendapat kisah tentang lapisan kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak mereka, tetapi juga banyak cerita tentang peran perempuan dalam menjaga perdamaian di Poso. Bagaimana perempuan Islam membantu perempuan Kristen, perempuan Kristen membantu perempuan Islam. Mereka saling membantu dalam keseharian–sesuatu yang hampir tidak pernah diceritakan oleh media massa. Karena itu, saya melihat kekuatan perempuan seharusnya menjadi modal besar bagi pembangunan perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan di Poso,” tuturnya.
Melalui sekolah perdamaian ini, Lian mempertemukan para perempuan dari berbagai latar belakang untuk saling bertukar pikiran, mengurai prasangka dan asumsi tentang perbedaan agama, termasuk ajaran, wacana, dan tradisi. “Sekolah Perempuan membuka ruang untuk bertemu, bersama-sama mengelola isu, mengelaborasinya, lalu membuat kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak bagi kehidupan. Jadi bukan cuma memikirkan gagasan, tapi ada kegiatan setelahnya,” kata Lian.

Terdapat sembilan pelajaran dalam Sekolah Perempuan, yakni Perempuan dan Perdamaian; Gender; Perempuan dan Budaya; Perempuan dan Politik; Keterampilan Berbicara dan Bernalar; Hak Layanan Masyarakat; Hak Ekonomi, Sosial-budaya, dan Politik; Kesehatan Seksual dan Hak Reproduksi; dan Ekonomi Solidaritas.
Perihal pelajaran yang disebutkan terakhir, Sekolah Perempuan berupaya untuk menciptakan kedaulatan ekonomi para perempuan lewat ekowisata dan perkebunan organik dengan pendekatan permakultur.
“Ekonomi Solidaritas ini sebenarnya adalah bagian dari cara kami mengkritik konsep ekonomi kreatif yang selama ini digaungkan oleh pemerintah, yang menganggap alam sebagai objek ekonomi yang bisa dieksploitasi. Kami berpikir bahwa kami perlu mengembangkan ekonomi yang bersolidaritas, bukan hanya antar-manusia, tapi juga solidaritas dengan alam,” katanya.
Sekolah Pembaharu Desa, Sekolah Keberagaman, dan Sekolah Rumah Kita
Hampir sepuluh tahun Sekolah Perempuan berjalan, Lian melihat bahwa upaya untuk merawat perdamaian tidak cukup hanya dengan melibatkan perempuan. Dalam banyak kesempatan, ia menyadari bahwa unsur masyarakat lainnya seperti laki-laki, pemuda, hingga tokoh masyarakat punya peran signifikan sehingga perlu dilibatkan. Pada saat yang sama, ia juga melihat bahwa peserta Sekolah Perempuan membutuhkan kegiatan setelah lulus.
Akhirnya, sejak tahun 2017, ia mulai menggagas program-program lain, seperti Sekolah Pembaharu Desa dan Sekolah Rumah Kita. Sekolah-sekolah ini mengajarkan pesertanya untuk mampu berpikir kritis terhadap konsep pembangunan di Indonesia.
Untuk Sekolah Pembaharu Desa, pesertanya adalah para perempuan lulusan Sekolah Perempuan yang bersedia melakukan advokasi di desa-desa di Poso bersama unsur masyarakat lainnya. Mereka terdiri dari tim advokasi kekerasan, tim perlindungan anak, tim advokasi layanan dan hak masyarakat, tim usaha desa, hingga tim media.
“Tim media ini mendorong terciptanya transparansi di desa. Para ibu-ibu perempuan lulusan Sekolah Perempuan melakukan reportase yang kemudian disiarkan melalui radio kami. Kami punya radio komunitas, Radio Mosintuwu namanya,” kata Lian.

Adapun Sekolah Rumah Kita merupakan ruang diskusi dan belajar untuk anak-anak muda dari berbagai latar belakang. “Di sekolah ini, anak-anak muda berkumpul bukan cuma bertemu dan berteman, tapi juga memikirkan masa depan dan melihat nilai-nilai yang ada di dalam Kebudayaan Poso. Ini penting untuk membentuk cara pandang mereka terhadap pembangunan di Kabupaten Poso, membuat mereka merasakan dan mempraktikkan perdamaian,” kata Lian.
Para tokoh agama juga tidak luput dari jangkauan Lian. Melihat peran vital tokoh agama dalam menjaga perdamaian, Lian juga menggagas Sekolah Keberagaman sebagai forum bagi para tokoh agama untuk saling berbagi pengalaman dan wawasan dalam bingkai toleransi dan persaudaraan.
“Bukan hanya pendeta atau imam, tetapi juga termasuk mahasiswa-mahasiswa dari sekolah tinggi keagamaan. Ruang pendidikan kritis di Sekolah Keberagaman ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman bahwa agama-agama itu bukan hanya tentang surga dan neraka, tetapi perlu berperan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Lian.
Sekolah Perdamaian untuk Anak-anak

Tak sampai di situ, Lian juga menginisiasi sekolah perdamaian untuk anak-anak lewat Project Sophia. Project Sophia terdiri dari perpustakaan keliling dan Perpustakaan Sophia yang berada lokasi Institut Mosintuwu di Tentena, Pamona Puselemba.
Seperti tiga sekolah yang telah diceritakan sebelumnya, ide pembentukan sekolah untuk anak-anak ini juga berangkat dari proses berjalannya Sekolah Perempuan, yang pesertanya banyak merupakan ibu-ibu yang memiliki anak yang masih kecil. Nama Project Sophia sendiri diambil dari nama anak Lian, Sophia Ava Choirunissa.
“Mereka (para perempuan) sering membawa anak-anak mereka saat ikut kelas. Tapi saya lihat anak-anak ini tidak punya ruang untuk berkegiatan. Nah, kebetulan anak saya, Sophia, suka sekali membaca buku. Dari situ, saya melihat bahwa membaca buku bisa menjadi kegiatan anak-anak kecil itu,” kata Lian.
Seperti halnya perempuan, anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan perdamaian karena mereka termasuk kelompok yang paling merasakan dampak konflik. Selain itu, dalam kehidupan pascakonflik, mereka juga kelompok yang paling rentan terpapar hasutan dan narasi kebencian.
“Selama melakukan riset untuk tesis saya itu, saya lihat anak-anak seringkali diabaikan dan dianggap tidak mengerti apa-apa. Padahal mereka punya ingatan traumatik yang sangat kuat tentang konflik. Terbukti saat di pengungsian, saya melihat anak-anak itu menggambar dengan sangat detail tentang bagaimana mereka hidup di pengungsian, bagaimana mereka melihat orang-orang ditembak, rumah mereka dibakar, dan seterusnya,” kata Lian.
Melalui Project Sophia, Lian membekali anak-anak korban konflik dan kekerasan tersebut dengan buku-buku yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan respek terhadap perbedaan sejak dini. “Tujuannya untuk membangun dialog antar anak-anak. Sekarang, Project Sofia sudah berkembang. Selain dengan buku, kita juga menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui dongeng. Dan anak-anak suka sekali dengan dongeng,” jelas Lian.
Memutus Benang Konflik

Semua inisiatif yang telah dilakukan Lian bukannya tanpa rintangan. Sejak hari pertama kembali ke Poso setelah menamatkan studinya, ia sudah menghadapi berbagai rintangan yang begitu berat. “Tinggal di Poso dengan dunia yang sangat patriarkis dan feodal bukanlah pilihan yang mudah. Apalagi saya punya seorang anak tapi tidak menikah. Ada banyak sekali diskriminasi dan desakan yang saya alami,” katanya.
Tantangan terasa semakin berat karena sebelumnya ia tidak pernah mengorganisir orang-orang. “Saya ini berlatar belakang penulis dan peneliti. Saya belum punya pengalaman sama sekali dalam memimpin organisasi. Ketika konsep dan gerakan kritis ini saya perkenalkan, beberapa kali saya dikirimi pesan dan didatangi oleh para suami dari para perempuan itu. Mereka tidak setuju dengan pengetahuan yang saya bagikan. Tapi, itu justru menjadi kesempatan buat saya untuk melakukan dialog dengan mereka. Jadi, ya, semuanya learning by doing,” kenangnya.
Tantangan terberat Lian bukanlah hadangan dari para laki-laki sebagai individu, tetapi justru dari pemerintah setempat yang menurutnya terusik dengan gagasan yang ia tularkan kepada para perempuan di Poso.
“Dan situasinya menjadi semakin sulit ketika pemerintah ‘berselingkuh’ dengan pemodal dan para oknum di institusi agama. Konsep-konsep dan gerakan akar rumput seringkali dibendung oleh perselingkuhan itu. Pemerintah dengan kekuasaannya, pemodal dengan modalnya, oknum agama dengan ayat-ayatnya. Gerakan akar rumput seperti kami ini sering dibungkam dengan menyebut bahwa itu bukan berasal dari Tuhan,” ujarnya.
Namun, tekad Lian tak pernah surut. Sebab, ia percaya dengan persatuan dan perdamaian, kekuatan masyarakat akar rumput mampu mengubah keadaan dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Lebih dari satu dekade berjalan, Sekolah Mosintuwu kini hadir di lebih dari 80 desa di Poso, memutus benang konflik di antara generasi penerus dalam komunitas dengan latar belakang yang berbeda. Masyarakat Poso kini kembali hidup dalam harmoni dan damai seperti sedia kala, saling bahu-membahu dalam urusan sehari-hari, dan membuang segala prasangka buruk jauh-jauh dari hati dan pikiran mereka. Anak-anak mereka hidup membaur, bermain bersama, dan saling tolong-menolong.
“Saya hanya berharap bahwa apa yang selama ini Mosintuwu telah lakukan bersama-sama dengan masyarakat, dapat mempengaruhi cara pandang serta mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi manusia dan alam,” kata Lian.
Lian pun kini bisa tersenyum lega. Pertanyaan yang menghantuinya selama bertahun-tahun telah ia jawab dengan tindakan nyata.
Ia kini banyak menghabiskan hari-harinya di Dodoha Mosintuwu, sebuah perpustakaan yang dibangun dengan bilah-bilah bambu di tepi Danau Poso, melakukan kerja-kerja merawat perdamaian sembari memandangi danau yang indah. Dodoha sekaligus menjadi pusat kegiatan Institut Mosintuwu dan tempat berkumpulnya para perempuan penjaga perdamaian dari berbagai latar belakang agama dan suku.
“Yah, beginilah hari-hari saya,” katanya, tersenyum simpul, saat saya mengunjunginya di Dodoha suatu sore pada April 2019.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.


 Infrastruktur Tak Terlihat yang Dibutuhkan Pasar Karbon ASEAN
Infrastruktur Tak Terlihat yang Dibutuhkan Pasar Karbon ASEAN  Pemerintah Mulai Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo
Pemerintah Mulai Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo  Dari Sawah ke Tambak: Transformasi Desa Kecipir di Brebes dan Kerentanan Tersembunyi di Baliknya
Dari Sawah ke Tambak: Transformasi Desa Kecipir di Brebes dan Kerentanan Tersembunyi di Baliknya  Clean Cooking sebagai Pengganda Pembangunan di Afrika
Clean Cooking sebagai Pengganda Pembangunan di Afrika 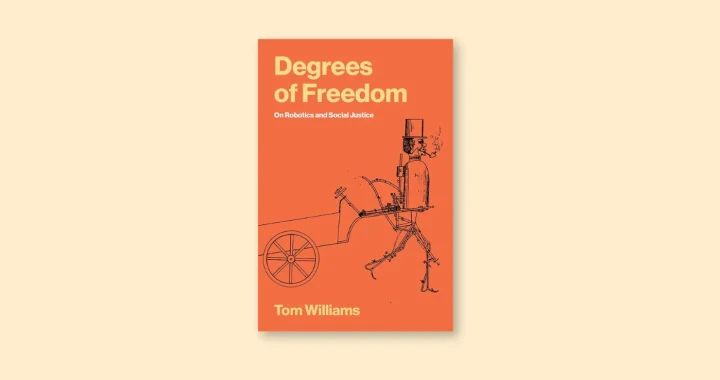 Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams
Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams  Memperkuat Penanggulangan Campak di Indonesia
Memperkuat Penanggulangan Campak di Indonesia