Aktivisme Iklim Kaum Muda Tak Boleh Abai Soal Kolonialisme

Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Dalam dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana kaum muda di seluruh dunia telah menjadi wajah gerakan keadilan iklim. Dari Fridays for Future hingga Extinction Rebellion Youth, para aktivis Gen Z mendorong perubahan iklim ke dalam wacana arus utama di tengah masyarakat kita. Mereka aktif dalam pawai, inisiatif, pidato yang penuh semangat, serta melakukan kampanye digital di media sosial. Di tengah gerakan yang terus berkembang ini, ada urgensi untuk menggarisbawahi sebuah paradigma: mendekolonisasi aktivisme iklim kaum muda.
Perubahan Iklim dan Kolonialisme
Seiring berkembangnya gerakan ini, kritik juga muncul: lingkungan hidup arus utama seringkali dibingkai secara terpisah dari sejarah dan struktur kekuasaan yang menciptakan krisis sejak awal. Perubahan iklim bukan sekadar masalah ilmiah. Melainkan, ia merupakan akibat langsung dari ekstraksi, perampasan, dan eksploitasi sumber daya oleh kolonial. Perubahan iklim berdampak dan terdampak oleh pembangunan yang tidak merata antara negara-negara Global North dan negara-negara Global South.
Kolonialisme telah berperan dalam ekonomi ekstraktif yang memperlakukan tanah, air, dan manusia sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi. Kini, kolonialisme dapat bersemayam di balik nama-nama baru: pembangunan, transisi, keamanan, dan investasi.
Upaya pembangunan negara-negara Global North seringkali bergantung pada ekstraksi dan eksploitasi tenaga kerja dan ketersediaan lahan dari negara-negara Global South. Dorongan untuk inovasi “hijau” seperti kendaraan listrik, misalnya, bergantung pada litium dari Bolivia, kobalt dari Kongo, dan nikel dari Indonesia. Namun, masyarakat yang tinggal di tanah-tanah tersebut jarang yang diuntungkan. Yang mereka dapatkan adalah polusi, perampasan tanah, dan penggusuran.
Perang dan pendudukan juga meninggalkan luka ekologis mendalam yang jarang diangkat dalam perbincangan iklim. Di Palestina, misalnya, pemboman militer telah menghancurkan kebun zaitun, lahan pertanian, dan infrastruktur air. Isu-isu ini masih sukar dipahami dan jarang dibahas dalam forum-forum lingkungan internasional yang diadakan setiap tahunnya.
Dekolonisasi Aktivisme Iklim Kaum Muda
Aktivisme iklim kaum muda rentan menghidupkan kembali ketidakadilan yang sudah ada. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika kita melihat suara siapa yang diutamakan dan realitas siapa yang diabaikan.
Mayoritas aktivis iklim orang muda tersohor yang mendapat perhatian media massa berasal dari Global North. Hal ini menarik, mengingat fakta bahwa komunitas di Global South adalah yang menghadapi dampak paling parah dari kerusakan lingkungan. Penghapusan aktivis Uganda, Vanessa Nakate, dari foto pers pada tahun 2020 merupakan contoh bias media dan gambaran bagaimana narasi iklim masih mencerminkan hierarki kolonial.
Namun, masih ada ruang untuk berkembang, dan orang muda terus berevolusi. Greta Thunberg, misalnya, adalah salah satu suara paling dikenal dalam gerakan ini. Aktivismenya mewakili kemarahan dan urgensi generasi muda sekaligus menunjukkan rasa kebersamaan, kegigihan, dan kejelasan moral.
Greta juga menandai sebuah pelajaran yang dapat dipetik, sebuah pergeseran kesadaran dalam aktivisme iklim orang muda. Awalnya, ia memfokuskan aktivismenya pada emisi dan ketidakpedulian pemerintah. Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, ia juga berbicara tentang hak atas tanah masyarakat adat, pendudukan Palestina, dan kekerasan lingkungan dalam perang dan militerisme. Hal ini menunjukkan semakin berkembangnya pemahaman di kalangan orang muda bahwa keberlanjutan tanpa keadilan tidaklah lengkap.
Generasi Z di seluruh dunia menyadari bahwa krisis iklim tidak dapat dipisahkan dari sistem politik dan ekonomi yang menyebabkan dan menopangnya. Ada pemahaman yang semakin berkembang bahwa ketika aktivis lingkungan menyerukan tindakan tanpa mengakui akar penyebabnya, maka akan ada risiko depolitisasi masalah tersebut.
Mewujudkan Aksi Iklim Berbasis Keadilan
Seruan untuk aksi iklim bukan lagi sekadar “mendengarkan sains”. Seruan ini tentang mendengarkan dan memperjuangkan orang-orang yang telah menentang kekerasan lingkungan selama beberapa generasi. Agar aktivisme iklim kaum muda dapat bermakna, Gen Z harus terus bergerak melampaui peningkatan kesadaran, menuju penataan ulang lingkungan hidup melalui lensa keadilan.
Artinya apa? Orang muda harus menolak solusi iklim dan lingkungan yang mereproduksi ketimpangan. Ini termasuk mempertanyakan lahan siapa yang digunakan untuk proyek pembangunan berkelanjutan dan memusatkan perhatian pada komunitas yang kehidupannya dibentuk oleh warisan kolonial dan militerisme masa kini. Selain itu, ini juga berarti mengakui fakta bahwa tujuan nol bersih mustahil tercapai ketika entitas yang sama yang mengadvokasinya terus mendanai ekstraksi bahan bakar fosil dan mendukung perang yang meracuni tanah dan air.
Pada akhirnya, kerusakan lingkungan akan dan selalu mengikuti jejak kekuasaan kolonial. Dekolonisasi environmentalisme tidak akan melemahkan gerakan tersebut; justru memperkuatnya. Dekolonisasi membuka pintu bagi solusi yang berakar pada akuntabilitas, solidaritas, dan welas asih. Aktivisme iklim kaum muda harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik dari advokasi dan gerakan mereka. Aktivisme iklim harus menyerukan transformasi sistem yang menggerakkan dunia.
Jika Gen Z ingin mendefinisikan ulang masa depan Bumi, mereka juga harus mendefinisikan ulang perjuangannya: tidak hanya melawan perubahan iklim, tetapi juga melawan struktur yang menciptakannya sejak awal.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
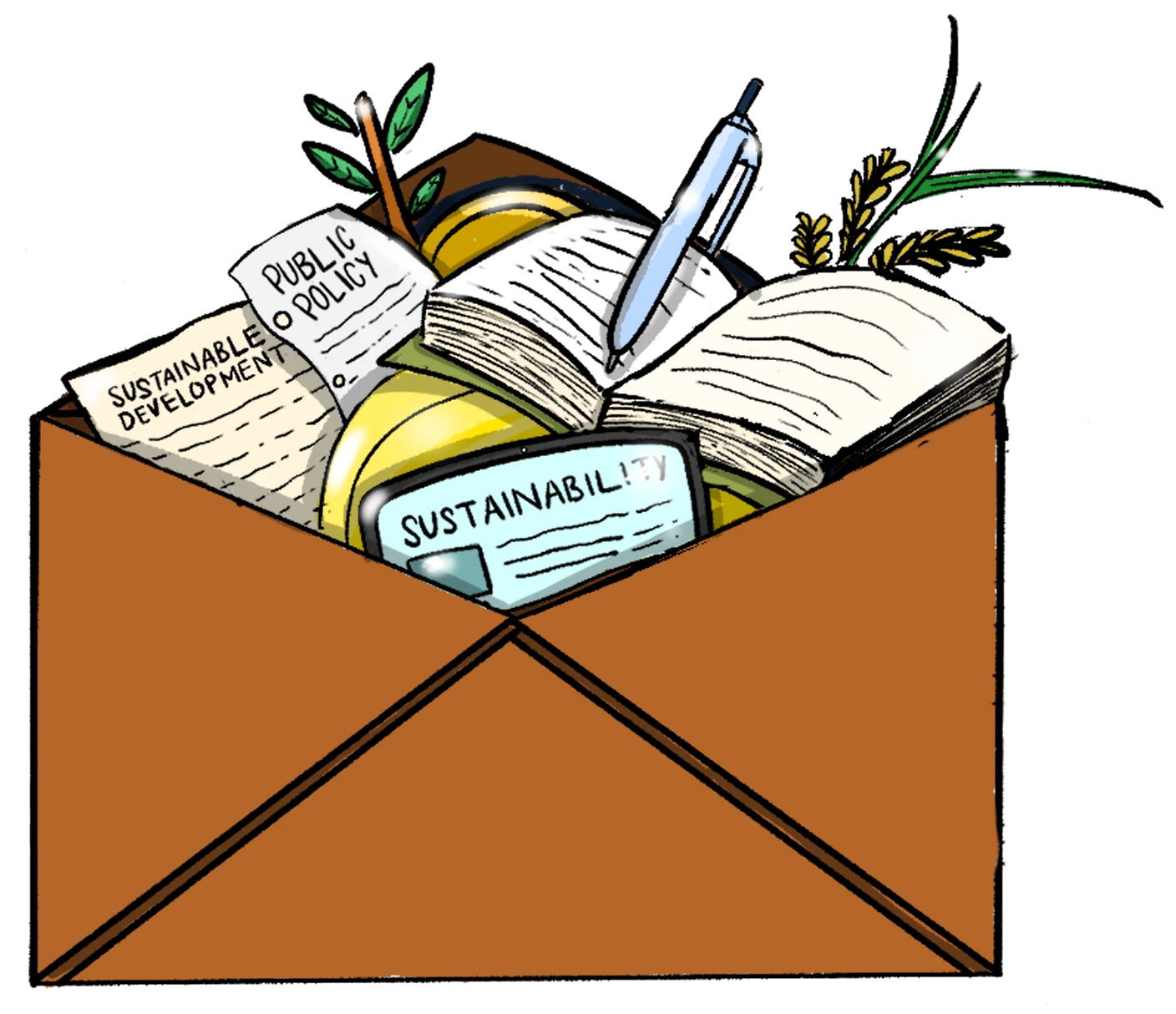
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Cahaya adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Fokus akademiknya adalah keadilan global, dekolonisasi, dan representasi minoritas. Ia memiliki minat khusus pada isu-isu lingkungan dan sosial.


 Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan
Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan  Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut
Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut  Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data
Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data  Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara
Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara  Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh
Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh  Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia