Mekanisme Anti-SLAPP Lewat Putusan Sela: Harapan Baru bagi Pembela Lingkungan?

Foto: fabrikasimf di Freepik.
Jalur hukum merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan untuk mencari keadilan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman. Namun pada saat yang sama, jalur hukum sering digunakan untuk menekan partisipasi publik, salah satunya lewat Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP). Di Indonesia, pembelaan terhadap SLAPP atau mekanisme anti-SLAPP masih kerap tidak efektif dan terdapat banyak celah.
Anti-SLAPP di Indonesia dan Celahnya
Secara umum, SLAPP merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politiknya. Ini merupakan sebuah gugatan yang ditujukan kepada individu atau organisasi untuk menuntut perbuatan tertentu. SLAPP juga merupakan bentuk pembungkaman partisipasi publik dan kebebasan berekspresi.
Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang mengatur prinsip pembelaan terhadap SLAPP (Anti-SLAPP), seperti Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) juga menyatakan bahwa setiap gugatan perdata yang terindikasi bertujuan untuk menjegal perjuangan masyarakat dalam meraih hak atas lingkungan yang berkualitas adalah pelanggaran terhadap Pasal 66 UU PPLH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah menerbitkan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
Namun, peraturan-peraturan yang ada kenyataannya belum dijalankan secara efektif. Data Auriga Nusantara mencatat bahwa sepanjang tahun 2014-2023 setidaknya terdapat 133 tindakan SLAPP terhadap pembela lingkungan. Di sisi lain, masih ada beberapa peraturan yang membuka ruang ancaman bagi pembela lingkungan maupun partisipasi publik. Misalnya, kriminalisasi dengan UU ITE seperti yang terjadi pada Daniel Frits di Karimunjawa, Pasal 162 UU Minerba yang dapat memberi sanksi pidana bagi individu/kelompok yang merintangi kegiatan pertambangan, hingga pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara seperti dalam kasus Budi Pego, aktivis lingkungan di Banyuwangi.
Regulasi yang sering tidak berkorelasi dengan permasalahan lingkungan dapat menyebabkan pemilihan majelis hakim yang tidak bersertifikasi lingkungan sehingga menimbulkan risiko pembelaan SLAPP semakin sulit atau bahkan tidak diterima. Sementara itu, Pasal 66 UU PPLH juga tidak menyebutkan secara jelas kegiatan advokasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai “memperjuangkan hak atas lingkungan”, sehingga rawan ditafsirkan secara sempit dan hanya mengacu pada perjuangan yang menggunakan langkah-langkah hukum. Akibatnya, aksi protes dan demonstrasi damai dapat dikategorikan “tidak dilindungi”.
Ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia juga belum memiliki dimensi restoratif, yaitu belum menyediakan pemulihan nama baik maupun kompensasi atas kerugian finansial, psikologis, hingga moral yang dialami oleh korban SLAPP.
Mekanisme Anti-SLAPP Lewat Putusan Sela
Namun, masih ada harapan. Pada 8 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong menolak melanjutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) terhadap dua akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis. Melalui putusan sela, Majelis Hakim menyatakan gugatan PT KLM tidak dapat diterima.
Dalam keputusannya, Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan dalam Pasal 66 UU PPLH yang mencakup “setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2023, penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan termasuk dalam bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang dilindungi.
Sebelumnya, PT KLM mengajukan gugatan terhadap Bambang dan Basuki karena memberikan keterangan ahli dalam sidang perkara kebakaran lahan gambut di areal perkebunan PT KML di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Keterangan dua akademisi tersebut membuat PT KLM dihukum membayar ganti kerugian lingkungan hidup hingga ratusan miliar rupiah.
Keterangan ahli seperti yang disampaikan Bambang dan Basuki merupakan salah satu bentuk hak warga negara untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Pasal ini juga menjamin bahwa pembela lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa keterangan Bambang dan Basuki merupakan bagian dari advokasi lingkungan; dan gugatan terhadap mereka merupakan tindakan SLAPP.
Memperluas Sasaran Anti-SLAPP
Regulasi yang mengatur Anti-SLAPP perlu diperkuat agar dapat lebih efektif dalam menepis kasus SLAPP, menghilangkan upaya pembungkaman dan mencegah ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyuarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik. Regulasi yang dibutuhkan setidaknya memuat secara jelas definisi SLAPP dan bentuk-bentuk tindakan strategis yang mungkin terjadi, definisi dan prosedur mekanisme Anti-SLAPP, koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menghentikan SLAPP sedini mungkin, hingga definisi pejuang HAM atas lingkungan dan bentuk-bentuk perjuangan yang dilindungi. Selain itu, pemerintah juga mesti memperluas aturan terkait SLAPP agar tidak terbatas pada kasus lingkungan hidup, tetapi juga mencakup kasus-kasus lainnya yang terkait dengan partisipasi publik.
Editor: Abul Muamar
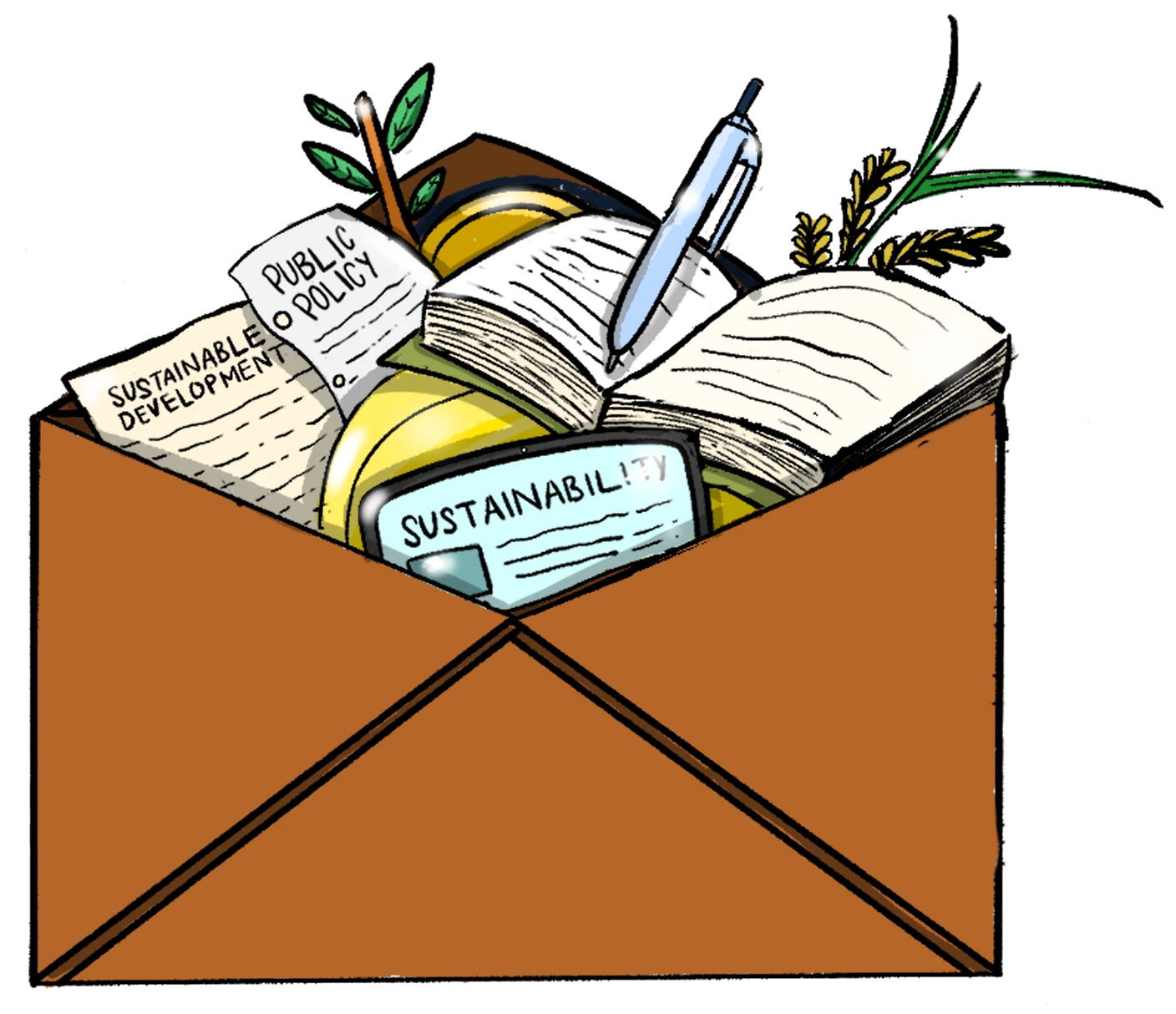
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.


 Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB
Memahami Perjanjian Laut Lepas PBB  Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global
Menilik Langkah Indonesia Bergabung dengan Koalisi Pasar Karbon Global  Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan
Risiko dan Peluang Kabel Bawah Laut bagi Pembangunan Berkelanjutan  Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia  Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah
Meningkatnya Serangan dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan Tanah  Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Menyoal Ketentuan Upah Minimum dan Tantangan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja