Menjadi Jembatan Keberlanjutan: Strategi Manajer Madya di Tengah Kelembaman dan Desakan Perubahan
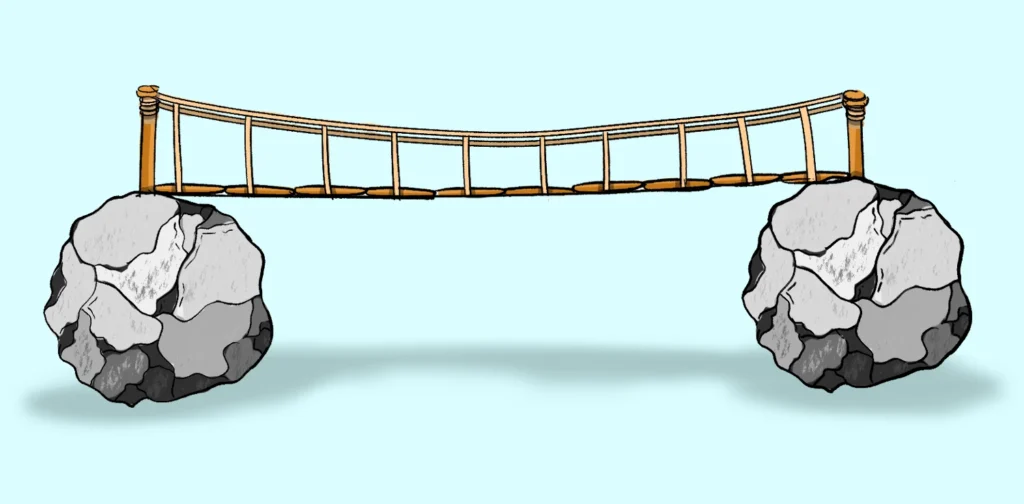
Ilustrasi: Irhan Prabasukma.
Jika apa yang saya pelajari tentang transformasi keberlanjutan perusahaan benar, selalu saja ada sekelompok orang yang punya posisi sangat menarik di dalam proses itu. Mereka tidak sepenuhnya memiliki kuasa untuk mengubah arah kebijakan organisasi, namun cukup dekat dengan denyut perubahan untuk menyadari bahwa arah lama tak lagi memadai. Dalam konteks keberlanjutan perusahaan di Indonesia, kelompok itu adalah para manajer madya—generasi pemimpin operasional yang kini terjepit di antara dua arus besar.
Di satu sisi, mereka menghadapi manajemen puncak yang terus saja berhitung soal ‘biaya’ keberlanjutan dan takut kehilangan keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada para pekerja muda, terutama generasi Milenial dan Gen Z, yang tidak hanya menginginkan karier, melainkan juga makna dan pengakuan atas dampak sosial-lingkungan positif dari pekerjaan mereka. Ketegangan yang harus mereka hadapi bukanlah sekadar dilema manajerial di level perusahaan, tetapi juga titik krusial dalam perjalanan transformasi seluruh perusahaan Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan.
Namun, posisi ‘terjepit’ itu bisa menjadi hal paling strategis bagi mereka—jika dimanfaatkan dengan cerdas. Dari posisi tengah inilah manajer madya dapat menggerakkan perubahan ke atas, ke samping, dan ke bawah secara bersamaan. Mereka tidak perlu menunggu perintah dari puncak, dan tidak perlu menuruti semua desakan dari kiri-kanan maupun bawah; mereka bisa menjadi katalis yang menyalurkan energi perubahan menjadi sistem yang secara nyata mewujudkan tujuan berkelanjutan.
Tujuh Aspek Strategis
Ada setidaknya tujuh aspek strategis yang saya pikir dapat dilakukan untuk memajukan keberlanjutan dalam situasi seperti itu. Ini tentu saja bukan daftar yang sudah lengkap, dan saya tuliskan utamanya untuk mengundang refleksi dan diskusi lebih lanjut. Saya akan mendiskusikan ketujuhnya, dimulai dari yang mungkin paling besar daya ungkitnya.
Aspek pertama adalah membingkai ulang keberlanjutan sebagai sumber nilai strategis, bukan ‘sekadar’ tanggung jawab moral atau kewajiban pemenuhan regulasi. Salah satu penyebab utama kelembaman di tingkat manajemen puncak adalah pandangan bahwa keberlanjutan hanyalah ‘biaya tambahan’. Keberlanjutan dipandang baik untuk reputasi, tetapi tidak esensial bagi daya saing.
Manajer madya harus menjadi narator ulung yang mampu mengubah narasi kuno tersebut. Mereka perlu membuktikan, dengan data dan logika bisnis, bahwa keberlanjutan justru memperkuat profitabilitas dan ketahanan jangka panjang. Contohnya, peningkatan efisiensi energi bukan sekadar untuk kepentingan mengurangi jejak karbon, tetapi juga menurunkan biaya operasional. Program pengembangan masyarakat bukan sekadar bentuk filantropi, tetapi alat penting dalam menciptakan stabilitas sosial di sepanjang rantai pasok. Saat manajer madya mampu menunjukkan hubungan langsung antara inisiatif keberlanjutan dan kinerja finansial dengan teori perubahan yang tak terbantah, resistensi dari atas akan mulai mencair. Dalam banyak kasus yang saya amati, perubahan besar tidak bermula dari kebijakan, melainkan dari bukti-bukti kecil yang mengubah persepsi dari risiko menjadi peluang.
Aspek kedua adalah membangun aliansi lintas-fungsi untuk memperkuat posisi keberlanjutan dalam operasi sehari-hari. Keberlanjutan tidak akan hidup jika hanya dimiliki oleh satu divisi, departemen, apalagi individu. Dalam banyak percakapan yang saya ikuti, para manajer madya terjebak dalam ilusi bahwa mereka perlu ‘mandat resmi’ terlebih dahulu, misalnya dalam bentuk komite eksekutif, untuk bisa bergerak. Padahal, perubahan paling kuat sering kali datang dari kerja sama informal antarbagian—dari keuangan, operasi, pemasaran, hingga SDM—yang saling menemukan kepentingan bersama.
Misalnya, seorang manajer di bagian produksi dapat berkolaborasi dengan bagian keuangan untuk membangun business case bagi investasi teknologi yang efisien; sementara bagian SDM dapat membantu menanamkan prinsip keberlanjutan dalam program pelatihan pekerja baru. Aliansi semacam ini tidak hanya memperkuat daya dorong internal, tetapi juga menciptakan ekosistem mini di dalam organisasi yang menormalisasi keberlanjutan sebagai cara berpikir, bukan sekadar projek. Inilah mengapa untuk bisa mempengaruhi ke atas dan menjawab ekspektasi dari bawah, para manajer madya perlu sangat menguasai gerakan ke samping.
Aspek ketiga adalah mengaktifkan suara generasi muda secara produktif, bukan reaktif. Banyak manajer madya merasa tertekan oleh semangat moral pekerja muda yang menginginkan perubahan besar ‘sekarang juga’. Tekanan itu bisa benar-benar terasa mengganggu, tetapi sebenarnya merupakan aset besar jika dikelola dengan baik.
Milenial dan Gen Z jelas membawa energi, kreativitas, serta sensitivitas terhadap isu sosial dan lingkungan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kunci terpentingnya adalah mengubah energi itu menjadi kolaborasi, bukan konfrontasi. Misalnya, manajer dapat memfasilitasi fora internal seperti ‘Green Innovation Lab‘ atau ‘Sustainability Sprint‘, di mana pekerja muda bisa mengusulkan solusi dan bereksperimen dalam skala kecil terlebih dahulu. Dengan cara ini, generasi muda merasa dihargai dan dilibatkan, sementara manajemen puncak dapat mengamati potensi inovasi tanpa merasa kehilangan kontrol. Pendekatan ini mengubah idealisme menjadi laboratorium ide yang konkret dan berorientasi hasil.
Aspek keempat adalah menanamkan metrik keberlanjutan dalam sistem pengukuran kinerja operasional. Sering kali, inisiatif keberlanjutan tidak berjalan bukan karena kurangnya motivasi, tetapi karena tidak ada ukuran yang mengikat terhadap bagian yang benar di dalam perusahaan. Apa yang tidak diukur, tidak akan dikelola, begitu nasihat Peter Drucker.
Karenanya, manajer madya dapat memainkan peran kunci dengan memperkenalkan indikator yang relevan dan mudah diintegrasikan ke dalam target kinerja, misalnya intensitas energi per unit produksi, rasio limbah daur ulang, atau tingkat partisipasi pekerja dalam program sosial. Ketika keberlanjutan menjadi bagian dari sistem evaluasi formal, maka pesan yang tersampaikan ke seluruh organisasi jelas: keberlanjutan bukan aktivitas sampingan, melainkan bagian dari kinerja inti. Pendekatan ini juga membantu menjembatani bahasa idealisme, yang sering digunakan oleh generasi muda, dengan bahasa bisnis yang mungkin masih menjadi cara komunikasi satu-satunya manajemen puncak.
Aspek kelima adalah menjadi role model dalam gaya kepemimpinan yang berkarakter transformatif. Dalam konteks keberlanjutan, kepemimpinan bukan hanya soal memberi arahan, tetapi menumbuhkan budaya yang memungkinkan dan memfasilitasi perubahan.
Para manajer madya perlu memperlihatkan integritas—konsistensi antara kata dan tindakan—yang membangun kepercayaan di kedua arah: ke atas dan ke bawah. Mereka harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, seperti menolak praktik yang tidak etis meskipun biasa dilakukan oleh bagian atau perusahaan lain, atau mendorong transparansi meski berisiko menimbulkan ketegangan. Kepemimpinan yang autentik semacam ini selalu memiliki efek domino. Ia menular, biasanya dimulai dengan lambat tetapi kemudian menjadi cepat luar biasa ketika bertemu momentum. Ketika pekerja melihat pemimpinnya berani bersikap, mereka akan meniru. Ketika manajemen puncak melihat hasilnya nyata, mereka mulai berpikir untuk menyesuaikan kebijakan. Kepemimpinan di tingkat menengah memang kerap diibaratkan sebagai api kecil yang bisa menyalakan bara perubahan di seluruh organisasi.
Aspek keenam adalah memperluas perspektif melalui pembelajaran eksternal dan kolaborasi lintas-organisasi. Banyak inisiatif keberlanjutan di perusahaan berhenti karena terjebak pada pandangan sempit, seolah-olah hanya bisa belajar dari dalam. Padahal, di luar sana, banyak perusahaan dan komunitas telah menemukan cara-cara inovatif untuk menyeimbangkan profit dan purpose—atau lebih tepatnya mendatangkan profit lewat bisnis yang purpose-driven. Manajer madya dapat menjadi jembatan pengetahuan dengan menginisiasi kegiatan benchmarking, kemitraan, atau bahkan proyek kolaboratif lintas-perusahaan, lintas-industri, bahkan lintas-sektor.
Keterlibatan dalam forum keberlanjutan, seperti Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) atau Global Compact Network Indonesia, serta forum intra-industri, bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga memberi legitimasi tambahan untuk menggerakkan perubahan di dalam perusahaan. Saat manajer madya menunjukkan bahwa aspek-aspek mereka sudah ditunjukkan berhasil di perusahaan atau organisasi lain, juga sejalan dengan praktik terbaik global, argumen bahwa itu tidak realistis di Indonesia perlahan kehilangan kekuatannya.
Akhirnya, aspek ketujuh, yang menurut saya sangatlah penting, adalah mengelola komunikasi keberlanjutan dengan kecerdasan naratif. Banyak ide perubahan gagal berkembang lebih lanjut karena disampaikan dengan cara yang tidak tepat atau ‘keterlaluan’—terlalu teknis, terlalu moralistik, terlalu menunjuk keberhasilan atau terlalu jauh dari realitas keseharian bisnis. Manajer madya perlu menjadi pencerita yang mampu menjembatani bahasa emosi generasi muda dan bahasa analitik yang dipakai manajemen puncak.
Cerita yang menghubungkan tindakan kecil dengan dampak besar selalu memiliki kekuatan luar biasa. Misalnya, kisah tentang sekelompok pekerja muda yang menemukan cara kreatif mengurangi limbah di pabrik dengan segala segi perjuangan mereka akan lebih menggugah daripada sekadar laporan tebal dan teknis tentang limbah itu sendiri. Ketika keberlanjutan diceritakan sebagai perjuangan kolektif para pekerja perusahaan yang penuh makna, bukan sekadar serangkaian KPI, seluruh organisasi akan merasa menjadi bagian darinya. Laporan teknis tetap diperlukan, tetapi komunikasi keberlanjutan bukanlah sekadar membuat dan mengirimkan laporan itu.
Perancang Pergeseran Paradigma
Dalam keseluruhan proses ini, manajer madya perlu menyadari satu hal penting: mereka bukanlah sekadar ‘penyambung lidah’ dua generasi, tetapi merupakan perancang pergeseran paradigma. Kelembaman manajemen puncak tidak selamanya berarti penolakan. Sering kali itu adalah sinyal ketidaksiapan dan kekhawatiran menghadapi kompleksitas baru. Sementara desakan generasi muda, jika diarahkan dengan empati dan struktur, bisa menjadi bahan bakar transisi. Dengan memainkan peran sebagai penghubung—yang berpikir strategis seperti manajemen puncak namun berempati seperti generasi muda—para manajer madya dapat membangun jembatan yang kuat menuju organisasi yang benar-benar berkelanjutan.
Keberlanjutan bukan revolusi instan, seperti pesan terpenting John Elkington dalam Cannibals with Forks. Dalam metafora Elkington, untuk membuat seorang kanibal berhenti memakan manusia lain, kita perlu mengajarinya makan dengan garpu terlebih dahulu, baru kemudian mengganti apa yang mereka makan. Keberlanjutan perusahaan adalah evolusi kesadaran yang membutuhkan pemimpin-pemimpin di setiap lapisan organisasi. Jika manajer madya mampu mengubah tekanan dari dua arah itu menjadi energi konstruktif, mereka tidak lagi merasa terjepit. Mereka akan merasa berada di tengah jembatan yang menghubungkan berbagai sisi. Bukan hanya antara manajemen puncak dan pekerja muda, melainkan juga antara masa lalu yang ragu dan masa depan perusahaan yang benar-benar berkelanjutan.
Editor: Abul Muamar
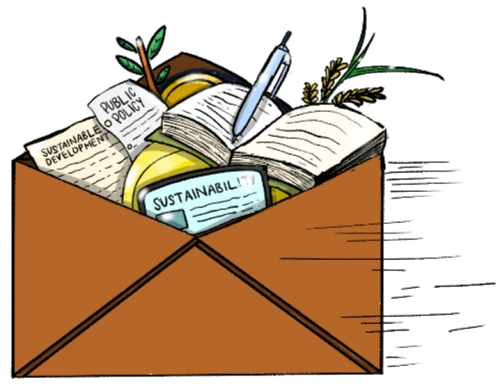
Join Membership Green Network Asia – Indonesia
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Join SekarangJalal is a Senior Advisor at Green Network Asia. He is a sustainability consultant, advisor, and provocateur with over 25 years of professional experience. He has worked for several multilateral organizations and national and multinational companies as a subject matter expert, advisor, and board committee member in CSR, sustainability, and ESG. He has founded and become a principal consultant in several sustainability consultancies as well as served as a board committee member and volunteer at various social organizations that promote sustainability.


 Mengatasi Penumpukan Limbah Elektronik di Batam
Mengatasi Penumpukan Limbah Elektronik di Batam  Pentingnya Rencana Pemulihan Bencana untuk Satwa Liar
Pentingnya Rencana Pemulihan Bencana untuk Satwa Liar  Bagaimana Bencana Ekologis Mempercepat Kepunahan Satwa Liar
Bagaimana Bencana Ekologis Mempercepat Kepunahan Satwa Liar  Menghidupkan Kembali Sungai-Sungai yang Tertimbun dengan Daylighting
Menghidupkan Kembali Sungai-Sungai yang Tertimbun dengan Daylighting  Menilik Simpul Antara ‘Gajah Terakhir’ dan Banjir di Sumatera
Menilik Simpul Antara ‘Gajah Terakhir’ dan Banjir di Sumatera  Meningkatnya Angka Pengangguran Sarjana dan Sinyal Putus Asa di Pasar Kerja Indonesia
Meningkatnya Angka Pengangguran Sarjana dan Sinyal Putus Asa di Pasar Kerja Indonesia