Mendengarkan Wisik dari Bukit Pnyx: Meretas Jalan Demokratis di Tengah Polikrisis
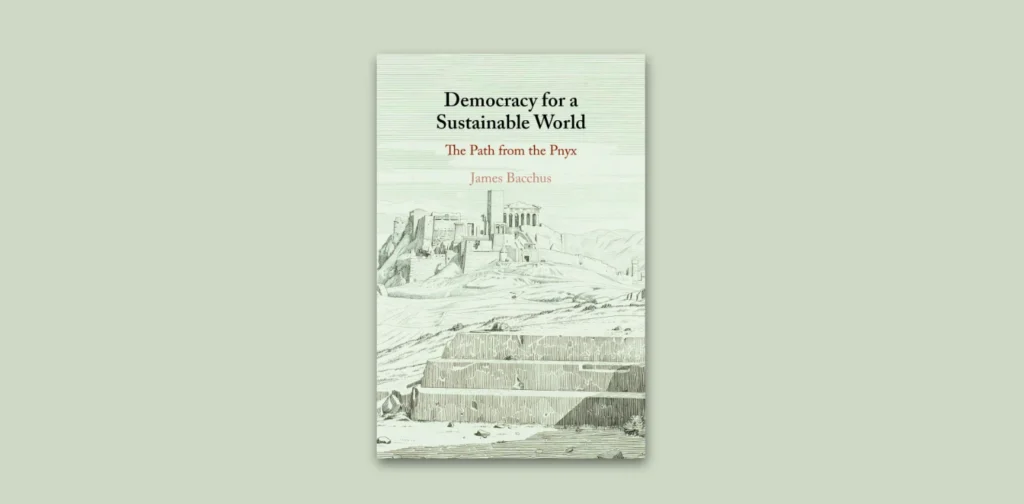
Foto: Cover buku Democracy for a Sustainable World: The Path from the Pnyx, James Bacchus. | Penerbit: Cambridge University Press (2025).
Ada sebuah bukit berbatu di Athena, tidak seberapa jauh dari keramaian turis di Akropolis, yang kini sering kali sunyi, hanya dikunjungi oleh angin dan segelintir peziarah masa lalu yang tahu apa yang mereka cari. Tempat itu bernama Pnyx. Di sinilah, dua setengah milenia yang lalu, eksperimen paling berani dalam sejarah peradaban manusia berlangsung: demokrasi. Bukan demokrasi dalam bentuk kertas suara yang kita coblos empat atau lima tahun sekali, melainkan demokrasi yang hidup, bising, dan menuntut kehadiran penuh fisik dan mental.
Di tengah krisis eksistensial yang kita hadapi hari ini—apa yang oleh para sejarawan masa depan mungkin akan disebut sebagai Abad Keruntuhan—kesunyian Pnyx terasa seperti sebuah bisikan dari masa lalu. Sebuah pesan bahwa kita sesungguhnya bisa memilih untuk tidak runtuh, melainkan sintas.
Di Tepi Jurang Otoritarianisme
Dunia kita jelas sedang sakit. Dan ini bukanlah metafora. Kita memang hidup relatif lebih sejahtera dibandingkan generasi lampau, namun sesungguhnya terperangkap dalam polikrisis: planet yang terus memanas dengan kecepatan mengerikan, pandemi yang mengintai di balik pintu laboratorium dan pasar hewan, serta ketimpangan ekonomi yang mencabik tenun sosial kita, diperparah oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan tanpa rem sama sekali.
Alih-alih bersatu, respons kolektif kita justru terpecah. Di seluruh dunia, dari Budapest hingga Brasilia, dari Moskow hingga sebagian sudut Washington DC, kita menyaksikan kebangkitan kembali hantu otoritarianisme. Narasi yang mereka jual memikat ratusan juta atau bahkan miliaran orang: bahwa demokrasi terlalu lamban untuk menangani krisis; bahwa parlemen hanyalah tempat bicara tanpa aksi; dan bahwa yang kita butuhkan adalah ‘orang kuat’ yang bisa membereskan segalanya dengan satu jentikan jari.
Namun, godaan untuk menyerahkan kebebasan demi keamanan semu ini adalah sebuah jebakan maut. Sejarah mengajarkan kita bahwa rezim otoriter mungkin efisien dalam membangun penjara atau menyensor dunia maya, tetapi mereka sangat buruk dalam mengelola ekosistem yang kompleks. Mereka tidak memiliki mekanisme umpan balik; mereka membungkam pembawa pesan buruk (seperti para ilmuwan iklim atau jurnalis lingkungan), dan akibatnya, mereka buta terhadap bencana yang mendekat. Sampai semuanya terlambat.
Mempertahankan demokrasi, dengan demikian, bukan lagi sekadar soal mempertahankan hak-hak sipil abstrak. Bagi saya ini adalah soal biologi dasar. Ini adalah soal bertahan hidup. Jika kita kehilangan kemampuan untuk berbicara, berdebat, dan memutuskan nasib kita sendiri secara kolektif, kita juga kehilangan satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan Bumi dari kita sendiri.
Harapan dan Imajinasi James Bacchus
Dalam buku terbarunya yang ambisius dan sangat provokatif, Democracy for a Sustainable World: The Path from the Pnyx, James Bacchus mengajak kita melakukan perjalanan intelektual yang melintasi waktu dan ruang. Bacchus bukanlah seorang anarkhis yang berteriak di jalanan; dia adalah bagian dari elite global itu sendiri—mantan anggota Kongres AS dan, yang lebih penting, mantan ketua Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO). Latar belakang ini memberikan bobot yang mengejutkan pada argumennya-argumennya. Ketika seorang ‘orang dalam’ mengatakan bahwa sistem yang dibangunnya itu telah rusak, kita sebaiknya mendengarkan.
Bacchus memulai dengan diagnosis yang tajam terhadap apa yang ia sebut sebagai ‘Sistem Westfailure’ (sebuah permainan kata dari Sistem Westphalia yang mendasari hubungan internasional modern). Sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648, dunia diatur berdasarkan kedaulatan mutlak negara-bangsa. Masalahnya, karbon dioksida tidak membawa paspor dan tak butuh visa. Virus tidak berhenti di pos perbatasan antar-negara. Pasar finansial bergerak dalam hitungan nanodetik melintasi samudra. Bacchus bilang, kita mencoba mengelola masalah-masalah abad ke-21 yang saling terhubung dengan perangkat lunak politik abad ke-17 yang usang. Institusi seperti PBB dan WTO, menurut Bacchus, lumpuh karena mereka dirancang untuk melayani kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat apalagi Bumi. Mereka menderita defisit demokrasi yang akut, lantaran demos, rakyat, tak benar-benar punya kuasa. Saya menarik nafas dalam-dalam ketika membaca analisis Bacchus ini, dan mengamini sepenuhnya.
Solusi yang ditawarkan Bacchus adalah kembali ke Pnyx, tetapi dengan sentuhan futuristik. Dia tidak menyarankan kita semua berkumpul di bukit di Yunani, melainkan mengadopsi prinsip inti demokrasi Athena yang telah lama kita lupakan: sortisi atau pemilihan acak.
Bagi telinga modern yang terbiasa dengan pemilu, ide ini mungkin terdengar gila. Memilih pemimpin secara acak? Seperti lotre? Namun, Bacchus mengingatkan kita bahwa bagi orang Yunani kuno, pemilu dianggap terlampau aristokratis lantaran cenderung memenangkan mereka yang kaya, terkenal, atau pandai bicara, sedangkan undian adalah satu-satunya cara yang benar-benar demokratis. Dengan sortisi, atau biasa juga disebut lottokrasi, setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk melayani kepentingan publik. Ini menghilangkan pengaruh uang dalam politik, mematahkan polarisasi partai, dan menciptakan badan perwakilan yang benar-benar mencerminkan wajah masyarakat—secara harfiah, sebuah mikrokosmos dari demos.
Dan itu bukan diusulkan untuk level negara atau daerah. Buku ini mengajukan cetak biru reformasi tata kelola global yang radikal. Bacchus membayangkan pembentukan majelis warga global sebagai dewan penasihat dalam struktur organisasi internasional. Bayangkan sebuah dewan di WTO yang anggotanya bukan diplomat karier, melainkan 500 orang yang dipilih secara acak dari seluruh dunia—petani dari Indonesia, guru dari Nigeria, perawat dari Norwegia, dll. Tugas mereka adalah membawa akal sehat dan pengalaman hidup nyata ke dalam ruang-ruang teknokratis global yang sering kali terputus dari realitas di level tapak.
Lebih jauh, Bacchus memperluas definisi demokrasi, dengan cara melampaui manusia yang hidup saat ini. Ia mengajukan argumen etis yang kuat untuk memasukkan suara masa depan dan suara alam ke dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Melalui perwakilan atau proksi yang dipilih secara acak, yang dimandatkan secara khusus untuk bertindak sebagai wali bagi generasi yang belum lahir dan bagi ekosistem yang tidak bisa berbicara. Ini adalah upaya untuk melembagakan pandangan jangka panjang ke dalam sistem politik yang secara patologis terobsesi dengan jangka pendek.
Bacchus juga menekankan bahwa struktur global ini tidak boleh menggantung di awan, apalagi di langit. Ia harus berakar pada demokrasi polisentris—jaringan ribuan inisiatif keberlanjutan lokal yang sudah ada. Dari komunitas pengelola hutan adat hingga koperasi energi surya perkotaan, yang menurut dia adalah laboratorium demokrasi yang sesungguhnya. Tugas tata kelola global adalah menghubungkan titik-titik ini, memberi mereka suara, dan meningkatkan skala keberhasilan mereka, bukan mendikte dari atas. Saya sangat terpikat pada ide ini. Tetapi, siapa yang tidak? Kalau mendambakan kuasa rakyat, keadilan dan keberlanjutan, pastilah kita mendukung Bacchus.
Berdiri di antara Visi dan Realitas
Membaca kitab ini terasa seperti menemukan oase yang jernih di tengah gurun keputusasaan politik. Kekuatan terbesar buku ini terletak pada keberanian imajinasinya. Saat sebagian besar literatur hubungan internasional terjebak dalam reformisme yang membosankan—sedikit penyesuaian tarif di sana, sedikit amandemen perjanjian di sini—Bacchus berani membongkar fondasi rumah itu sendiri. Ia berhasil meyakinkan pembaca bahwa krisis ekologi dan krisis demokrasi adalah satu dan sama; kita tidak bisa menyelesaikan perubahan iklim dengan sistem yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional yang sempit, apalagi kini makin kerap dipersempit untuk melayani kelindan kepentingan elite ekonomi dan politik.
Gaya penulisan Bacchus, yang memadukan hukum internasional, sejarah klasik, dan etika moral, sangatlah memikat. Ia menghidupkan kembali konsep sortisi bukan sebagai relik sejarah, melainkan sebagai teknologi politik canggih yang siap pakai. Idenya tentang perwakilan alam dan masa depan adalah kontribusi filosofis yang brilian, walau bukan kali pertama saya dengar, mengubah konsep abstrak keadilan antargenerasi menjadi prosedur birokrasi yang dapat dibayangkan.
Namun, di sinilah juga letak kelemahan—atau mungkin tragedi—dari argumen Bacchus: jurang antara apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Ada kenaifan dalam keyakinannya bahwa kekuatan logika dan moralitas dapat menembus tembok tebal realpolitik. Bayangkan saja skenario berikut: Bacchus mengusulkan agar negara-negara adidaya—Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia—secara sukarela menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kepada majelis warga global yang dipilih secara acak. Dalam iklim geopolitik yang memanas saat ini, di mana ketegangan antarnegara memuncak dan nasionalisme proteksionis terus naik daun, proposal ini terasa seperti mimpi yang keterlaluan indahnya di siang bolong.
Apakah para elit Washington DC, Beijing, dan Moskow bakal menerima keputusan yang dibuat oleh seorang nelayan yang terpilih secara acak dari Bangladesh atau Maladewa hanya karena prosesnya memang lebih demokratis? Apalagi, mereka jelas bakal menuding emisi tinggi dari negara-negara adidaya itu sebagai biang keladi kesengsaraan masyarakat seperti mereka di seluruh dunia. Kemungkinan besar tidak. Saya merasa Bacchus kurang memberikan peta jalan taktis tentang bagaimana memaksa atau membujuk para pemegang kekuasaan ini untuk melepaskan cengkraman mereka. Dia seperti membangun katedral yang indah, tetapi ‘lupa’ merancang jembatan untuk menyeberangi parit berisi buaya dan piranha yang mengelilinginya.
Selain itu, ada tantangan logistik yang sangat besar dalam skala global. Sortisi bekerja dengan baik di Athena kuno atau di majelis iklim tingkat kota di Prancis, tetapi bagaimana mengelolanya di tingkat global dengan hambatan bahasa, budaya, dan pendidikan yang ekstrem? Risiko bahwa majelis semacam itu akan dimanipulasi oleh politisi, teknokrat, atau ahli yang ditugaskan membantu mereka, juga tidak bisa diabaikan. Kita baru saja menyaksikan COP30 yang dibajak para pelobi industri bahan bakar fosil, dengan hasil yang bakal membuat atmosfer terus memanas beberapa dekade mendatang.
Membaca Bacchus dari Nusantara
Bagi pembacanya di Indonesia, buku ini mendarat dengan resonansi dan urgensi. Indonesia adalah garis depan dari pertarungan yang digambarkan Bacchus: sebuah demokrasi muda yang riuh—atau bahkan ricuh—bergulat dengan warisan otoritarianisme, sekaligus sebuah negara kepulauan yang berada di rahang buaya dan harimau krisis iklim. Banjir besar di Sumatera adalah pengingat bahwa deliberasi soal keberlanjutan yang benar-benar memihak rakyat itu adalah kebutuhan nyata dan perlu ditegakkan sekarang juga.
Buku ini, bagi saya, menawarkan bahasa baru untuk mengkritik kemacetan politik. Di Indonesia, kita sering terjebak dalam sinisisme bahwa politik hanyalah permainan elite partai. Konsep sortisi yang diusung Bacchus bisa menjadi inspirasi radikal untuk reformasi di tingkat desa, kabupaten/kota, atau bahkan provinsi. Bayangkan jika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak hanya dihadiri oleh pejabat dan tokoh masyarakat, tetapi oleh warga biasa yang dipilih melalui undian—seorang ibu rumah tangga, seorang petani, seorang mahasiswa, dll. Ini bisa menjadi cara untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang sering kali hanya menjadi jargon, mengubahnya menjadi partisipasi politik yang nyata dan bebas dari politik uang.
Bacchus juga memberikan argumen ampuh untuk melawan narasi pembangunan yang destruktif. Kita sering mendengar dalih bahwa demokrasi menghambat investasi atau kita butuh pemimpin kuat untuk membangun infrastruktur. Bacchus menunjukkan dengan data dan argumen bahwa jalan pintas otoriter adalah jalan menuju neraka ekologis. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kecerdasan kolektif yang hanya mungkin muncul dari musyawarah yang bebas. Pembaca Indonesia, terutama para aktivis, akademisi, dan pembuat kebijakan, dapat menggunakan buku ini sebagai amunisi intelektual untuk menuntut agar proyek-proyek strategis nasional melibatkan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar sosialisasi satu arah, seperti yang selama ini jadi moda dominan.
Terakhir, dalam kancah diplomasi global, Indonesia sering memposisikan diri sebagai jembatan. Buku ini, menurut saya, menantang Indonesia untuk menjadi lebih dari itu: menjadi arsitek. Sebagai negara yang memegang kepemimpinan strategis di ASEAN dan suara penting di G20, diplomat Indonesia harus mulai menyuarakan reformasi struktural yang diusulkan Bacchus. Kita harus menuntut agar institusi global tidak lagi hanya menjadi klub eksklusif negara-negara kaya, tetapi membuka pintu bagi suara-suara yang selama ini dibungkam—suara dari pulau-pulau kecil yang akan tenggelam, dan suara dari hutan hujan tropis yang menjadi penyedia oksigen dan keanekaragaman hayati bagi dunia.
Karya Bacchus ini perlu kita baca sebagai sebuah undangan. Ia mengajak kita untuk tidak menyerah pada kebuntuan politik dan keputusasaan sosial, untuk berani membayangkan bahwa cara kita mengatur dunia saat ini bukanlah satu-satunya cara yang ada. Bahwa di balik kakofoni politik hari ini, kita masih bisa mendengar suara dari Pnyx, membisikkan kemungkinan dunia yang lebih adil dan hijau, jika saja kita berani mendengarkan dan mewujudkan pesannya.
Editor: Abul Muamar

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.


 Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan
Bagaimana Perilaku Manusia Menjadi Mesin Utama Aksi Keberlanjutan  Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut
Meningkatkan Peran Komunitas Lokal dalam Mengatasi Masalah Sampah Laut  Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data
Menilik Dampak Masifnya Pembangunan Pusat Data  Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara
Menyoal Biaya Visum Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Ditanggung Negara  Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh
Memprioritaskan Pembiayaan untuk Alam demi Ekosistem yang Sehat dan Tangguh  Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia
Menilik Arah Baru Kebijakan Pariwisata Indonesia